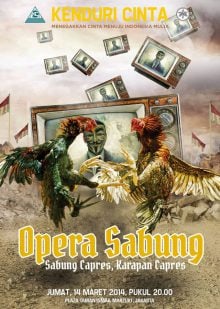Membebaskan Diri dari Ego Kesalehan
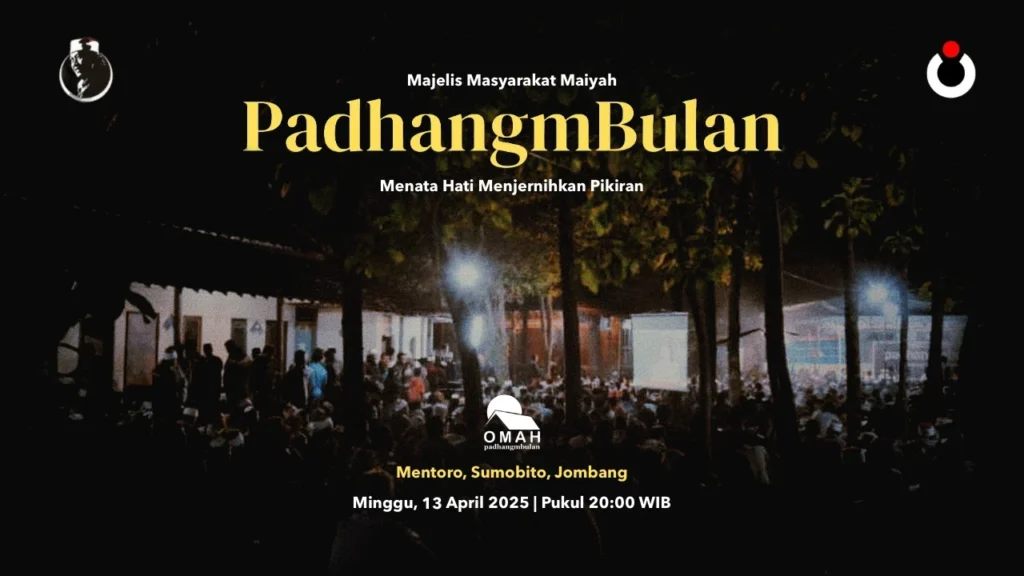
“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia salat.” (Q.S. Al-A’la: 14-15)
Ayat ini sering kita gunakan untuk “melegitimasi” keberhasilan setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Kita percaya diri dan gedhe rumangsa saat mengumumkan bahwa 1 Syawal adalah hari kemenangan.
Konstruksi keagamaan yang populer menyatakan bahwa ketaatan seseorang identik dengan salat tepat waktu, membayar zakat fitrah, melaksanakan puasa Ramadan. Kalau ukuran ketaatan terletak pada salat, zakat, atau puasa yang telah selesai dikerjakan, kita memang berhasil mengerjakannya. Namun, keberhasilan itu apakah membuahkan prestasi?
Kata aflaha (beruntung/sukses) dalam ayat tersebut tampak bersifat preskriptif atau final. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apa itu aflaha? Apakah seseorang otomatis “berprestasi” dan meraih kemenangan hanya karena telah menunaikan salat, zakat, puasa?
Tindakan tazakka dan shalla bisa menjadi simbol ketaatan yang hampa apabila dijalankan tanpa kesadaran batin. Keduanya hanya menjadi rutinitas formal dan sebatas menggugurkan kewajiban tanpa terjadi transformasi yang membawa manfaat pada kehidupan sosial.
Kata tazakka menyimpan makna ganda. Pertama, menunjuk pada zakat fitrah — tindakan ekonomi yang konkret dan kasatmata; kedua, tazkiyah al-nafs, penyucian jiwa, proses batin yang tidak kasat mata.
Ambiguitas ini menimbulkan pertanyaan: apakah kita otomatis “suci” setelah memberikan sekantong beras kepada fakir miskin? Apakah jiwa kita langsung meraih kesucian saat melakukan tazkiyah al-nafs? Atau kita justru berpura-pura suci dan menampilkan diri sebagai manusia suci?
Apakah penyucian diri cukup dilakukan secara tekstual-syariat, ataukah ia bersifat transformatif melalui upaya yang terus-menerus dalam memberikan manfaat pada lingkungan di sekitar kita? Sehingga upaya transformatif menyucikan diri berbuah prestasi secara sosial?
Kita sangat mudah terjebak pada kenyataan bahwa “orang yang menyucikan diri” adalah orang yang merasa telah suci sehingga terperangkap oleh ego kesalehannya sendiri.
Alih-alih mengikuti tren beragama yang dibelenggu oleh ego kesalehan yang sepihak dan otoritatif, kita dapat mengajukan pertanyaan reflektif untuk diri sendiri. Apakah tazkiyah al-nafs yang aku lakukan berbanding lurus dengan kemanfaatan sosial—ataukah aku hanya sedang menampilkan kesucian?
Apa makna “keberuntungan” bagi diriku ketika dunia sedang dipenuhi ketimpangan sosial, politik, ekonomi? Benarkah merasa diri suci adalah tiket untuk meraih aflaha? Bagaimana jika merasa suci itu justru membutakan mata?
Selanjutnya, surat Al-A’la ayat 15 secara gramatikal menampilkan urutan zikir terlebih dahulu lalu salat. Banyak dari kita “menemukan” Tuhan saat tidak sedang menjalankan kewajiban ritual yang terjadwal, tetapi ketika mengalami kegagalan, keterpurukan, atau kehilangan. Bisa jadi hubungan antara zikir dan salat bukan sebab-akibat yang linier-mekanis, melainkan refleksi timbal balik dari pengalaman eksistensial yang getir.
Salat bukan sekadar kewajiban, tapi permohonan diam-diam dari hati yang tidak tahu lagi harus berbuat dan berkata apa di hadapan Allah SWT. Zikir bukan lagi mengulang-ulang lafaz, melainkan jeritan terpendam dari kegelisahan yang tak pernah reda.
Jadi, kewajiban ritual bukan hanya beban yang dilegalkan oleh hukum fikih, tapi ruang reflektif dan transformatif yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban menyerahkan beras kepada fakir miskin, tetapi kesanggupan melepaskan ego, menanggalkan rasa kepemilikan, dan meluruhkan dominasi kesombongan. “Aku bukan tuan atas dunia ini, bahkan bukan atas diriku sendiri.”
Salat menjadi titik temu antara yang fana dan yang transenden — momen hening saat kita mengemis kepada Allah SWT, karena kita tidak tahu dan tidak memiliki apa-apa. Dan dari pengakuan itu makna reflektif dan tindakan transformatif mulai tumbuh.
Kandungan surat Al-A’la ayat 14-15 tidak mengajarkan klaim status kesalehan. Maka, seseorang yang merasa “sudah suci” sejatinya sedang memasuki wilayah kesombongan. Klaim otoritatif sebagai “hamba yang baik” adalah narasi yang rapuh. Ia bisa runtuh kapan saja di hadapan kejujuran dirinya sendiri.