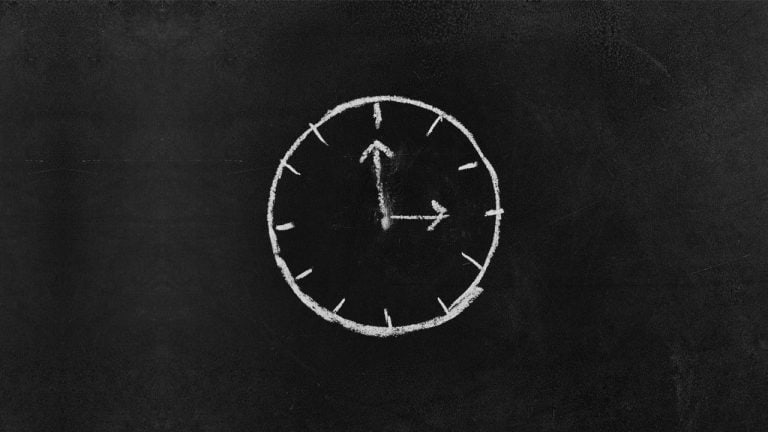Tlethong Bulan Purnama

Udara dingin Sumobito perlahan menusuk kulit tatkala sekelompok pemuda ingusan duduk di pinggir jalan yang hening sepi. Gelap. Pandangan mata hanya terbantukan cahaya bulan purnama. Tak ada satupun dari mereka yang mengenakan jaket.
Waktu sudah lewat tengah malam. Hampir satu jam mereka menanti. Berharap ada mobil pikap atau truk yang lewat dan bisa dengan senang hati atau terpaksa untuk ditumpangi gratis. “Nggandhol” istilahnya.
Para pemuda ingusan itu sebelumnya sudah nggandhol pikap dari Menturo, tempat acara pengajian Padhangmbulan. Tapi pikap yang digandholi itu tidak melewati tujuan mereka ke Pasar Peterongan. Melainkan berlawanan arah menuju Sumobito dan bablas ke Mojoagung. Nggandhol pikap tadi sudah lumayan daripada jalan kaki tengah malam bergelap-gelap ria 3 kilometer dari Menturo ke jalan raya Peterongan-Sumobito.
Rasa kantuk sudah mulai menggerogoti mata mereka. Daripada menunggu seolah tanpa harapan dan mengantuk, lebih baik jalan saja, pikir mereka. Tapi mau jalan ke Peterongan masih 6 kilometer. Para pemuda ingusan ini masih bertekad untuk nggandhol daripada kelelahan jalan kaki. Mereka gamang. Mau jalan atau tetap menanti sembari sesekali menyaksikan kereta api dari Surabaya atau sebaliknya yang melewati rel di samping jalan.
Di tengah kegamangan itu mereka sedikit menyesal. Mengapa tadi tidak ikut pikap yang ke Mojoagung. Karena di sana jalan lintas utama. Sudah tentu ramai dan banyak truk yang bisa digandholi. Walaupun itu berarti harus melalui jalur memutar menjauh dulu jika mau ke Peterongan. Tapi itu lebih mending ketimbang menanti di jalan sepi ini.
Salah satu di antara mereka yang jam terbang nggandholnya di wilayah ini lebih tinggi, memberi usul untuk jalan ke arah Sumobito saja. Lalu menunggu di pertigaan. Katanya, peluang cari gandholan truk dari Lamongan yang mau ke Mojoagung lebih terbuka. Mereka pun sepakat, berjalan kaki 2 kilometer menuju Pasar Sumobito.
Benar saja, setibanya di sana, banyak truk lewat jalan Kesamben-Sumobito ini yang menuju Mojoagung. Tapi sayang seribu sayang, saat truk dicegat, tidak ada satupun yang berhenti dan mau mengangkut mereka.
Rasanya waktu sudah hampir masuk waktu fajar. Tubuh mereka sudah lelah. Sedangkan pagi-pagi sekali mereka sudah harus tiba di Peterongan. Karena jika telat, sesuatu yang tidak mengenakkan akan mereka alami.
Harapan mereka sudah menipis. Mau tidak mau, terpaksa mereka ambil keputusan balik jalan kaki, walau harus menempuh 10 kilometer. Ya sudah, bismillah.
Ternyata Allah masih menyayangi mereka. Belum terlalu jauh berjalan, di depan Puskesmas Sumobito, perlahan melintas dari belakang menuju arah Peterongan, sebuah truk Fuso bak kayu. Dengan sigap mereka menyetop. Dan syukur alhamdulillah, kali ini pengemudi truk dengan sangat senang hati berhenti dan mengangkut mereka.
“Peterongan Cak!!” teriak para pemuda.
“Munggaho rek!!” sahut pak supir.
Tanpa babibu, lalu dengan penuh girang, lincah, cekatan, para pemuda ingusan itu memanjat bak truk. Mereka melompat masuk bak dan cretttt… kaki mereka mendarat di atas sesuatu yang hangat lembut agak lengket. Mereka tidak bisa melihatnya karena bak truk itu gelap. Apakah itu gerangan? Sesaat kemudian, mereka melihat di kejauhan, tampaknya truk akan melewati persimpangan yang di atasnya tergantung lampu. Maka jawaban atas kegelapan itu akan tampak di sana.
Sambil menunggu truk melintasi lampu, mereka sadar ada penumpang lain di dalam bak. Penumpang itu hanya bergerak-gerak, tak banyak bicara. Para pemuda yang sedang dalam keadaan hampir putus asa tadi, masa bodoh saja. Karena yang penting sekarang sudah dapat gandholan dan tak perlu payah jalan jauh ke Peterongan.
Akhirnya, tibalah moment of truth. Sampai juga di titik terang. Dan keterangan cahaya sungguh mengagetkan mereka. Penumpang selain mereka kini tampak jelas dan nyata. Mereka shock. Bahwa mereka kini nggandhol truk bermuatan sapi. Dan sesuatu yang lembut mesra sebelum cahaya, yang mereka injak tadi, adalah ceceran tai-tai sapi.

***
Saya termasuk salah satu dari pemuda ingusan yang menginjak tlethong itu. Sudah kepalang tanggung, kami tidak bisa menghindar. Dan akhirnya sampai juga di Peterongan. Perut kami keroncongan. Shalawat tarhim menggema. Sebentar lagi subuh. Kami sempatkan makan nasi bali dulu di warung langganan sebelum sholat subuh di Masjid Peterongan.
Usai subuh, kami pun istirahat sampai langit agak terang. Sekira pukul 6.30 kami pulang ke asrama di Pondok Tinggi Rejoso, lewat jalur tikus agar tidak diketahui satpam pondok. Sampai asrama, kami segera siap-siap masuk sekolah. Nanti di kelas, kami akan banyak tidur. Hehehe.
Situasi seperti itu merupakan gambaran rutin ketika kami mengikuti Padhangmbulan pada medio tahun 1999-2002. Kami sebagai santri Ponpes Darul Ulum Rejoso terbilang cukup sering ke sana sepanjang masa SMA. Biasanya, sejak sore pulang sekolah kami sudah keluar diam-diam ke Masjid Peterongan. Setelah magrib baru beranjak ke Menturo.
Bila Padhangmbulan tidak pas malam jumat, sudah dipastikan kami bolos ngaji malam. Untuk alasan itulah, bagi semua santri saat itu dilarang pergi ke Padhangmbulan. Bila ketahuan, akibatnya tidak main-main. Ancamannya akan dikeluarkan dari pesantren. Taruhannya adalah nama baik orang tua. Haha. Tapi namanya anak ingusan, rasanya waktu itu nekat melanggar aturan menjadi sebuah keseruan tersendiri.
Naik apa? Kalau tidak jalan kaki ya nggandhol. Hanya itu opsi yang tersedia kala itu. Mustahil kami punya kendaraan bermotor. Angkutan ke sana tidak ada saat malam. Kalaupun ada, eman uangnya. Mending buat beli rokok. Seringnya sih kami nggandhol dari pertigaan jomplangan kereta api Peterongan. Cari yang ke arah Sumobito.
Nggandhol adalah keahlian utama yang kami punya untuk traveling gratis. Pernah juga kelakon nggandhol sampai Pasuruan. Kalau diingat-ingat lagi sekarang, kami hanya berpikir kok bisa ya dulu melakukan itu.
Kalau sekarang enak, tinggal buka hape cari angkutan pakai Grab atau Gojek, langsung bisa tiba di lokasi Padhangmbulan. Dulu kadang kami harus jalan kaki lewat kampung-kampung, mulai dari Mancar belakang Pasar Peterongan terus ke utara. Pergi-pulang.
Bisa dibilang semua yang kami jalani, mulai dari informasi jadwal Padhangmbulan hingga perjalanan mengikuti pengajian, semuanya manual. Pokoknya yang kami tahu, acara itu diselenggarakan pas bulan purnama. Internet juga belum umum, apalagi sampai dalam genggaman hape seperti sekarang.
Apa yang kami, pemuda ingusan ini, cari di sana, tak lebih dari keseruan. Sebagian besar isi yang disampaikan Cak Nun dan Cak Fuad waktu itu belum kami pahami sepenuhnya. Yang jelas, acaranya seru, lucu penuh tawa, plus musik KiaiKanjeng. Tak heran yang datang selalu ramai.
Pengajian Padhangmbulan, begitu kami mengenalnya, terkenal setidaknya di seantero Jawa Timur. Sering saya lihat rombongan ibu-ibu datang naik Colt atau L-300 dari luar Jombang, yang di kaca depannya biasanya ditempel kertas, tertulis kota asal mereka. Blitar, Jember, Banyuwangi, Madiun, dst. Atau rombongan jamaah lain datang naik truk Mitsubishi tiga perempat.
Suasana penjaja makanan masih seperti Padhangmbulan sekarang. Ramai. Dari dulu sampai sekarang, yang tak pernah absen hanya satu: tahu solet. Dulu banyak penjual kaset KiaiKanjeng. Bahkan ada yang bajakan. Bayangkan, cuek dan asik-asik saja mereka jual kaset bajakan KiaiKanjeng di depan KiaiKanjeng pentas. Manusia Indonesia memang tiada duanya.
Di antara sekian kali kami ke Menturo pada masa pergantian abad ketika itu, selalu pas Padhangmbulan digelar. Patokannya tanggal 15 bulan hijriah, atau lihat bulan purnama. Hanya sekali kami kecelik. Saat ke sana pada tanggal itu, kok ya tidak ada pengajian Padhangmbulan.
Sebelumnya di kalangan kami, santri yang sering ke Padhangmbulan, sudah mendengar desas-desus kalau pengajian ini bubar. Kala itu, dari pemberitaan koran Jawa Pos–satu-satunya sumber informasi yang tersedia bagi santri–yang ditempel di mading, diberitakan suasana politik Jakarta yang sedang memanas. Mbah Nun juga banyak mengkritik Gus Dur yang sedang menjadi presiden. Ada ketegangan suasana politik yang membuat Mbah Nun memutuskan meliburkan Padhangmbulan.
Kami tidak tahu kepastiannya. Ya namanya belum ada website apalagi Instagram, kami tetap berangkat ke sana, berbekal sopo ngerti ono. Dan benar, ketika sampai Menturo, pengajian libur. Katanya libur tiga bulan. Banyak juga yang sudah jauh-jauh datang ke sana akhirnya hanya nongkrong-nongkrong saja. Termasuk kami, yang ketika pulang bisa numpang pikap sampai jalan raya dan akhirnya ke pondok dengan nggandhol truk sapi penuh tlethong itu.

***
Tahun ini adalah tahun ke-30 digelarnya Majelis Ilmu Maiyah Padhangmbulan. Jejak pertama kali saya ke sana pada tahun ke-6. Dan terkahir kali ke sana dua puluh tahun kemudian, pada tahun ke-26, sebelum saya pindah sementara ke Chicago.
30 tahun Padhangmbulan menjadi wadah menata hati dan menjernihkan pikiran. Padhangmbulan istiqomah diselenggarakan kakak-kakak dan adik-adik Mbah Nun, untuk melanjutkan jariyah ayah Muhammad dan ibu Chalimah, sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Dulu hanya untuk membangun masyarakat Menturo, kini membangun masyarakat Indonesia.
30 tahun pula berarti, setidaknya keluarga ini melalui Maiyah mencoba membangun manusia Indonesia. Itulah inti dari Maiyah: membangun manusia. Karena membahas konsep-konsep kehidupan setinggi apapun, konsep kenegaraan bagaimanapun canggih ndakik-ndakik-nya, percuma diterapkan kalau manusia Indonesia masih gampang dibodohi dan diadu domba serta selalu salah memilih pemimpin.[]
Pinggirsari, 30 Oktober 2023