Sembilan Putra-Putri Anugerah Tuhanku
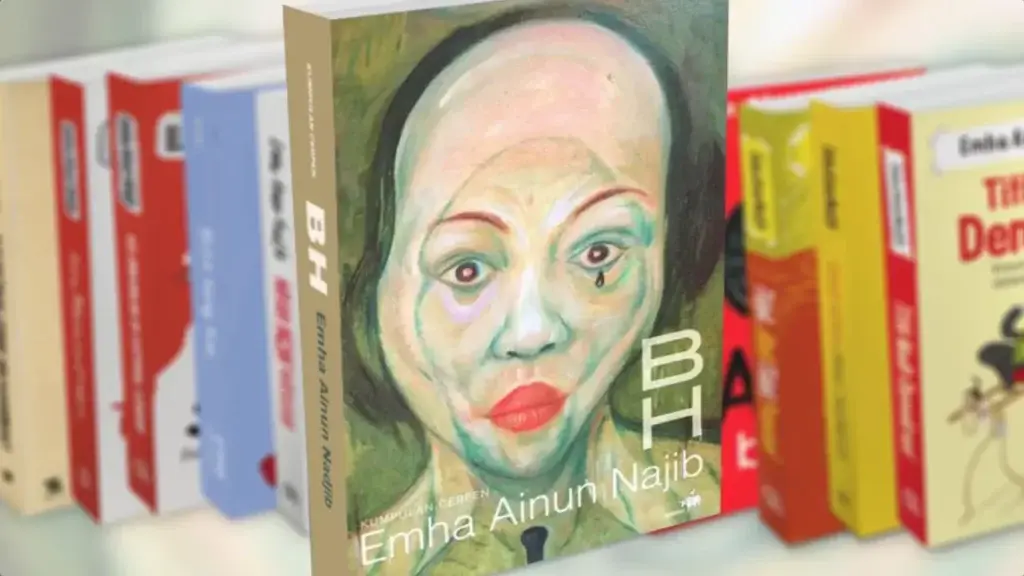
Gatot membangunkanku dengan kasar. “Pakde Budi datang!” katanya. Ia duduk di atas kedua kakiku.
“Pakde Budi?”
“Ya. Bangun dong. Sudah pukul delapan lho.”
Sudah pukul delapan?
Belum. Baru pukul delapan. Gatot tak tahu pukul berapa saya tidur. Dengan malas saya bangkit, sambil langsung saya angkat tubuh Gatot tinggi-tinggi, saya letakkan di atas almari kerja saya, ia teriak-teriak, sampai beberapa lama, baru dengan tertawa saya turunkan kembali. la memukul-mukul punggung saya kemudian menghambur ke adik-adiknya di depan.
Saya gembira. Selalu saya merasa gembira. Di dunia ini alangkah banyaknya hal-hal yang menggembirakan. Dan, kedatangan kakakku Budi ini adalah anugerah kegembiraan yang lebih mahal harganya dibandingkan kepentingan istirahatku. Kakakku Budi yang baik, satu di antara sekian miliknya yang baik, kedua orangtuaku yang baik, serta sembilan putra-putriku yang baik, meskipun mereka semua bukanlah anak-anakku.
Sehabis cuci muka, saya temui Mas Budi di ruang tengah.
“Nglembur terus?” sapanya.
Saya hanya tersenyum, sambil menyalaminya.
“Banyak order?” lanjutnya. “Ada. Tidak banyak.”
“Sebab kau tak mau banyak!”
Sekali lagi saya hanya tersenyum.
“Kau selalu begitu sih. Nggak mau maju.”
“Maju ke mana?”
“Ah kau ini!”
Kami tak akan pernah ketemu pendapat kalau sudah sampai ke soal-soal yang agak serius. Selamanya. Sejak dulu, dan saya kira sampai kapan pun. Kakakku ini tipe orang zaman sekarang. Saya kagum, tapi juga heran. Begitu tinggi cita-citanya, begitu banyak yang dimauinya. Saya kurang paham. Tanpa banyak cingcong, tanpa modal dan fasilitas yang berlebih, hidup ini tak pernah kering dari hal-hal yang menggembirakan. Kenapa begitu repot. Karena itu kakakku kemudian kuajak saja omong tentang segala sesuatu yang menyenangkan, memanggil anak-anak itu untuk bergurau tanpa pernah puas — dan bukannya berdiskusi tentang kerja, masa depan atau rencana-rencana dengan dahi berkerut.
Tetapi, siang harinya, sehabis makan siang, ia mencuri kesempatan. Sebenarnya saya sudah duga. Jauh-jauh datang dari Madiun ke Yogya, mesti ada membawa hal yang lebih dari sekadar silaturahmi.
“Serius ya ini?” tanya saya sambil tersenyum begitu ia menampakkan suatu gelagat.
Ia tertawa kecil, tapi kemudian wajahnya serius kembali.
“Payah kau ini!”
“Iya Mas. Pukul 4 pagi saya baru tidur.”
Ia keki. “Ini benar serius lho. Maksudku sampai kapan kau akan begini-begini terus?”
“Mudah-mudahan selamanya. Saya tidak mau kehilangan kegembiraan sedetik pun.”
“Aduh. Maksudku kapan kau akan lebih serius dengan usahamu. Masak dari dulu begini-begini terus. Kan tanggunganmu makin berat.”
“Tidak. Tidak berat. Tidak ada yang berat.”
“Gusti Pangeran! Kau ini….”
Saya tertawa.
“Begini deh. Saya cespleng saja. Saya ke sini sebenarnya disuruh oleh Mas Arifin. Dia sudah lama ingin sekali melihat hidupmu maju. Maju ke mana….”
Saya tertawa.
“Jangan jawab begitu. Mas Arifin sungguh-sungguh memikirkan perkembanganmu. Jalan terbuka lebar, landasan ada, modal tak sukar kau peroleh. Apa lagi? Kau tinggal tekan knop.”
“Mesin sudah berjalan baik.”
“Tapi begitu lamban, dan untuk pikiran yang dinamia usahamu ini bisa dikatakan tak berjalan. Sebenarnya kau bisa perluas toko peci-mu ini, mungkin dengan jualan barang yang lebih beragam. Juga usaha kaligrafimu itu keistimewaan besar yang sesungguhnya bisa membikinmu kaya raya.”
“Wah.”
“Jangan wah. Kau menanggung hidup sembilan orang. Dan anak-anak kecil itu makin lama makin membutuhkan biaya. Kau bisa kerepotan nantinya.”
“Kerepotan sedikit kan nggak apa-apa.”
“Kau mungkin nggak apa-apa. Tapi mereka? Jangan kau masukkan mereka dalam kesempitan cara hidupmu. Kau jangan egois!”
“Egois?”
Saya tertawa. Egois? Alangkah menyenangkannya hidup ini. Saya mungkin gila, tapi kuurusi sekian orang yang sebenarnya bukan menjadi kewajiban saya, dan untuk itu saya harus egois!
“Ya. Kau egois!”
“Baiklah. Saya egois.”
“Dan, tidak realistis!”
“O ya?”
“Orang akan menyangka bahwa kau telah dan sedang menolong keadaan. Itu benar, dari satu segi, tapi selebihnya kau sangat keliru. Kau tak mendidik secara tepat adikmu Maman. Kau terlalu memanjakannya. Kau biarkan ia kawin, tanpa pekerjaan, tanpa sikap, tanpa kedewasaan, sampai anaknya enam, dan besok tujuh dan lusa delapan! Kau- mengurusi semuanya seperti kau lah bapaknya, sementara istrimu sendiri kau korbankan. Pikirkanlah coba. Apa tidak boleh masuk akal kalau sekarang kau coba untuk perlahan-lahan melepaskan mereka agar baik Maman maupun kau sendiri bisa memulai suatu kehidupan yang realistis….”
“Mas Budi,” saya terpaksa memotongnya, “bagaimana kalau kita teruskan obrolan yang menyenangkan ini di ruang kerja saya, sambil saya bisa sedikit mengerjakan sesuatu.”
Mas Budi melengos. Tapi, kami beranjak dan masuk. Kakakku ini sungguh baik. Ia sangat memikirkan keadaan saya. Cuma barangkali kami saling tidak memahami. Seringkali orang merasa bisa memahami sesuatu, padahal sesungguhnya ia hanya memahami pemahamannya sendiri belaka. Orang melihat dan merasa telah berhasil melihat, padahal yang dicapainya hanyalah batas penglihatannya saja. Saya bukan orang yang tak bisa dipahami atau dilihat. Saya hampir tak punya rahasia. Tapi, memang tidak ada kenyataan yang tanpa rahasia. Kenyataan yang senyata-nyatanya pun sebenarnya tetap suatu rahasia, sebab setiap orang adalah orang lain bagi lainnya. Susahnya kita mesti baik dan karib satu sama lain, dan lagi sering merasa harus menjadi satu. Padahal, kesatuan itu tak pernah ada, kecuali satu dengan S besar, yang ternyata juga merupakan puncak dari segala rahasia.
Ah, kok malah berfilsafat.
“Mas Budi?”
“Ya?”
“Kalau saya senang, Mas Budi juga senang, kan?”
“Lebih dari itu. Kami semua justru selalu ingin berusaha menyenangkanmu!”
“Terima kasih. Menyenangkan sekali.”
“Begini deh. Kau pikirkan dulu baik-baik tawaran Mas Arifin itu. Saya akan keluar dulu. Tapi, kalau saya pulang nanti sore saya sudah ingin mendengar keputusanmu.”
Ia beranjak. Dan, saya meneruskan pekerjaan menulis kaligrafi saya di meja yang merupakan sahabat dari lebih 75 persen waktu saya, dan insyaallah yang akan menjadi satu-satunya saksi kematian saya nanti. Meja yang bisa mengantarkan saya ke dunia yang sesungguhnya. Meja yang tidak akan pernah bisa berkata apa-apa kepada orang lain. Juga Mas Budi.
Mas Budi. Mas Arifin. Adikku Maman. Serta siapa saja yang mencintaiku. Baiklah. Akan saya pikirkan kembali. Usia 44 tahun saya akan memikirkannya kembali. Saya sudah tua. Bahkan sejak kecil saya memang sudah tua. Sejak saya memomong Maman yang mungil, melayani segala keperluannya seperti melayani kebutuhan adik kandungku sendiri. Sejak ia bertumbuh agak besar dan melangsungkan perkawinannya yang terlampau cepat. Sejak ia membuahkan anak, satu, dua, sampai enam kini. Sejak ia tak pernah punya pekerjaan, sejak ia tiap hari minta uang saku, sejak anak-anaknya saya urus segala sesuatunya, sejak istrinya minggat karena tak tahan melihat kelakuan suaminya, sejak akhirnya perempuan itu kembali lagi untuk menolong kewajiban saya mengurusi anak-anaknya. Bahkan sejak aku kawin dan istriku menolak untuk tinggal bersama di rumah ini karena muak pada kakaknya, yakni Maman sendiri. Sejak bapak-ibu angkatku berangkat pikun karena ketuaannya. Aku sudah tua. Sehabis kecil, aku langsung tua. Bapak-ibu yang arif itu dulu memungutku, Arifin, Budi dan Maman, sehingga hanya ketuaan berikutnya yang bisa mewarisi kearifan itu. Kini Mas Arifin dan Mas Budi telah amat maju usahanya, namun biarlah aku tak usah kebagian kemajuan. Proses telah menghidupkanku, atau membunuhku. Namun, perkenankan saya memungut semua kewajiban ini untuk menjadi putra- putriku. Maman dan istrinya, 6 orang anak mereka, serta bapak dan ibu yang sudah amat sepuh. Kemudian, istriku sendiri, dan mungkin anakku, kalau akan ada. Sudah cukup banyak, bukan? Sudah cukup untuk membikin hidupku termangu-mangu di atas meja. Meja yang unik yang bisa membawaku ke segala apa pun yang membahagiakanku. Meja yang begitu kuhadapi, hilang kayu dan garisnya, menjadi ruang yang amat-amat luas sampai ke sana.
Apa lagi? Jangan tuntut saya lebih dari itu. Saya ini hanya apa adanya.
Mengorbankan istri? Saya ingat ia, seperti juga keponakan-keponakannya. Biarlah waktu mengajarinya bagaimana bisa tahan terhadap kakaknya kelak. Dan, Maman, kau kumanjakan, dik? Kaulah sendiri yang berhak dan mampu mengalami pengalaman sendiri. Dan, hanya kau sendiri pula yang bisa bergolak dari pengalaman itu, untuk menjadi baik, buruk, dewasa atau bayi. Itu hak dan kewajibanmu, dan kau pula yang akan memetik semua arti atau kesia-siaannya, sebab aku tak bisa, aku bukan kau. Selebihnya, siapa berani bilang ada kesia-siaan dalam hidup ini?
Tugas saya hanyalah mencintaimu, persis seperti saya mencintai adikmu, anak-anak kalian, istri saya serta kedua orangtua kita. Tak bisa dihitung. Cinta saya kepada putra-putri saya yang dianugerahkan Tuhan itu, tak bisa dihitung.
Mas Budi, Mas Arifin, harus berapa kali lagi saya katakan hal itu?
Yogyakarta ‘82








