Rakyat Tanpa Negara

Misalnya di bidang pertanian, orang bertanya: kenapa para petani semakin tak sanggup mempertahankan tanahnya, kenapa semakin sirna kedaulatan mereka atas penyelenggaraan benih padi, atas komoditas damen dan unsur-unsur lain di seputar padi, serta atas pengambilan keputusan terhadap harga gabah?
Pipit Kartawidjaja, saya duga, menjawab: karena para petani tidak berdomisili di wilayah kedaulatan institusi Negara dan memperoleh perlindungan dari keputusan-keputusan Negara. Para petani hidup di alamat antah berantah, berhadapan dengan ancaman Pemerintah. Pemerintah Indonesia, selama sekian kali pergantian, tak pernah mengurusi kaum tani. Konsern mereka adalah pertanian. Petani bukan subyek utama dalam dunia pertanian, sawah dan tanaman. Subjek utamanya adalah pedagang yang bernama Pemerintah, lahannya adalah tanah, budak dan pelengkap penderitanya adalah para petani.
Demikian juga kalau Anda bertanya kenapa biaya pendidikan semakin gila mahalnya, kenapa kaum pelajar dan keluarganya diperas oleh kewajiban-kewajiban tak masuk akal di bidang petualangan kurikulum, perdagangan paksa buku-buku pelajaran, pendangkalan ilmu, robotisasi murid-murid melalui sistem pengajaran — atau beratus-ratus problem pendidikan yang lain yang lebih ganas dibanding kanker paling ganas? Jawaban Pipit senada: karena Departemen Pendidikan adalah Kerajaan Dagang Pendidikan dan Menterinya adalah Raja dengan wilayah kedaulatan dan skala kedaulatan yang sangat berlebihan. Segala keputusan tentang pendidikan selalu merupakan keputusan departemental. Selalu merupakan keputusan Pemerintah. Murid-murid dan orangtua mereka adalah ikan-ikan teri yang tiap hari dimakan dalam kenduri beramai-ramai oleh boss-boss mafia perniagaan di seluruh jalur dan lini dunia pendidikan.
Silahkan pandang dan pelajari Indonesia, Anda bisa dengan sangat mudah menemukan dan mendaftari ratusan bahkan ribuan problem di seluruh bidang kehidupan. Yang tingkat keparahannya sangat tinggi. Yang kadar komplikasinya hampir seperti persoalan mistik karena sedemikian tak terurainya. Yang jangankan menemukan metoda problem-solving-nya, sedangkan merumuskannya saja pun hampir-hampir tak terkerjakan atau terjangkau oleh kumpulan segala ilmuwan yang didatangkan dari belahan dan sudut bumi sebelah manapun.
Tak usah repot-repot memilih metodologi atau menentukan terminologi, cukup bukalah saja kamus: urutlah, pada setiap kata terdapat jenis permasalahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau saya boleh mengungkapkannya dengan bahasa yang agak “pulitik”, setiap huruf mengandung ratusan problem, bahkan jumlah permasalahan Indonesia lebih banyak dibanding jumlah kata dalam kamus.
Penjelasan Pipit sangat sederhana, namun substansial dan fundamental: di dalam konstitusi Indonesia, peran Negara sudah diambil alih oleh Pemerintah hampir sepenuhnya. Ia sangat halus menyebut “tidak jelas pemilahan antara Negara dengan Pemerintah”, itu karena meskipun ia sudah hidup lebih 30 tahun di Jerman, tetap ia orang Jawa. Orang Jawa lain yang mendengarnya, yang “tanggap ing sasmita”, mengerti bahwa yang dikatakan oleh Pipit sesungguhnya adalah bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang tanpa Negara.
Konstitusi memberi ruang kekuasaan sedemikian hampir mutlak kepada Pemerintah, dalam arti kedaulatan rakyat tidak memiliki “alamat” yang jelas, yang semestinya disediakan oleh institusi Negara. Segala sesuatu yang seharusnya merupakan otoritas Negara, berada di genggaman tangan Pemerintah. Kas Negara menjadi kas Pemerintah. Saham Negara menjadi saham Pemerintah. Bank Negara menjadi bank Pemerintah. Sekolah dan Universitas Negara menjadi sekolah dan universitas Pemerintah. Sekurang-kurangnya, semua itu, berada tidak di tangan kedaulatan rakyat dalam lembaga Negara. Pegawai Negara dieufemisasikan menjadi Pegawai Negeri, dan dalam aturan maupun prakteknya adalah Pegawai Pemerintah. Pada umumnya Pegawai Negeri tidak memiliki ingatan, apalagi kesadaran bahwa mereka adalah pegawainya rakyat dalam bingkai Negara: merasa merasa dirinya adalah pegawai dan bawahannya Pemerintah.
Pipit telah membukakan jendela. Pipit telah membobol dinding pemahaman dan kesadaran nasional tentang kekhilafan mendasar dalam konstitusi kita. Pintu Pipit ini kelak akan membuat langkah kita tiba pada kesadaran dan kenyataan konstitusi di mana ada keputusan tingkat departemental, ada tingkat pucuk eksekutif, ada juga keputusan tingkat Negara — yang permanen, yang mungkin diolah melalui MPR, yang berkekuatan hukum dan mengikat pemerintah meskipun berganti setahun sekali. Entah soal pendidikan murah, perlindungan kepada tani dan buruh, kebebasan beragama, atau apapun. Setiap langkah departemental bisa dibawa naik dua tingkat hingga diabsahkan oleh MPR sebagai Keputusan Negara. Sehingga tidak setiap presiden dan menteri baru boleh bersikap seperti Tuhan dengan keputusan-keputusan yang sama sekali baru — melainkan mereka patuh kepada Keputusan Negara sebagaimana pemerintah sebelumnya maupun sesudahnya. Tentulah segala yang telah dituliskan oleh Pipit wajib diikuti oleh sambutan-sambutan pemikiran, perhitungan kembali, kritisisme, analisis dan pendalaman, oleh siapapun yang cinta kepada kebangunan kembali kehidupan bangsa dan negara Indonesia, terutama oleh para pengarif hukum dan konstitusi. Pipit tidak pasti benar dan tepat, tapi sejarah Indonesia yang semakin bangkrut sangat ditolong oleh buku Pipit ini. Tidak sekedar di wilayah ilmu yang menyangkut pembenahan mendasar konstitusi: Saya mengalami berpuluh tahun lamanya dalam pergaulan nyata, bahwa Pipit adalah seorang nasionalis sejati yang hatinya sangat berisi cinta tulus kepada negara dan bangsa yang melahirkannya.
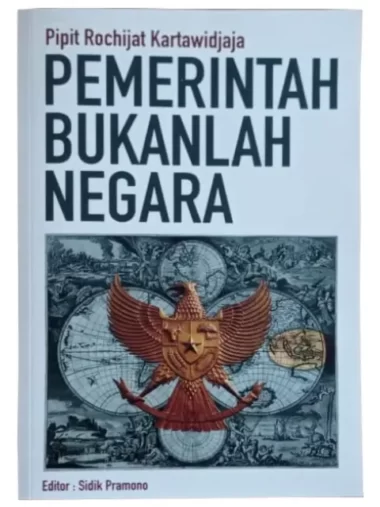
Ketika saya membuat tulisan ini, bangsa Indonesia sedang berada pada salah satu puncak krisisnya. Menjelang akhir tahun 2005, harga bahan bakar melonjak secara sangat curam, sampai ke tingkat yang secara teoritis tak akan mungkin tertanggungkan oleh sisa ketidak-berdayaan ekonomi rakyat Indonesia.
Sebenarnya identifikasi krisis yang saya maksud sangatlah jelas: bahwa bisa dikatakan tidak tersisa satu sisi kehidupan yang tak mengalami krisis, terserah Anda akan memakai teori, parameter, metodologi, terminologi — yang manapun dan mengacu pada teori ilmu yang bagaimanapun.
Dengan kata lain: krisis total. Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis total. Bahkan mungkin itu tidak cukup menjelaskan, kecuali ada idiom selain “total” yang bisa ditemukan untuk mendeskripsikan kadar krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia.
Anda tinggal menyebut kata apa saja secara bebas untuk menunjuk sisi, titik, sudut atau bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Ambil saja sekenanya: perekonomian, politik, hukum, kebudayaan, pendidikan, keamanan nasional, karakter, iman, moral, mentalitas, apapun — orang paling bodoh di antara bangsa Indonesia bisa dengan sangat mudah menjelaskan krisis apa dan bagaimana yang mereka alami di wilayah konteks yang Anda sebut.
Krisis itu sedemikian nyata dan totalnya sehingga melahirkan suatu jenis krisis baru yang ajaib: kalau Anda berada di antara bangsa Indonesia, bergaul dan bercengkerama dengan mereka, sesudah beberapa waktu Anda akan menemukan pertanyaan di dalam diri Anda: Yang mana krisisnya? Orang Indonesia selalu hangat, tertawa-tawa, tekanan-tekanan yang terkadang muncul pada ekspresi psikologis mereka tak pernah sampai pada kadar yang serius yang memungkinkan munculnya tingkat yang memadai untuk melawan keadaan, memberontak, atau apapun.
Dahsyatnya krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak berbanding lurus dengan tingkat munculnya kritisisme, progresivisme — tidak juga melahirkan rasa krisis atau “sense of crisis” yang sepadan dengan penderitaan obyektif yang sebenarnya mereka alami secara total dan mendalam.
Rendahnya rasa krisis diindikasikan tidak hanya oleh karakter kepemimpinan yang culas namun lemah namun tak tahu malu, oleh praktek kepengurusan negara yang sangat tidak memfokuskan diri pada keharusan melindungi kesejahteraan rakyat, serta oleh beribu-ribu kejadian yang mencerminkan subyektivisme dan egosentrisme kelompok-kelompok yang berkuasa.
Rendahnya “sense of crisis” itu juga tampak pada puluhan bahkan ratusan juta orang yang menderita pada kehidupan bangsa Indonesia. Tidak ada ketersambungan rasa derita satu sama lain, sehingga sesungguhnya yang berlangsung bukanlah penderitaan sosial, melainkan penderitaan individu-individu atau keluarga dan kelompok. Tidak terdapat gejala di mana keprihatinan diperkaitkan antara satu dengan lain orang, antara satu segmen masyarakat dengan segmen lain. Tidak ada organisasi orang-orang menderita. Tidak ada kesedihan dan kebingungan kolektif, yang ada adalah setiap orang memendam dan memelihara kesedihan masing-masing.
Pada sebagian tidak kecil bahkan krisis total nasional tidak membuat mereka menurunkan kadar budaya konsumerisme, hedonisme dan pesta-pesta kegembiraan — dengan berbagai formula yang berbeda sesuai dengan strata yang juga berbeda. Mal-mal dan plaza tempat jualan mitologi, mimpi dan khayalan tidak sedikit pun menurun jumlah pengunjungnya. Tayangan televisi Indonesia tetap penuh joget riang gembira dan terus menerus tak peduli siang atau malam, tetap penuh intensitas putaran modal dengan siaran-siaran hedonisme budaya dan olahraga. Industri televisi bahkan merekrut Agama, Tuhan, Nabi, Malaikat dan hantu menjadi bagian primer dari komoditas mereka. Tidak ada bangsa di dunia yang tertawa lebih banyak melebihi frekuensi tertawanya orang Indonesia. Tidak ada masyarakat di muka bumi yang kehangatan dan kegembiraan hidupnya, bahkan tingkat keberaniannya membeli ini itu, melebihi bangsa Indonesia. Bagi tradisi akal sehat konvensional: ini adalah suatu jenis krisis.
Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedemikian bodohnya sehingga tidak memiliki kemampuan identifikasi dan deskripsi atas keadaannya sendiri, termasuk atas krisis yang dialaminya sendiri, sehingga justru karena itu mereka tidak mengalami betapa dalam dan kompleksnya krisis itu. Seperti orang yang tidak paham hantu dengan konstelasinya: ia tenang-tenang saja lewat atau singgah di kuburan. Atau seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit, sehingga tidak berprihatin sedikit pun ketika di dalam badannya terdapat komplikasi penyakit yang pada suatu pagi akan membuatnya mendadak tak berdaya dan mati. Kalau orang itu mengerti hantu, maka ia akan ketakutan dan lari tunggang langgang menjauhi kuburan. Kalau orang itu memahami penyakit, maka ia akan melakukan perlawanan, pemberontakan, pengobatan dan segala daya untuk memisahkan penyakit-penyakit itu dari dirinya. Tetapi salah satu krisis bangsa Indonesia adalah bahwa mereka punya tradisi bersikap acuh tak acuh terhadap hantu dan penyakit-penyakit.
Kemungkinan lain adalah bangsa Indonesia memiliki daya tahan dan kekuatan yang tak tertandingi dan tak terpahamkan oleh bangsa dan manusia manapun yang lain di permukaan bumi. Sedemikian kuat dan kebalnya sehingga mereka tidak mengaduh ketika dipukul, karena pukulan itu tidak cukup menyakitkannya. Mereka tidak meronta-ronta ketika dijerat dan dipenjarakan, karena mereka tetap mampu membangun kemerdekaan subyektif psikologisnya di dalam penjara. Mereka tidak melawan ketika dianiaya, ditindas, disiksa, dicurangi, dibohongi — karena tingkat penganiayaan yang mereka alami belum sepadan dengan daya tahan yang mereka miliki.
Sekorup apapun pemerintahnya, tak membuat bangsa Indonesia memberontak sampai kadar yang signifikan. Sekurang ajar apapun pemimpin mereka, tak membikin mereka melakukan perlawanan. Semenderita apapun kehidupan yang menimpa mereka, tak pernah cukup mendorong mereka untuk berdiri agak sedikit tegak dan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dan primer.
Pintu yang dibukakan oleh Pipit ini, beberapa waktu yang lalu saya coba pakai untuk menjajagi kemungkinan perubahan dan sedikit mulai membalikkan arus itu. Saya ajak Pipit berkeliling ke daerah-daerah, berjumpa dengan berbagai pelaku kekuasaan untuk berdiskusi. Bahkan saya pertemukan Pipit dengan ribuan rakyat di alun-alun, lapangan-lapangan…. Dan saya berharap kesempatan seperti itu akan bisa kami lanjutkan. Karena bangsa Indonesia sungguh-sungguh berada dalam keadaan-keadaan mendasar yang tak ada kontinuasinya besok dan lusa. Dalam beberapa tahun ke depan ini harus dipastikan akan dilakukan penjebolan, perombakan dan perubahan yang habis-habisan.
Malaysia
4 Maret 2006



