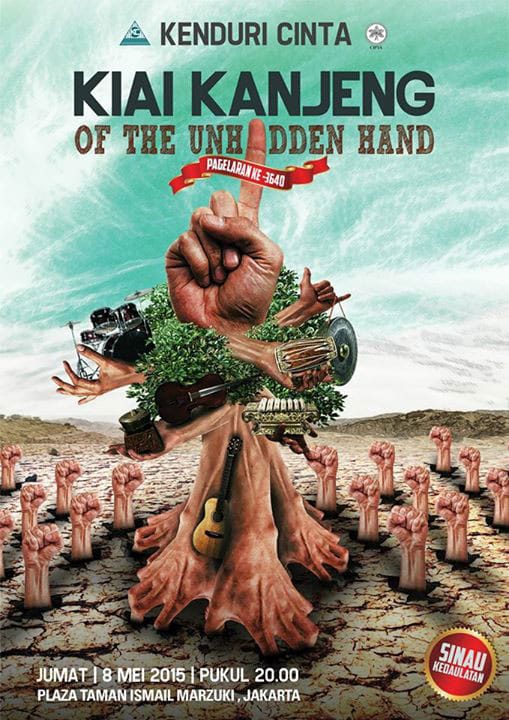Mengingat Sejarah Mocopat Syafaat dan Reformasi 1998




Ikhtiar Mbah Nun ngéman masyarakat Indonesia di huru-hara 1998 — meski kemudian ditikung oleh banyak orang — tiada berhenti, tetap berlanjut dan kian meluas mendalam. Strateginya berubah, medianya berganti. Mbah Nun mengajak dan menemani masyarakat Indonesia bershalawat, yang bermula dari Jakarta hingga ke pelosok negeri bahkan mancanegara. Acara berkeliling shalawatan yang kemudian berkembang menjadi sinau bareng atau Maiyahan merupakan wahana laku ngéman Mbah Nun hingga hari ini yang kita berada di dalamnya.
Maiyahan bukan lantas selesai di rentang “meminimalisir benturan, supaya bangsa Indonesia jangan lebih berdarah-darah lagi dan memperpanjang mati konyol”, lebih dari itu Maiyahan adalah kebun untuk ndèdèr para pejalannya. Manusia-manusianya, beserta segala dimensi kemanusiaannya, dioptimasi dan ditemani melalui sinau bareng yang semoga Allah Swt. berkenan membimbing untuk bertransformasi menjadi manusia Muhammad.
Mas Yoyok, Pak Joko Kamto, dan Pak Bobiet bergiliran menceritakan latar belakang situasi sosial kala 1998. “Kita perlu tahu betapa shalawatan di masa itu bukanlah sesuatu yang seperti sekarang ini, dulu amat jarang ada shalawatan di ruang publik di luar pengajian, sehingga yang dilakukan Cak Nun seorang diri itu adalah perjuangan,” Pak Bobiet bercerita. “Kami shalawatan di pinggir jalan, kehujanan, sementara mayoritas kami ini (Mini Kanjeng) bisa dibilang tidak tahu apa-apa soal shalawatan, kecuali Pak Nevi ya,” sambung Pak Bobiet.
Usai pakdhe-pakdhe KiaiKanjeng berkisah, sound system normal kembali. Semua perangkat elektronik dapat difungsikan. Mas Angga memanggil Resan Blues ke panggung untuk berbagi kebahagiaan. Menyusul saudaranya (Gamelan Kahuripan) pada bulan lalu, delapan pemusik berbusana serba hitam dengan aksesoris etnik memperkenalkan diri mereka ke seluruh jamaah Mocopat Syafaat. Berasal dari komunitas penggiat konservasi air di dataran karst Gunungkidul. Resan berasal dari kata “Wreksa” yang berarti “kayu” dalam bahasa Jawa Kawi, kemudian mengalami proses afiksasi: Wreksa+n. Lantas dimudahkan pelafalannya menjadi Resan. Resan Blues mengemas kampanye kepedulian terhadap alam khususnya kelestarian sumber air melalui alunan etnik blues yang berlirik Jawa.

Setelah nge-blues, jamaah diajak untuk menghadiahi Pak Mustofa W Hasyim puisi sekaligus doa. Kali ini bukan Pak Mus seorang diri yang akan berpuisi. Mas Tri Reman dan Pakdhe Maskun memandu sesi membaca puisi rusak-rusakan yang dihaturkan kepada Sang Penyair Rusak-rusakan. Puisi yang dibacakan dan cara membacakannya pun harus rusak-rusakan. Kalau tidak rusak-rusakan, harus tampil di Sastra Emha. Ada tiga orang jamaah tampil. Puisi pertama adalah puisi tiga detik-an hasil prompting AI. Disusul puisi kedua hasil olah rasa dadakan. Dipungkasi puisi ketiga yang tak kalah gayéng. Tiap puisi memicu gelak tawa pecah, menambah riang suasana. Panggung sinau bareng senantiasa menjadi altar kreativitas yang tak terduga.
Tiba waktunya untuk puncak rusak-rusakan. Pak Mus membacakan puisi yang diambil dari buku beliau yang berjudul “Perang yang Damai, 101 Puisi Mustofa W Hasyim” yang terbit tahun lalu. Buku puisi ini kemudian di-roasting beramai-ramai oleh Cak Zakki, Mas Helmi, dan para personel KiaiKanjeng. Masing-masing mengulik judul-judul dan bait-bait dalam buku. Ada judul puisi “Mengapa Ada Hujan di Musim Hujan?”, “Pohon Bambu Mengembara”, juga terdapat kalimat “…your body is my ship…”. Kata dan kalimat dibolak-balik untuk mencari maksud, meraba arti yang sesuai kapasitas cerna dan selera para pe-roasting yang budiman.
Buku puisi tersebut panen tawa dan sorak-sorai dari berbagai penjuru kompleks TKIT Alhamdulillah. Inilah apresiasi dan kemesraan dalam balutan suasana jenaka, formula keindahan yang mungkin hanya ada di masyarakat puisi Mustofa W Hasyim. Satu nomor shalawat dari KiaiKanjeng memungkasi Mocopat Syafaat sekaligus menemani para jamaah Maiyah pulang ke huma masing-masing.