Dari Puisi: Melebur Bingkai Kesenian ke Bingkai Kehidupan
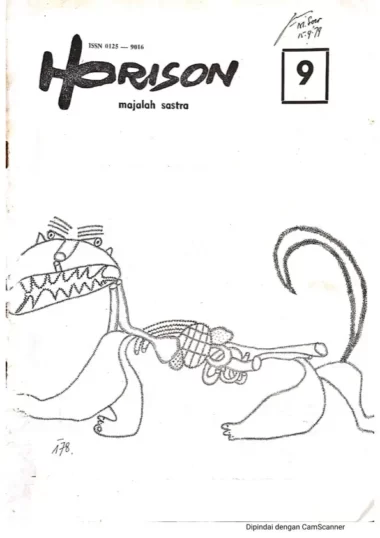
Pencarian ‘indikator nasional’ itu bisa juga dengan berorientasi pada jaringan kemasyarakatan yang lain. Tidak pemilihan per-suku, tapi mungkin per-alam pikiran, per-masalahan, per-interest. Penyair memang bukan budaknya masyarakat sehingga musti begitu repot dengan pertimbangan semacam itu. Tapi Rendra, sengaja atau tidak, meletakkan diri di fase terakhirnya pada aksentuasi masalah sosial politik. Apa yang di atas kita sebut sebagai usaha-usaha baru pengungkapan puisi notabene adalah juga pemilihan untuk mempenetrasi keindonesiaan semacam itu.
Kritik Yang Tak Menampung. Kanvas Kesenian, Kanvas Kehidupan
Kritik komunikasi puisi merupakan salah satu bab dari kritik puisi. Tapi kritik puisi Indonesia dewasa ini kurang ‘berhak’ untuk diomongkan, karena hampir tak ada, sekarat, tanpa runtut irama, tanpa dinamika yang mampu mengimbangi pertumbuhan puisi. Sedangkan kritik komunikasi puisi pun seringkali tak cukup memiliki bagan wawasan untuk mampu ‘memperlakukan dengan baik’ trend-trend komunikasi puisi.
Kritik komunikasi puisi (juga seni umumnya), yang setidaknya tercermin dari berbagai refleksi lisan maupun tulisan (resensi-resensi, diskusi, dan seterusnya), pada umumnya terlalu diliputi oleh alam pikiran yang teknis kesenian. Karya-karya seni itu sendiri tak banyak demikian, tetapi medium dan cara yang mempergaulkan karya seni itu dengan masyarakatnya (sebagai jembatan, begitu biasanya disebut), terlampau teraksentuasi ke alam pikiran kesenian, kurang bersikap secara kehidupan. Bobot pertimbangan teknis kesenian seringkali menjadi substantsi yang acapkali berakibat memisahkannya dari bobot kehidupan itu sendiri. Hal-hal teknis menjadi kesibukan yang dominan. Penilaian atas kesenian berkisar pada sistem ungkap, sosok tubuh, gaya. Karya seni ‘disuruh bertanding’ mana yang lebih bagus tongkrongannya.
Ini tentu saja juga bagus, karena kesenian musti dinamik, innovatif serta penuh unikum-unikum baru. Tetapi ia tidak harus memproporsikan kesenian pada akhirnya sebagai patung lilin atau rumbai-rumbai di etalase. Kita mustinya mampu menangkap kesenian dalam kanvas kehidupan, bukan hanya dalam kanvas kesenian. Kalau memang karya seni seyogyanya ‘diperbandingkan’, maka pertandingannya mustinya lebih memperhatikan hobot kehidupan daripada sekedar pertandingan tongkrongan.
Keadaan ini menjadi lebih memprihatinkan, ketika karena tidak muncul-muncul juga kritikus seni yang berbobot, kemudian para seniman sendiri yang tampil sebagai kritikus. Pada prakteknya hal ini pun kurang menguntungkan, karena (saya tidak menyebut bahwa setiap seniman membawa ‘kepentingan’ nya sendiri sendiri, juga dalam kritiknya) entah bagaimana begitu seniman menulis kritik, ia banyak cenderung teknikal juga. Atau dalam kerangka lain, ia akademis juga. Tak tahu apakah ini karena tradisi kritik memang bermula dari kelembagaan yang formal-intelektual.
Kita para seniman beramai-ramai main sepakbola, sekaligus jadi wasit. Kita yang menentukan peraturannya, memutuskan pemenangnya, dan penonton tak boleh ikut campur. Salah satu tanda eksklusivisme kesenian kita adalah bahwa para penonton itu selalu kurang diberi kesempatan untuk ikut menguji. Dengan kata lain, kurang ada usaha untuk membenturkan seni moderen kita ke hadapan hidung masyarakat seluas-luasnya. Karya-karya kita dilindungi baik-baik dalam kaca etalase. Gejala seperti ini di samping kurang mendukung mekanisme dialog antara karya seni itu dengan lingkungannya, juga memberi peluang bagi kemungkinan manipulasi tata nilai, di mana masyarakat kita suruh menerima atau membebek belaka. Sengaja saya paparkan lanskap umum pada seni moderen Indonesia ini buat memperoleh gambaran yang lebih merangkum dalam soal kritik komunikasi puisi.
Gejala kritik yang semacam itu, menampakkan suatu ironi. Yakni bahwa justru para seniman sendiri yang ‘seolah-olah’ menghambat proses pengakraban karya seni dengan lingkungannya. Di satu pihak kita mengeluh soal keterpencilan seni moderen sambil mendengung-dengungkan pemasyarakatannya, di pihak lain kita pasrah bersembunyi di kaca etalase itu. Sepanjang saya pernah mengikuti pembicaraan kesenian di TIM atau di tempat- tempat lain, saya merasakan pembingkaian itu tidak makin mengendor. Seyogyanya ‘fanatisme’ kita terhadap ‘kuantita’ tidak harus dengan menghilangkan proporsi di tengah kehidupan nyata. Proporsi, relevansi, integritas, juntrungan, juga mungkin fungsi. Kesenian tentulah bukan kesibukan para senimarı saja. Apalagi ia minta subsidi uang orang banyak.
Saya tidak sedang berbicara tentang perbedaan pure art dan applied-art. Masalahnya tak sesederhana itu. Itu rumusan yang berbahaya dan bisa kurang merangkum masalah. Seakan-akan seni-murni tak bisa dipakai, dan seni-pakai itu tak murni. Konteks yang saya maksudkan ialah keberadaan karya seni secara lebih mengurat-daging dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini bukan saja tugas seniman, tapi juga para tukang-letak karya seni (kritikus misalnya), yang sepanjang ini di Indonesia memang kurang mampu.
Prinsip ‘kesenian dengan kanvas kehidupan’ ini memang bisa saja tergelincir pada proses pelunturan atau pencairan kualitas. Bisa saja seniman ‘kalah’ dan mengorbankan dirinya dalam pertemuan dengan massa yang kondisinya memang sangat berbeda. Tapi, kiranya, memang itu tugas konkrit seniman. Berada utuh di tengah orang banyak, bukan di etalase belaka. Saya pikir petani di sawah itu tidaklah terutama menggarap sawah, tetapi menggarap hidup.
Demikian pun penyair. Ia tak sekedar menggarap puisi itu an sich sebagai barang mainannya, tetapi menggarap kehidupan. Penyair menulis puisi tidak dalam rangka masturbasi. Jadi rangka kritik juga tak bisa meletakkannya dalam bingkai yang onani saja.
Puisi, Mode, Mainan, Kesementaraan, Sampai Dunia Dalam
“Puisi itu (niscaya, adalah, hanyalah) barang mainan. la sendiri tak begitu penting, sebab yang utama darinya ialah kemampuannya menawarkan suatu ‘dunia dalam’. Jadi yang pokok adalah dunia dalam itu sendiri. (Dunia dalam ialah sekaligus ‘dunia luar yang tak terbatas’).”
Seperti juga mode rambut atau design pakaian, puisi musti berubah-ubah. Tak boleh itu ke itu juga. Musti selalu ada inovatip, baru, dinamik. Sebab ia, bersama waktu, harus selalu mampu menawarkan dunia dalam itu. Dunia dalam itu sendiri tak berubah. Ia kekal. Sosok wujud yang kita sebut ‘puisi’ itu tak kekal. Ia berubah terus-menerus.
Berubah itu bergerak. Demikian maka yang menjadi karakter kehidupan adalah gerak. Sementara itu yang dicari manusia ialah yang kekal. Manusia mengayuh keabadian. Puisi berusaha menempuh usia sepanjang-panjangnya. Untuk itu ia harus bergerak, berubah-ubah. Kita tempuh kekekalan itu dengan keberubahan, dengan kebaruan demi kebaruan, dengan deretan kesementaraan, estafeta ketidak-kekalan. Itulah ‘dunia tubuh’. Itulah kesibukan karya yang kita sebut puisi.







