Anak-Anak yang Diyatimkan
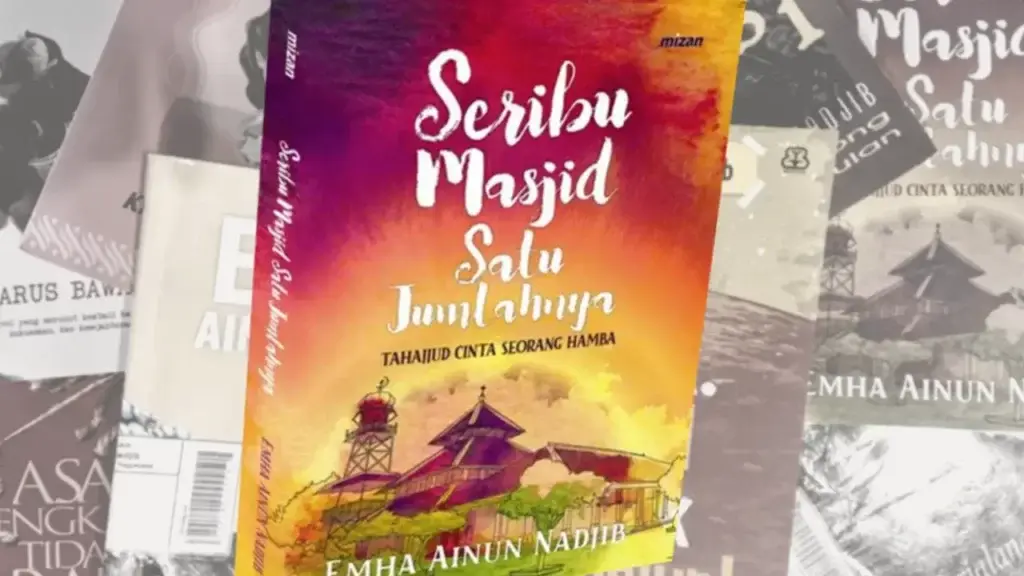
Dzu Walayah lenyap dari rumah kediamannya tanpa seorang pun mengerti ke mana dia pergi, terkadang bahkan dalam waktu yang lama sekali.
Dia selalu berpamit kepada istrinya dengan kata-kata yang sukar dipahami, “Aku wajib meluangkan waktu untuk menemui saudara-saudaraku dalam sunyi!”
Orang-orang, karena amat sibuk oleh kerja, uang dan gengsi, tak pernah punya kesempatan untuk mengenali siapa sebenarnya dia.
Sebagian menyimpulkan dia gila, sebagian lain menyebutnya sebagai orang yang gemar mencari perkara, lainnya lagi beranggapan bahwa dia adalah lelaki yang suka berkhalwat dan bergaul dengan rasa derita.
Aku membuntuti Dzu Walayah di suatu siang yang amat terik, berjalan menyusuri jalanan, berpakaian kumuh, tak memakai alas kaki dan wajahnya bagai orang kesakitan.
Ini adalah zaman modern yang efisien dan efektif di mana setiap orang memusatkan diri pada pencarian kejayaan dan kemegahan: oleh karena itu terhadap perangai lelaki itu aku sungguh penasaran.
Di suatu lorong yang sepi tiba-tiba saja dia membalikkan badan dan memergokiku.
Tapi sebelum sempurna kuurus rasa kagetnya, terdengar dia berkata, “Mari, Nak, berjalan saja bersamaku. Kalau di- buntuti, aku selalu merasa seperti seekor binatang berbuntut.”
Hampir aku tertawa oleh kata-katanya, tapi karena aku salah tingkah, spontan kuikuti saja dia melangkah.
“Aku selalu mencari kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak yatim,” katanya tanpa kuminta.
“Kenapa tidak langsung ke rumah-rumah panti asuhan anak-anak yatim?” aku bertanya.
“Ke sanalah memang sebagian dari perjalananku. Kasihan anak-anak itu. Tinggal di rumah yatim. Rumah yang selalu mengumumkan kepada orang banyak bahwa ia adalah tempat anak-anak yatim.”
“Kenapa kasihan, wahai Dzu Walayah?”
“Karena dengan begitu anak-anak asuh itu tiap hari disuruh merasa yatim. Disuruh merasa tak punya orangtua. Padahal tujuan panti asuhan adalah mengembangkan perasaan aman pada anak-anak itu agar merasa sama dengan anak-anak lain yang punya orangtua.”
Ternyata apa yang terjadi pada lelaki ini adalah sesuatu yang sederhana saja.
“Jadi,” kataku, “kalau soalnya hanya demikian, untuk apa Anda lara lapa berjalan kaki, berpakaian kumuh, dan berlaku seperti ini?”
“Pertama karena aku ingin memasuki jiwa anak-anak itu. Kedua aku ingin merasakan keyatiman yang dahsyat: dengan penampilan seperti ini, bahkan anak-anak yatim pun tak menerimaku. Aku tak sanggup berbuat apa pun untuk menyantuni atau mengurangi jumlah anak-anak yatim.
Oleh karena itu, aku memohon kepada Allah hendaknya diperkenankan setidaknya menemani situasi jiwa mereka.”
“Di dunia ini,” dia meneruskan, “Allah memuliakan sebagian dari hamba-hamba-Nya dengan menakdirkan mereka menjadi anak-anak yatim. Setiap Muslim wajib menyantuni anak yatim, baru kemudian orang miskin. Itulah tanda kemuliaan anak-anak yatim. Merekalah unsur penguji apakah kita mendustakan agama atau tidak.”
“Anak-anak yatim adalah kendaraan utama yang bisa kita naiki untuk mencari keluhuran. Tetapi hanya Allah yang berhak meyatimkan seseorang, sebab tindakan peyatiman oleh Allah itu disertai dengan akal budi dan fasilitas yang diberikan kepada orang-orang lain untuk menyantuni anak-anak yatim.”
“Adapun di dunia yang disebut maju dan modern ini, sebagian pekerjaan penting dari manusia adalah meyatimkan anak-anak, bahkan anak-anak mereka sendiri. Orang-orang modern di kota-kota amat sibuk bekerja sehingga anak-anak mereka teryatimkan. Kapan saja seorang anak tidak memperoleh perhatian, cinta kasih, dan santunan dari orangtuanya, pada jam-jam itu dia menjadi yatim. Kalau bapaknya sibuk rapat dan ibunya sibuk arisan, kau bisa hitung sendiri berapa jam sehari anak itu menjadi yatim piatu. Anak-anak yang diyatimkan oleh orang-orangtuanya itu lantas mencari orangtua di dunia abstrak, mencari cinta kasih di tempat-tempat yang mereka tak tahu bagaimana mencarinya. Mereka menjadi berandal di jalanan, tidak peka terhadap batas baik buruk, tidak terlatih bagaimana berlaku baik. Mereka tidak terdidik menghargai sesama manusia, karena bahkan oleh orangtua mereka sendiri mereka kurang dihargai sebagai manusia. Anak-anak yatim seperti itu, yang kalau ketemu denganku selalu merasa jijik, memandang rendah, bahkan mungkin meludah. Tetapi ketahuilah bahwa tak ada orang yang lebih menanggung dosa perilaku dan sikap anak-anak itu selain orang-orangtua mereka sendiri.”
Telah amat jauh kami berjalan, dan perutku sudah amat terasa kelaparan, tetapi Dzu Walayah terus menyerbuku dengan pernyataan-pernyataan —
“Adapun engkau pastilah anak yang berpikiran cerdas untuk mengetahui betapa banyak jenis keyatiman di dunia maju yang gegap gempita ini.”
“Jika anak-anak tak memperoleh pendidikan seperti yang Allah memberinya hak dan kewajiban, yatimlah dia. Jika orangtua terlalu mendikte anaknya dan menjadikan anak itu hanya sebagai alat dari kemauannya, yatimlah dia. Jika suatu tata perekonomian memberi kemudahan yang berlebih kepada sebagian orang dan memberi kesulitan yang berlebih kepada sebagian lainnya, maka yatimlah orang-orang yang disukarkan. Jika suatu tata politik tak menyediakan ruang bagi anak-anak negerinya untuk mengembangkan pikiran dan sumbangan jujur bagi kemajuan negerinya, maka yatimlah putra-putri negeri yang mulutnya dibungkam itu.”
“Betapa melimpah anak-anak yatim di sekitarmu, Nak. Jika bisa kau ubah, ubahlah. Tapi setidaknya ber-dzikir-lah untuk mengingat mereka, seperti yang kulakukan dengan caraku sendiri ini.”
1987







