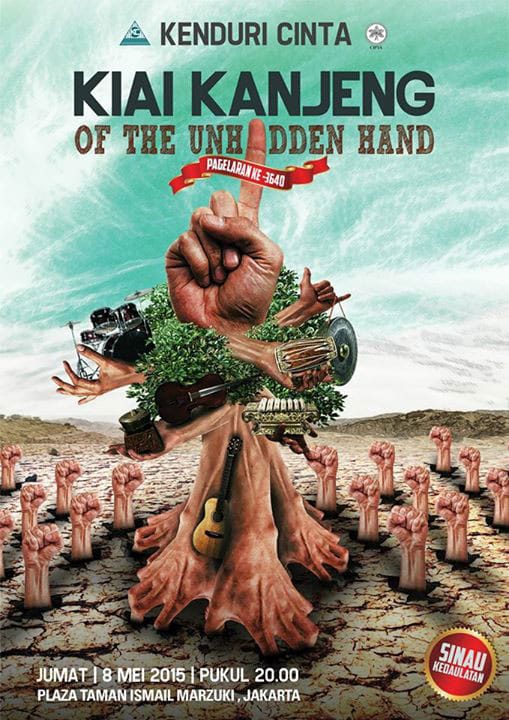Menjelang Senja di Pengujung Ramadhan
Esensi Idul Fitri menurut Cak Nun adalah menjadi makhluk sebagaimana dahulu Allah menciptakan.
Hari raya Idul Fitri tinggal menghitung jari. Menyambut puncak dari bulan Ramadhan itu Selasa sore (11/03) Menjelang Senja mencapai edisi kedelapan. Telah banyak topik keutamaan puasa yang dibabar Cak Nun dan dua hari terakhir beliau menegaskan satu hal. “Kita harus punya jiwa parados, punya jiwa iftitah, jiwa transformasi. Supaya kita masuk Idul Fitri dengan jiwa yang tepat,” ungkapnya.

Kata “parados” ini serupa sebuah transisi yang Cak Nun analogikan dengan iringan musik KiaiKanjeng sebelumnya. Ia menggambarkan parados sebagai penunjuk kedua lokasi bagian kanan dan kiri pada teater Yunani yang merupakan jalan masuk pemain maupun penonton. Tatkala mereka memasuki amfiteater, bebunyian bertalu-talu diorkestrasikan sampai pentas mulai digelar.
“Itu namanya musik parados atau pambuko untuk menyambut transisi menuju pentas. Tidak langsung pentas mulai tapi perlu ada transisinya. Sama seperti ketika Anda ke Masjid Gede di Kauman. Di sebelah selatan maupun di dalam kampung Kauman kita berduyun-duyun masuk masjid. Maka ketika itulah terdengar di dalam diri semacam pengantar musikal menjelang masuk masjid,” ujar Cak Nun.
Langkah menuju masjid, menurut Cak Nun, merupakan bagian dari transformasi. Jeda di sana disebutnya sebagai parados agar kelak siap berhadapan dengan Allah Swt. “Maka dari parados itu KiaiKanjeng tadi kemudian membunyikan Tholaal Badru. Tahap transisi akhir dari Ramadhan menuju Idul Fitri itulah yang akan kita bahas,” imbuhnya.
Bagi Cak Nun, esensi fitri adalah menjadi makhluk sebagaimana dahulu Allah menciptakan. Walau di kalangan masyarakat fitri kerap dipahami sebatas kultural. Semacam dinilai sekadar persambungan hidup bebrayan. Beliau tak menampik kecenderungan horizontal demikian. Namun, lanjutnya, “Idul Fitri harus dikonsentrasikan secara vertikal Akan jangkep pula bila dilakukan keduanya, baik horizontal maupun vertikal.”
Mengikuti cara pandang “ketela dan tape” seperti sudah diterangkan edisi sebelumnya, Cak Nun berpendapat bahwa Idul Fitri itu domain gaib—tak mungkin kembali suci sebagaimana pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Mustahil di sana bukan berarti Allah tak akan mengampuni hamba-Nya yang berlumuran kesalahan.
“Allah mengatakan allażīna yu`minụna bil-gaibi wa yuqīmụnaṣ–ṣalāta wa mimmā razaqnāhum yunfiqụn (Al-Baqarah Ayat 3). Supaya kamu itu lulus di gerbang kegaiban itu. Anda tidak perlu menjawab dengan argumentasi. Anda cukup percaya, ikhlas, kepada Gusti Allah,” tutur Cak Nun.
Riyaya bakda pasa akan tertunaikan manakala cinta manusia total dicurahkan kepada Allah. Pesan ini ditandaskan Cak Nun di segmen terakhir Menjelang Senja. Beliau juga mengajak jamaah Maiyah untuk merefleksikan kembali apakah praktik puasa beberapa hari belakangan hanya urusan “badokan” atau justru sudah mencapai level terdalam: melampaui kesadaran ketela, merengkuh hakikat ragi.
“Ramadhan ini mengaklirkan diri kita dari telo menjadi tape,” sambung Cak Nun, “Dari materialisme menjadi rohaniah. Melakukan transformasi hidup kita agar lebih rohaniah.” Sementara itu, Cak Nun pun tak luput menguatkan hati jamaah Maiyah yang tak dapat mudik di tahun kedua pandemi ini.
Menurutnya, mudik harus dimaknai bukan sekadar sebagai kesadaran jasadiah atau kultural. Suatu perpindahan tempat dari perantauan menuju kampung halaman tempat orang tua dan sanak saudara tinggal. “Kalau Anda sudah mentransformasikan laku puasa menjadi rohaniah maka kamu akan switch. Mudik sebetulnya sudah bersemayam di lubuk kita,” tutupnya.