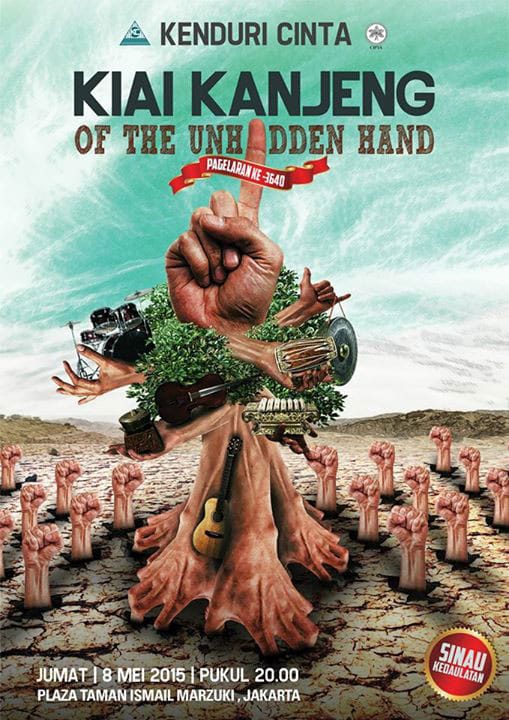Mamayu Hayuning Kadipiro Musik Puisi Dinasti

Foto: Adin (Dok. Progress).
“Musik Puisi Karawitan Dinazti menyeimbangkan antara fungsi-puisi dan fungsi-musik. Konsistensi berkesenian mereka menjadi bukti nilai paseduluran tanpa tepi.”
Sorot tajam sepasang mata Jujuk Prabowo itu seakan semakin menyala. Perlahan ia bangkit berdiri berjalan pelan dua langkah ke depan. Tubuhnya yang ramping membuat gerak-geriknya nampak gemulai mengikuti irama gamelan.
Jujuk sengaja merespons satu nomor berjudul Bangbang Wetan yang dinyanyikan Bu Novia bersama Mas Imam Fatawi. Sepasang tangannya sesekali mengayun ke atas dan bawah mirip figur Gatotkaca. Koreografi Jujuk menyedot perhatian penonton.
Bangbang wus rahina, bangbang wus rahina, srengengene muncul muncul muncul, sunar sumamburat
Cicit cuit-cuit, cicit cuit-cuit, cit-cuit rame swara ceh-ocehan
Krengket gerat-geret, krengket gerat-geret, nimba aning sumur sumur sumur, adus gebyar-gebyur
Segere kepati, segere kepati, kepati bingah bagas kuwarasan
Pukulan terakhir saron menutup pertunjukan itu. Jujuk kembali duduk bersila di sebelah kanan Cak Nun. “Semua serba spontan. Terima kasih kepada Mas Jujuk atas responsnya. Bukti mamayu hayuning Kadipiro,” ujarnya disambut gelak tawa hadirin.
Mocopat Syafaat malam itu menampilkan Musik Puisi Karawitan Dinasti. Formasinya lengkap. Dari Joko Kamto, Hari Murti, Vincensius Dwimawan, Narto Piyul, Joko Kusnun, Novi Budianto, dan Godor Widodo.
Satu lagu pembuka karya Ki Hadi Sukatno dari Taman Siswa sebelumnya memberi lambaran nomor-nomor lain yang akan dibawakan seperti Tuhan Aku Berguru dan Gelandangan. Keguyuban para personel Musik Puisi Karawitan Dinasti sampai sekarang merupakan bukti paseduluran tanpa tepi.
Cak Nun sendiri mengungkapkan Dinasti menyeimbangkan antara fungsi-puisi dan fungsi-musik. Keduanya acap dipisahkan, bahkan kerap dijadikan sekadar pelengkap atau pengiring pementasan. Namun, di tangan kreatif para bapak dan pakdhe itu puisi menemukan haromoninya bersama musik. Demikian pula sebaliknya. Model carangan ini telah dipertunjukkan sejak era Dipowinatan akhir 70-an.
Dahulu masyarakat mengenalnya sebagai “komunitas Ndipo” yang memang disematkan kepada salah satu kampung di belakang THR (kini bernama Purawisata), Jalan Brigjen Katamso.
Pak Nevi merupakan warga setempat di sana. Waktu itu Cak Nun, usai menggelandang di Malioboro, turut berproses kreatif bersama mereka.
“Kita harus berevolusi mencari jati diri kita sendiri. Mencari metamorfosis,” demikian ujar Cak Nun saat merefleksikan estetika Dinasti. Keterbukaan terhadap kemungkinan sampai keberanian bereksperimentasi dalam kesenian ditandaskannya. Itu dilakukan agar kesenian tetap berada di jalur otentisitas.
Inovasi Dinasti terhadap instrumen gamelan di luar arus utama. “Secara karawitan tidak memenuhi prasyarat. Tapi kita men-carang-kan kebudayaan,” tuturnya. Gamelan Dinasti, seperti halnya gamelan KiaiKanjeng, tak mengikuti sistem tangga nada laras pentatonis (pelog dan slendro) tapi masuk ke ranah diatonis—mengikuti pola sel-la-si-do-re-mi-fa-sol yang menggunakan nada dasar do (G) atau E minor.
Masalah carangan seperti ini lalu Cak Nun kaitkan dengan kecenderungan orang yang tak berani melakukan hal berbeda. Ia memberikan contoh soal tayangan di YouTube di CakNun.com yang dicabut hanya karena berbeda dengan pandangan umum.
“Soal pring apus itu pun juga dihapus oleh YouTube. Yang boleh berlaku hanya ilmu modern. Ilmu yang tidak modern tidak diakui. Yang pengobatan lokal dianggap pengobatan tradisional. Dia menjadi subordinat dari ilmu kedokteran modern,” jelasnya.
Malam itu diskusi berangsur dinamis. Tema carangan yang semula disarikan dari langgam dan etos musik Dinasti diperluas sampai masalah pewayangan, kebudayaan, serta dimensi sosial lainnya. Cak Nun berpesan agar konsep pakem dan carangan dipelajari kembali. Bukan hanya pada wilayah kesenian, melainkan juga agama. Jika keduanya dipahami, maka akan sampai pada mana yang sejati dan mana yang artifisial.
“Dunia wayang dan dunia agama itu alurnya melalui makelar-makelar.
Kita harus mengacu pada acuan sumber utama,” tuturnya.