Maiyah dalam Ruang Kajian Pluralisme
Pernak-pernik pembicaraan pluralisme di Maiyah terejawantah dalam bentuk sinau bareng sampai meretas konflik akar rumput.

Sekitar setengah dasawarsa belakangan perbincangan mengenai pluralisme kembali mengemuka. Titik pemicunya diduga peristiwa pemilihan presiden terakhir yang berangsur membagi masyarakat menjadi dua kelompok. Cebong dan Kampret seolah mewakili dua kubu yang berseberangan dan masing-masing darinya ditengarai memproduksi wacana kebencian satu sama lain. Pada tahun-tahun itu media sosial begitu banyak merekam jejak digital berupa ancaman, umpatan, sampai dalih perseteruan fisik.
Terlepas keretakan antara Cebong dan Kampret telah berada di penghujung senja, antara lain dibarengi dengan keduanya sudah berada di kubu serupa, serpihan-serpihan usai peperangan simbolik belum sepenuhnya mereda. Di kalangan masyarakat umum sisa kebencian satu sama lain masih menguat. Walaupun tensinya semakin variatif, warisan pergulatan antara Cebong dan Kampret tetap meninggalkan jejak. Orang saling memandang dan menaruh curiga bukan karena personalitasnya. Melainkan identitas pilihan politik.
Menariknya, fenomena ini kemudian diikuti sejumlah penulisan artikel ilmiah yang membincang pluralisme dalam perspektif Maiyah. Jumlah produksi pengetahuan semacam itu lumayan banyak selama dua tahun terakhir. Sebagian besar peneliti seperti menautkan seutas benang merah, yakni pentingnya penerapan atau pendiskusian kembali nilai-nilai pluralisme di Maiyah yang diwedarkan Cak Nun.
Salah satu asumsi yang mereka tegaskan adalah mengapa hari ini orang tak lagi bebrayan dan cenderung menempatkan liyan sebagai ancaman. Momen Pilpres memang menjadi pemantik masalah itu. Namun, ibarat puncak gunung es, peristiwa tersebut sekadar pucuk yang mampu teramati. Sedangkan persoalan mendasar seperti ketimpangan ekonomi, pemusatan kekuasaan oleh segelintir orang, dan dismanajemen penyelenggaraan negara adalah musabab berikutnya yang kelak menimbulkan liyan sebagai ancaman itu.
Dalam cakupan etis, pluralisme mengandaikan adanya kesadaran akan perbedaan. Etika pluralisme yang demikian acap kali terjebak pada perasaan paling tahu diri seseorang ketimbang orang lain. Sikap itu melahirkan tindakan aproriasi yang amat berpotensi melakukan pengontrolan, penguasaan, dan penjinakan. Diskriminasi juga salah satu akibat selanjutnya. Yang agak tipis perbedaannya: apa batas-batas pluralisme dalam konteks penerimaan tanpa syarat dan pluralisme dengan keberterimaan sesuai ketentuan berlaku?
Masalah pluralisme di Indonesia, sebagaimana ditelisik perbincangan para akademikus, lebih menempatkan opsi kedua daripada pertama. Pluralisme masih bias akan prasyarat dan ketentuan berlaku, yang sesungguhnya merupakan sinonimi dari penyeragaman. Pada tahun 2017 Cak Nun sudah mengemukakan gejala ini dengan ungkapan menggelitik, “Katanya Pancasila tapi kok ada kelompok yang dilarang. Katanya negara plural tapi harus ada syarat dan ketentuan berlaku.”
Paradoks praktik pluralisme ini memang mengimplikasikan dua hal. Di satu pihak mengakomodir keberagaman sesuai kepentingan pihak berkuasa, sementara di pihak lain pluralisme membangun musuh bersama. Dengan kata lain, pluralisme menuai konsekuensi logis dengan menciptakan siapa yang saat itu terliyankan.
Mengakui perbedaan berarti mengimajikan ada sesuatu antara diri dan orang lain yang berseberangan. Bahwa perbedaan yang dimaksudkan ditandai oleh “etnisitas”, bahasa, budaya, bangsa, agama, sekte kepercayaan, pilihan politik, dan seterusnya itu bergantung pada wacana dominan yang sedang menguat. Di samping problem politik wacana, barangkali masalah “politisasi pluralisme” yang melatarbelakangi beberapa akademikus melakukan kajian di atas beberapa tahun terakhir.
Riset Ismail Angkat bertajuk Budaya Politik Emha Ainun Nadjib dalam Meretas Problematika Pluralitas Agama di Indonesia (2021) yang hangat terbit medio tahun ini memperlihatkan skema konsep Cak Nun tentang pengolahan keberagaman menjadi kekuatan. Ia menilai pijakan berpikir semacam itu amat penting bagi wacana pluralisme di Indonesia, yang bukan sebatas abstraksi menara gading, melainkan strategi praktis di tengah massa.
Ismail menghadirkan kembali rekam jejak Cak Nun di masyarakat, khususnya ketika bersama KiaiKanjeng dalam meretas konflik. Kata kunci peretasan yang dilakukan adalah mengolah keberagaman menjadi keharmonisan.
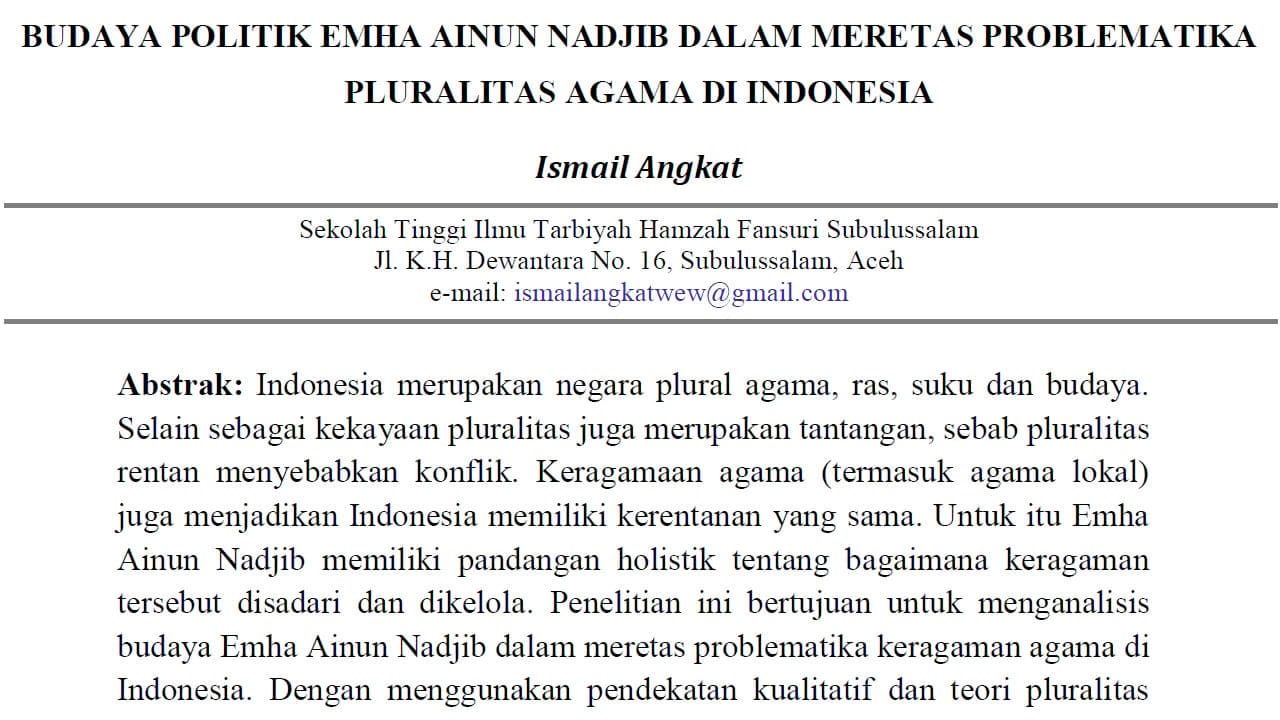
Keberagaman ini kerap dipandang sebatas keberagamaan. Itulah sebabnya, upaya menengahi konflik di Indonesia sering dimulai dengan helatan forum-forum seperti dialog lintas iman. Bukan berarti pendekatan agama secara formal keliru. Terlebih mengundang para tokoh agama untuk duduk bersama.
Akan tetapi, acara demikian sekadar berefek simbolis sehingga kurang mengindahkan problem kontekstual akibat konflik di masyarakat. Meretas konflik, dengan demikian, membutuhkan upaya sistemik dan operasional. Tak akan tuntas jika digelar di mimbar simbolis semata.
Pendekatan Cak Nun berbeda. Kendati sepintas mewakili kelompok agama tertentu, strategi dan siasatnya merangkul aspek-aspek seperti kultur masyarakat setempat. Pihak yang berseteru diundang dalam satu panggung. Merembuk sejauh mana permasalahan yang dihadapi. Membincang seberapa potensial menemukan jalan tengah melalui upaya dialog setara.
Itu pun terselenggara dengan dan melalui pertunjukan kesenian. Peran KiaiKanjeng karenanya begitu krusial sebagai sebuah metode meretas konflik. Apa yang dilakukan Cak Nun dan KiaiKanjeng sebetulnya merupakan meretas konflik lewat kebudayaan. Suatu modal sosial yang menjadi pijakan penting dan relevan bagi kondisi masyarakat setempat.
Menurut Ismail, pendekatan Cak Nun lebih efektif karena tak sekadar melakukan peretasan konflik pada ranah teologis maupun metafisik. Meskipun keduanya menjadi inspirasi mendasar, sesuatu yang niscaya karena latar belakang keagamaan, Cak Nun menerapkan konsep “harmoni, kompromi ataupun toleransi” (lihat, hlm. 25) dengan mempertimbangkan segi emik (native point of view) masyarakat setempat.
Tanpa melibatkan orang bersangkutan, pencarian jalan tengah untuk meretas konflik hanya membekas sebatas seremoni, sebagaimana sering terjadi dalam praktik pendekatan dialog lintas iman di Indonesia. Dalam istilah Ismail, Cak Nun mencoba mendekati masalah dengan mendayagunakan “kesejajaran sistem nilai moral dan etika” selama proses berlangsung.
Temuan penelitian Ismail ini memiliki keserupaan kajian, tetapi riset berikut cenderung memfokuskan pada masalah pemikiran Cak Nun mengenai moderasi beragama. Antara lain tesis pascasarjana Mochamad Hasan Mutawakkil berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib (2020).
Ia menyimpulkan — dan ini justru melengkapi konsep peretasan konflik sebelumnya — bahwa Cak Nun menerapkan pendidikan moderasi beragama dengan metode Iqro’: pemahaman melalui rasa, pembelajaran kontekstual, keteladanan, kasih sayang, dan tolong-menolong. Rincian ini sekilas bernuansakan pedagogik dan memang Hasan mencoba mengaitkannya di ranah pendidikan.
Sebagai magister di bidang Pendidikan Agama Islam, metode yang dilakukan Cak Nun relevan diterapkan bagi lembaga pendidikan, masyarakat, dan orangtua. Utamanya pendidikan moderasi itu berdampak signifikan untuk ambil bagian pembentukan karakter serta pemahaman peserta didik. Mengapa demikian?
Hasan mencatat (lihat, hlm. 124), “Pemikiran Emha Ainun Nadjib tentang pendidikan moderasi beragama lebih mengarah pada bagaimana memadukan antara teks keagamaan berdasarkan realitas kehidupan, agama yang kontekstual dengan perubahan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian secara universal.”
Dalam argumen Hasan, moderasi beragama memberikan jalan tengah “bertindak, berpikir bijaksana, dan menicayakan umat untuk tidak fanatik buta” yang ketiganya merupakan hal mendasar bagi toleransi. Sekalipun Hasan kurang mengelaborasi gagasan toleransi serta pluralisme yang sering disebutkan pada bagian pembahasan dengan konteks politik nasional lima tahun terakhir, temuan itu secara implisit memperkuat apa yang telah dipaparkan di awal: pluralisme harus tanpa syarat, universal, tanpa tebang pilih.
Pendapat Hasan tentang Cak Nun yang memadukan teks keagamaan dan realitas kehidupan yang kontekstual menunjukkan keumuman itu. Dalam ungkapan lain, Cak Nun mentadabburi ayat yang tertulis dan ayat yang terhampar sebagai bagian dari dialog meretas konflik di masyarakat. Kecenderungan itulah yang amat kentara di dalam setiap kesempatan sinau bareng di Maiyah.
Apa namanya kalau fenomena ia bukan merupakan ejawantah ruang kajian berikut penerapan pluralisme di Indonesia?











