“Leader Governance”: Kepemimpinan Menurut Cak Nun
Kepemimpinan memberikan energi berupa rasa percaya dan aman. Kepemimpinan mendistribusikan kearifan, pengetahuan, solusi, serta harmoni bagi orang di sekelilingnya.

Pekan pertama Agustus lalu Gandhie Tanjung W. menulis catatan berjudul An Introduction IT Governance di LinkedIn. Ia membicarakan pentingnya penguasaan teknologi informasi terhadap tata kelola organisasi atau perusahaan. Ada dua kata kunci yang ia kemukakan, yakni structure of integrating dan business strategy. Keduanya bagian vital dari manajemen pengelolaan teknologi informasi.
Gagasan itu bukanlah semata wilayah bisnis, melainkan juga mencakup organisasi secara umum. Tanpa kerapian manajemen informasi, sebuah organisasi berada di jurang kehancuran. Risiko paling potensial: berumur pendek. Gandhie menyebut “chaos and disorder” sebagai akibat jika sebuah organisasi tak dikendalikan sesuai kerangka kerjanya.
Itulah sebabnya, kedudukan pemimpin berikut corak kepemimpinan tidak saja penting, tetapi juga sebuah keniscayaan. Masih bertaut persoalan demikian, pada tulisan lain, April silam, Gandhie juga menyinggung “micromanager” dan “leader” yang sesungguhnya berada di balik kesuksesan pengendalian organisasi. Apa bedanya? Di akhir tulisannya, ia mengatakan, “Micromanager tells, the leader asks.”
Faktor penting yang membedakan keduanya terletak pada pemahaman akan detail kinerja atau kegiatan. Kendati keduanya tetap memiliki peran manajerial, antara “manager” dan “leader” juga dipisahkan dan ditandai oleh kewibawaan. Kata ini terkesan abstrak. Namun, bukan berarti ia mengawang tanpa dapat dijelaskan atau dipelajari.
Setiap orang berpeluang menjadi pemimpin tapi belum tentu dirinya menunjukkan wibawa kemimpinan. Kewibawaan diperoleh dari proses yang panjang dan mungkin juga terbentuk karena kepercayaan jamak orang. Bagi pemimpin yang juga memiliki jiwa kepemimpinan, ia tidak sekadar memberikan instruksi, sebagaimana terlihat kentara dalam pola manajerial, tetapi harus mampu menaburkan inspirasi.
Jawaban ini saya dapatkan ketika membaca penelitian berjudul The True Leaders and Leadership: From The Narratives of Emha Ainun Nadjib (Atlantis Press, 2020). Kajian karya Ahmad Mabrur dan Pardjono dari Universitas Negeri Yogyakarta itu mencoba menelisik gagasan konseptual Cak Nun mengenai pemimpin dan kepemimpinan.
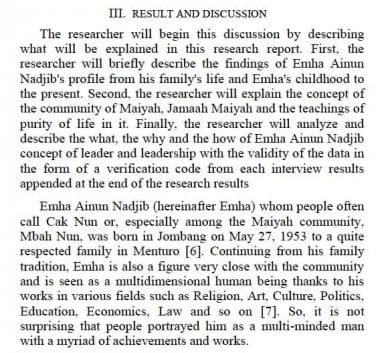
Kepemimpinan, bagi Cak Nun, cenderung bersifat kualitatif. Ia karenanya perlu dibedakan dengan “pimpinan” sebagai identitas atau entitas yang memiliki bawahan. Kepemimpinan memberikan energi berupa rasa percaya dan aman, sehingga orang lain di sekitarnya merasa terwadahi maupun ternaungi. Kepemimpinan, dengan demikian, mendistribusikan kearifan, pengetahuan, solusi, serta harmoni bagi orang di sekelilingnya (lihat, hlm. 3).
Simbolisasi kepemimpinan semacam itu menurut Cak Nun terwakilkan dalam figur punakawan. Khususnya tokoh Semar. Di dalam diri Semar terdapat kecenderungan orang biasa sekaligus dewa. Ia menggambarkan titik perpaduan yang paripurna, sehingga bukanlah mengherankan kalau Semar mengamsalkan cita-cita demokrasi.
Ahmad dan Pardjono berpendapat buku Cak Nun bertajuk Arus Bawah (1994) adalah contoh deskriptif bagaimana seorang Semar menunjukkan kepemimpinanya dalam melindungi maupun menampung aneka perbedaan pendapat (lihat, hlm. 4). Pengayoman Semar terhadap siapa pun tanpa membedakan berbagai latar dan motif memperlihatkan betapa dirinya berkepribadian nyegoro — hatinya seluas samudera.
Kepemimpinan Semar karena itu holistik dan universal. “A holisctic leader who is able to absorb the value of various aspects in solving problems or behaving in one particular condition,” catat Ahmad dan Pardjono. Dalam novel “pascamodernis” tersebut Cak Nun banyak memberikan ilustrasi kearifan maupun altruisme sang Ki Lurah Badranaya itu.
Pada buku Cak Nun lain, Demokrasi La Roibafih (2016), Ahmad dan Pardjono juga mendapatkan hakikat kepemimpinan dalam skala negara yang berkaitan dengan jiwa kesatria: kompeten, manajer yang handal, pemberi solusi, namun ia harus juga seorang pinandita. Itu pun belum mencukupi. Ia harus pula sinisihan wahyu. Yang terakhir ini dijelaskan lebih mendetail oleh Cak Nun dibukunya berjudul Jibril Tidak Pensiun (2007).
Masalahnya, kepemimpinan yang berjiwa kesatria, berwatak pinandita, serta berpedoman sinisihan wahyu acap kali berada di tataran idealita. Bahkan ironinya sematan tersebut sering dipolitisir segelintir kelompok. Akan tetapi, sebagai acuan kultural wacana kepemimpinan seperti ini berlangsung cukup lama dalam bentangan sejarah di bumi Nusantara. Saking lawasnya ia kerap dimitoskan sepanjang tahun.
Diskursus kepemimpinan tersebut pada gilirannya dibicarakan dalam konteks gerakan mesianisme atau milenarisme. Sebuah gerakan yang bukan saja terjadi di Jawa, melainkan juga dunia dengan berbagai variasinya. Industri film modern turut pula menggeser cakupan itu ke dalam konsep pahlawan ataupun hero. Pendek kata, wacana kepemimpinan selalu menubuh di dalam praktik kesejarahan.
Sementara itu, di tengah konstruksi wacana kepemimpinan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Maiyah berupaya mengetengahkan konsep kepemimpinan sebagai ranah independensi. Suatu sikap berdaulat atas dirinya sendiri. Seturut temuan Ahmad dan Pardjono, “For Emha everyone is a leader for himself, sovereign over himself …”

Kedaulatan yang seakan eksistensial ini meneguhkan posisi free will. Dalam konteks kepemimpinan yang berdaulat, seseorang menjadi dirinya karena keputusannya. Bahwa sebelum mencapai tahap itu seseorang menengok kanan dan kiri, menghimpun sejumlah aspirasi, keputusan final tetap berada di pundaknya. Sebuah keputusan yang tentu saja terlandasi sikap bijaksana.
Dalam pembahasan di awal, tata kelola organisasi yang berdasarkan structure of integrating, semestinya berangkat dari kedaulatan atas individu, baru kemudian merambah kepada cakupan sosial. Kepemimpinan, sejauh alur pembahasan sebelumnya, berada di tengah-tengah sebagai tumpuan penyeimbang. Berangkat dari yang individual berujung kepada yang sosial. Integrating without a specified variable would be chaos.
Bukankah demikian?
Kajian pemimpin dan kepemimpinan yang dijelajahi dari pemikiran Cak Nun ternyata membuka interpretasi baru yang sifatnya multidisipliner. Kutipan buah ena Gandhie di awal tulisan mendapatkan penjelasan dalam perspektif lain yang barangkali belum terbayangkan sebelumnya. Terutama penjelasan yang mulanya berpijak dari disiplin ilmu IT Governance, namun bisa terintegrasi dalam kajian Educational Management sebagaimana latar akademik peneliti jurnal di atas.
Semoga penelitian berikutnya membuka kemungkinan khazanah baru.











