Jamaah Maiyah dan Otoritas Religius

Apakah jamaah Maiyah berbeda dengan jamaah Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah, tarekat, atau organisasi masyarakat lain? Adakah penanda normatif yang membedakan jamaah Maiyah dengan komunitas keislaman lain? Pertanyaan semacam ini acap kali dikemukakan akademisi ketika hendak meneliti seputar Maiyah.
Sepintas pertanyaan itu juga terdengar aneh bagi sejumlah jamaah Maiyah karena ia mengandaikan satu kategori baku, tunggal, dan distingtif. Suatu pertanyaan yang barangkali tak akan muncul kalau akademisi tersebut hendak meneliti Cak Nun atau KiaiKanjeng secara spesifik.
Pertanyaan di atas tergolong dalam konstruksi ideologis. Dalam bayangan akademisi jamaah selalu berada di dalam tiplologi tertentu. Kalau bukan a maka b, c, atau d. Demikian pula pengertian umat Islam. Seolah terdapat bangunan yang stabil maupun absolut. Padahal, apa yang disebut sebagai umat Islam selalu berada di tengah lintasan sejarah.
Ia selalu inheren dalam pergulatan politik, sosial, maupun budaya yang sifatnya partikular. Itulah sebabnya, imaji akan umat Islam yang diandaikan individu atau sekelompok orang dalam periode sejarah tertentu niscaya beraneka rupa. Keberanekaan inilah yang pada gilirannya saling dipertarungkan, didefinisikan, serta dinegosiasikan.
Gerakan Maiyah yang secara faktual tumbuh dan berlangsung di berbagai wilayah merupakan realitas sosiologis. Keberadaan ini dapat diamati dan diteliti. Namun, Maiyah sebagai realitas sosiologis kerap diperdudukkan oleh akademisi dengan asumsi penelitian yang cenderung terbangun dari konstruksi ideologis.
Seperti pertanyaan yang dimunculkan di awal: bukankah akan reduktif bila realitas sosiologis didedah dengan pertanyaan ideologis? Di situlah letak persoalan mendasar yang sering diabaikan akademisi dalam meneliti Maiyah. Kesalahan itu pertama dan terutama berpusar pada problem metodologis dalam memandang objek penelitian.
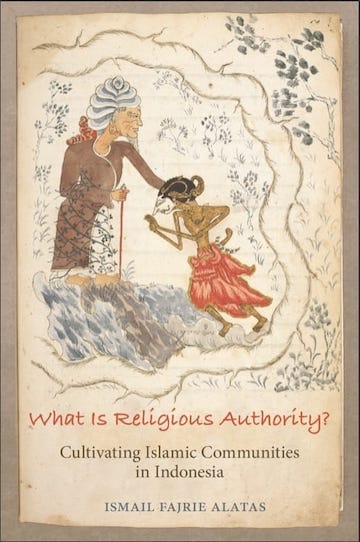
Ide mengenai metodologi ini saya dapatkan ketika membaca buku terbaru Ismail Fajrie Alatas berjudul What Is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia (2021). Ia tidak meneliti Maiyah tapi memfokuskan pada Habib Luthfi. Tapi dari bukunya itu kita bisa merefleksikan posisi Maiyah di Indonesia. Otoritas religius, seturut dengan argumen Ismail, ditandai dengan adanya jamaah. Sesuatu yang barangkali agak berbeda dengan pandangan otoritas seseorang dan/atau sekelompok orang selama ini yang sering ditengok berdasarkan kemampuan intelektual.
NU, Muhammadiyah, maupun organisasi keislaman lain dipandang otoritatif karena memiliki jamaah. Ia merupakan modal sosial yang tidak jatuh dari langit. Adanya jamaah berarti terdapat upaya terus-menerus untuk membangun ikatan kolektif.
Dalam konteks jamaah Maiyah otoritas itu hasil dari rekam jejak Cak Nun bersama jamak orang, yang bukan hanya bersinggungan di periode 2000-an manakala Maiyah memperlihatkan identitas kolektifnya, melainkan juga dekade 70-an, 80-an, maupun 90-an dengan beragam corak serta variasinya. Jamaah Maiyah, dengan demikian, terlahir atas akumulasi persinggungan antara Cak Nun dan khalayak yang terus diperjuangkan.
Kita bisa melihat gamblang betapa Maiyah sebagai realitas sosiologis itu mewarnai diskursus praktik keseharian jamaah yang amat organis, cair, serta terorganisir melalui simpul yang tersebar di berbagai wilayah. Fenomena sinau bareng bulanan yang sebelum pandemi begitu berjubel dari surup sampai subuh menunjukkan militansi jamaahnya. Itu hanya satu sisi dari sudut pandang kasatmata. Masih banyak dampak atas militansi jamaah bagi kehidupan masing-masing.
Salah satunya apa yang diprogramkan setiap simpul selama pandemi: membuat lumbung pangan, strategi bercocok tanam berbasis rumahan, dan lain-lain. Gerakan mereka terwujud karena terdapat imaji kolektif yang menyatukan, yakni sama-sama merasakan bagian dari jamaah Maiyah.
Apakah otoritas religius jamaah Maiyah bersumber dari kefiguran Cak Nun? Tentu saja demikian tapi masih terdapat fase berikutnya yang lebih berpengaruh. Ismail dalam bukunya tersebut menyebut situs realisasi sunnah. Transmisi dan realisasi atas ajaran Kanjeng Nabi membentuk proses pembangunan jamaah.
Kedudukan Cak Nun menghubungkan antara yang silam (ajaran Rasulullah) dengan yang sekarang (konteks zaman) lewat dialog “sinau bareng” sehingga pada gilirannya otoritas religius terbentuk. Dalam salah satu nilai Maiyah, relasi antara Tuhan, Kanjeng Nabi, dan hamba terejawantah di ranah Solusi Segitiga Cinta: Allah merupakan faktor primer bersama Rasulullah dalam mengupayakan solusi atas segala permasalahan.
Kefiguran Cak Nun yang berada di posisi sentral dalam mengoneksikan “gondelan klambine Kanjeng Nabi” di satu pihak dan mendialogkan nilai-nilai kenabian secara kontekstual di pihak lain membuat Maiyah relatif berbeda dengan otoritas religius lainnya. Berbeda bukan berarti memosisikan pihak lain sebagai liyan sehingga berseberangan atau vis-à-vis. Namun, ia menegaskan karakteristik articulatory labour atau mengartikulasikan pemahaman Islam dengan konteks lokalitas jamaah Maiyah.
Contohnya bisa banyak hal. Terutama bagaimana Cak Nun benar-benar merangkul apa yang disebut sebagai jamaah Maiyah tanpa membedakan latar belakang gender, ekonomi, “etnis”, ataupun agama. Kata jamaah yang konotasinya sangat Islam pun sangat cair di Maiyah. Pun orang yang mengaku beragama Islam. Di Maiyah keyakinan atas Islam tidak berada di dalam kategori identitas (KTP), tetapi proses perjuangan terus-menerus saling menyelamatkan satu sama lain. Wujud articulatory labour di Maiyah lebih banyak di ranah dekonstruksi nilai atau cara berpikir seseorang.

Wujud atau karakter yang mengidentifikasi jamaah Maiyah yang beraneka rupa itu dideskripsikan Timothy Daniels dalam bukunya bertajuk Islamic Spectrum in Java (2009). Selama lebih dari dua dasawarsa Maiyah menyinergikan empat hal: “fundamentalist-sufi-radical-democratic” (lihat, hlm. 13). Keempatnya, kendati memerlukan pembahasan lebih lanjut, terartikulasikan ke dalam pola “sinau bareng” yang penuh proses komunikasi nonformal, sehingga Cak Nun jamak membabar suatu topik dengan perumpamaan (analogi) yang dapat diterima keseluruhan jamaah.
Itu pun ditambah pula dengan pandangan egaliter bahwa jamaah merupakan narasumber dan partisipan sekaligus. Ketambah pula selama proses sinau bareng di tengah-tengah acara KiaiKanjeng menjadi perantara antara selingan musik sekaligus medium dialog. Seperti kata Timothy, “Despite the obvious attraction of such amazing musical performances, for many, the core of these monthly events is the open dialogues, facilitated and moderated by Cak Nun, involving participants from various layers of society” (hlm. 157).
Cak Nun karenanya bukan sekadar melakukan articulatory labour dengan pola penyesuaian sesuai konteks latar belakang jamaah Maiyah, melainkan mencoba melakukan “sinkretisasi” atas beragam pendekatan atau metode dakwah yang paling tidak memuat anasir sastra, teater, dan pertunjukan musik. Fenomena itulah yang kemudian banyak direproduksi jamaah Maiyah di wilayahnya masing-masing dengan tentu saja memperlihatkan kekhasan tertentu.
Jamaah Maiyah sebagai realitas sosiologis, sebagaimana diperlihatkan semenjak awal, memiliki unikumnya sendiri di tengah jamaah-jamaah keislaman lain di Indonesia. Pertama, keunikan itu organis meski tanpa struktur keorganisasian yang baku atau kaku. Kedua, fenomena jamaah Maiyah berada di tengah lintasan sejarah yang spesifik dengan dinamika sosial maupun budaya tertentu. Poin terakhir ini menuai rentetan pertanyaan berikutnya.
Tatkala belajar selalu diandaikan secara vertikal dan sentralistik, di Maiyah dengan adanya sinau bareng semua orang adalah guru sekaligus murid, sehingga posisinya cenderung egaliter, demokratis, serta inklusif. Di saat organisasi mana pun terbangun dan terkondisikan atas struktur hierarkis tertentu, Maiyah memilih kultur sebagai gerakan berbasis komunitas dengan berbagai bentuk inisiatif penggiat dan/atau jamaah Maiyah masing-masing.
Dengan pilihan itulah jamaah Maiyah terbangun dan berlangsung sampai sekarang. Bukanlah mengherankan kalau Maiyah menyebut diri bukan organisasi, melainkan organ yang tidak kalah organis ketimbang organisasi formal lainnya.










