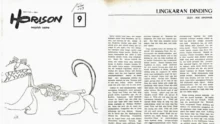Hutang-Hutang Kebudayaan
dari Masalah Idealisme dan Orientasi Kaum Muda
Kita bisa mengadakan pengandaian-pengandaian, untuk mengukur seberapa tinggi hutang-hutang kita telah menumpuk, dengan kondisi semacam itu. Barangkali kita tidak perlu bermimpi untuk dalam waktu dekat kita mampu menciptakan keseimbangan antar pembangunan berbagai sektor kehidupan masyarakat kita, sehingga dengan demikian ia bisa merupakan iklim yang menumbuhkan perkembangan yang utuh dan seimbang pula individu-individu masyarakat kita. Bahkan Agama-agama yang dipeluk oleh seluruh penduduk Indonesiapun tidak usah bermimpi dengan pidato dan khotbahnya untuk mampu melibatkan secara kuat dasar falsafahnya ke dalam setiap gerak kultur pemeluk-pemeluknya — sebab dalam hal ini para juru agama barangkali amat perlu berkotor tangan untuk tidak berdakwah sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan keterlibatan sosial yang sejauh dan sedetail-detailnya. Bahkan kitapun sudah senantiasa terbuntu berbicara tentang sistem-sistem dan tatanan-tatanan karena menganggap “revolusi-mentalitas” adalah utopi.
Impian kita sahajakan. Sekedar bagaimana pospos perangsang tumbuhnya gerak kultur bisa kita manfaatkan seefektif mungkin untuk menanamkan benih idealisme dan integritas kebudayaan. Bagaimana TV lebih memperhatikan penyuguhan bukti-bukti kreativitas serta contoh-contoh tradisi kreatif, secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana film-film diwarnai juga oleh iktikad untuk merangsang kreativitas bangsa serta meninggikan mutu kehidupan mereka. Bagaimana pelaksanaan pendidikan formil tidak sekedar berisi pengajaran-pengajaran informatif-konsumtif, tetapi lebih diarahkan untuk merangsang tumbuhnya kreativitas rochani. Bagaimana orang tua tidak hanya menjejali mulut anak-anaknya dengan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan, hiburan dan konsumsi, tetapi juga selalu memperhatikan langkah-langkah paedagogis untuk membuka kreativitas, daya cari, daya mandiri, serta mengasah kesiapan untuk memiliki dan mengolah dirinya sendiri. Bagaimana setiap medium, perkumpulan-perkumpulan sosial, Pramuka, group kesenian, perguruan silat, bahkan juga kelompok olah raga, tidak abai terhadap pentingnya penumbuhan kreativitas individu lewat sektornya masing-masing.
Tetapi permasalahan kita barangkali baru pada tahap tehnik pemasaran idealisme. Maka jawabannya bagaimana kita berusaha mengenal betul medium-medium pembudayaan itu serta memperhitungkan effektivitasnya. Salah satu segi, anak-anak muda yang terpelajarpun, bahkan kini masih sedang berada pada tahapan permulaan untuk belajar menjadi manusia yang punya kultur membaca. Membaca, sebagai salah satu sarana penumbuhan kesadaran dan penalaran idealisme (padahal membaca Pustaka dan Vista tentu amat jauh berbeda pula), masih belum merupakan kebutuhan pokok. Maka sementara tradisinya terus dirintis, kita juga harus peka terhadap sarana-sarana lainnya. Saya pikir cukup banyak bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Media pendidikan formil maupun informil, forum-forum, bahkanpun pertemuan silaturahmi keluarga, kenapa tidak. Apalagi jika kita berpikir juga untuk menambah frekwensi sarana.
(V)
Pemasaran idealisme menjadi masalah primer, sebab setiap jengkal langkah kebudayaan, amat diseyogyakan dilandasi olehnya. Kehidupan manusia hanya bisa diorientasikan secara tepat dan benar, betapa relatif dan tidak bisa seutuhnya pun, apabila kesadaran dan penalaran idealisme benar-benar menjadi sumber geraknya.
Idealisme di sini bisa dalam pengertian yang seluas-luasnya. Seorang petani di pelosok dusun yang relatif belum tersentuh oleh “kultur intelektuil modern”, tidak mustahil memiliki idealisme yang barangkali tidak kalah kuat dibanding kita yang tidak buta huruf. Idealisme mungkin saja beressensi sama tetapi dari sumber kefalsafahan yang berbeda. Idealisme murni kemanusiaan dan alam. Idealisme juga bisa amat diwarnai oleh keagamaan atau banyak isme-isme yang tumbuh secara massif tradisionil maupun yang berasal dari cetusan-cetusan.
Permasalahan idealisme anak-anak muda kita yang berada dalam pusat-pusat jaringan dinamik kebudayaan, tentu saja berbeda dengan problem petani kita di pelosok tersebut. Keinsyafan intelektuil tentang idealisme beserta kemampuan penalarannya, menjadi amat penting, karena dinamik kehidupan masa kini, terutama di pusat-pusat jaringan itu, berhadapan dengan tantangan-tantangan, yang secara umum telah terillustrasikan dari uraian di atas. Petani yang kita sebut itu, yang kurang begitu berurusan dengan arus gerak “modernisasi”, mungkin tak perlu terlalu banyak berkewajiban membayar hutang-hutang kebudayaan, betapapun mereka kita anggap terbelakang, ndeso dan tidak pintar. Tetapi kenyataan kerugian-kerugian spirituil (bahkan juga materiil) yang diderita oleh masyarakat terbaru kita, meminta dihadapi dengan bentuk dan isi idealisme yang lain sama sekali. Saya pikir inilah tantangan utama yang harus dilayani oleh kaum muda kita hari ini. Bahkan lebih dari itu, mereka harus sekaligus merintis pengolahan sejak hari ini agar hal tersebut bisa bertumbuh kuat pada kaum muda besok pagi. Prinsip dasar bahwa setiap bentuk kolektivitas sosial budaya, juga setiap pos kebudayaan (dari bangku sekolah, pengajian di surau, organisasi mahasiswa ekstra universiter, sampai group-group kesenian, dst) mustilah melandaskan diri pada iktikad mengolah kepribadian, tatanan sikap mental, penumbuhan kreativitas dan idealisme, merupakan falsafah kuno yang hari ini terasa makin urgen.
Majalah Pustaka, Perpustakaan Salman ITB Bandung, edisi No. 9 Th. II, 1978, hlm. 38-44