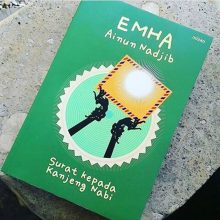Ditangkap Demi Silaturahmi

Di era 1970-an ke atas, ada istilah umum yang berbunyi “Kenakalan Remaja”. Itu menjadi mindset masyarakat secara keseluruhan. Dari orangtua-orangtua dalam keluarga, generasi tua di masyarakat, bahkan semacam cara berpikir dan istilah resmi yang juga dipakai oleh pemerintah.
Tidak ada “Kenakalan Dewasa” atau “Kenakalan Kaum Tua”. Selalu yang nakal adalah remaja. Padahal entah seberapa besar kadarnya, tetapi kenakalan remaja adalah kontinuasi, akselerasi atau turunan dan transformasi dari kenakalan generasi sebelumnya, yakni kaum dewasa dan kaum tua.
Proses pendewasaan anak-anak muda yang dulu klaster utamanya adalah Dipowinatan, melalui Dinasti hingga KiaiKanjeng, tatkala sampai di era Patangpuluhan: kami bahkan secara agak radikal menyepakati suatu arus berpikir bahwa kenakalan kaum tua sebenarnya jauh lebih parah dibanding kenakalan remaja.
Ada pemahaman universal, termasuk logika pemikiran dalam agama, bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Senakal-nakal anak-anak dan remaja, yang tetap lebih salah dan paling salah adalah orangtuanya.
Ketika sejak era Dipowinatan hingga Patangpuluhan kami mengalami dunia dan kreativitas karya seni teater, Dinasti, kemudian KiaiKanjeng, selalu dianggap sebagai “anak nakal”.
Setiap naskah pentas Dinasti selalu harus disetorkan ke Polresta dulu untuk disensor. Pentas “Pak Kanjeng” dicekal di Surabaya maupun di Yogya.
Saya ingat pada hari pencekalan itu, malamnya Pak Permadi dan Ki Gendheng Pamungkas datang ke Patangpuluhan untuk menyatakan simpati dan dukungan.
Musik-Puisi Dinasti seri puisi “Dokar” yang Pemerintah tahu asosiasinya adalah “Golkar”, bikin gerah penguasa dan saya harus berlari-lari dari kejaran polisi dan tentara. Apalagi “kenakalan” saya ganda: pada saat-saat bersamaan saya dianggap melatarbelakangi demonstrasi mahasiswa di Yogya. Beberapa dari mereka ditangkap dan ditahan di kantor Korem, sehingga saya harus datang untuk membebaskan dan mengeluarkan mereka dari tahanan.
Setelah lebih sepuluh tahun sekitar era Daoed Yousoef menjadi Mendikbud tak ada demontrasi mahasiswa, saya memprakarsai demonstrasi “Anti Kekerasan” dengan membakar patung Presiden Soeharto di Boulevard UGM Yogya. Tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat waktu itu antara lain Brotoseno, Rizal Malarangeng dan M. Thoriq dan Taufiq Rahzen. Karena pemilik speaker atau alat pengeras suara (pastilah) tidak ada yang mau dan berani disewa, maka kami memakai pengeras darurat dengan menggunakan accu (aki) Jeep saya sebagai sumber tenaga.
Yang datang ke keramaian demo itu bukan hanya pasukan TNI dan Polri, tapi juga Danrem dan Kapolda. Dalam orasi sempat saya sampaikan ucapan terima kasih kepada beliau berdua dan pasukannya bahwa mereka telah repot-repot datang ke Boulevard UGM untuk mengamankan demokrasi dan kebebasan mimbar.
Setelah Seno, Taufiq dan Rizal berorasi, sudah kami rancang mereka langsung masuk mobil dan kita bawa ke suatu tempat yang aman. Ketika demo berakhir, mereka tidak ada, sehingga tidak bisa ditangkap. Tinggal saya, uthak-uthek membawa accu ke Jeep saya. Daripada gelisah saya menunggu ditangkap, saya berlari mendatangi dan menemui Danrem dan Kapolda dan bertanya: “Gimana Pak? Bagus nggak? Bagus nggak?”. Mereka spontan menjawab: “Bagus Cak! Bagus Cak!”.
Jadi, demo tadi bagus. Tidak alasan untuk menangkap saya. Saya pun aman ngeloyor dengan Jeep saya balik ke Patangpuluhan.
Sore itu Pak Danrem dan Pak Kapolda tidak termasuk dalam kategori “kenakalan kaum tua”, dan demostrasi “Anti Kekerasan” anak-anak mahasiswa tadi juga tidak dinisbahkan sebagai “kenakalan remaja”.
Bahkan prakarsa saya untuk menghidupkan gerakan mahasiswa dengan demonstrasi Anti Kekerasan itu oleh Pak Danrem dan Pak Kapolda dinilai “bagus”.
Itu mirip dengan di Kongres PDI di Asrama Haji Surabaya tahun 1993, di mana bersama Gus Dur dan Eros Djarot, saya melalukan “subversi“ supaya Suryadi lengser dan Megawati naik menjadi Ketua Umum PDI.
Termasuk dengan melibatkan “jimat” seorang Kiai Madura yang kita taruh di dalam tas hariannya Bu Mega untuk doa kelancaran dan perlindungan.
Sesudah saya diminta orasi dalam Kongres itu, saya ditangkap oleh serombongan TNI-AD. Digelèndèng ke ruangan yang ada Kolonel Satriya, Komandan pengamanan Kongres pada waktu itu.
Kolonel Satriya nyengèngès begitu saya masuk dan berkata: “Kalau nggak dengan cara ini bagaimana mungkin saya bisa ketemu dan ngobrol dengan Cak Nun”. Akhirnya dia mengajak ngobrol kekeluargaan cukup panjang.
Satriya adalah putranya Pak Rauf, Brigjen Anumerta yang dulu Bupati Polmas dan senior TNI di satuan Hasanudin Makassar. Beliau segenerasi dan seiring dengan pahlawan kesucian moral saya yakni Pak Baharudin Lopa. Sering saya menginap di rumah mereka. Bahkan Kurni, kakaknya Satriya yang stres tidak keluar rumah 3 tahun lebih, suatu malam saya paksa ikut ke acara saya dan saya perkenalkan kepada hadirin. Sedemikian rupa sehingga Kurni mulai bisa tersenyum, kepercayaan dirinya kembali, sampai kemudian mau bekerja dan sekarang di Mamuju, ibukota Sulawesi Barat.
Kenakalan Remaja dan Kenakalan Kaum Tua bisa dipetakan juga menjadi Kenakalan Rakyat dan Kenakalan Pemerintah. Kalau saya berkisah tentang pencekalan yang saya dan Dinasti dan KiaiKanjeng alami, ternyata bukan pasti kenakalan Pemerintah yang terjadi.
Di Kongres PDI 1993 Surabaya itu yang terjadi adalah kemesraan. Memang ada kami alami semacam nuansa kenakalan pemerintah dengan berbagai pencekalan termasuk di Mandar, di Lampung, Surabaya, dan Yogya sendiri. Bahkan ada era saya dilarang masuk Jawa Tengah. Tetapi itu diaplikasikan tanpa mengerahkan tentara dan polisi ke terminal-terminal dan jalanan untuk memeriksa apakah saya masuk Jawa Tengah atau tidak, sehingga saya tetap juga ke Semarang, Purwokerto, Pati atau Solo.
Di depan mata kepala saya sendiri saya pernah mendengar Pak Rauf menelpon Kodim di Makassar marah-marah dan memperingatkan tidak usah macam-macam sama Emha, karena saya menginap di rumah Pak Rauf.
Saya mengalami banyak kejadian yang memberi pengetahuan kepada saya bahwa persaudaraan, silaturahmi kemanusiaan dan budaya, bisa lebih kuat dibanding kekuasan politik Negara.