Berakrab terhadap Al-Qur’an
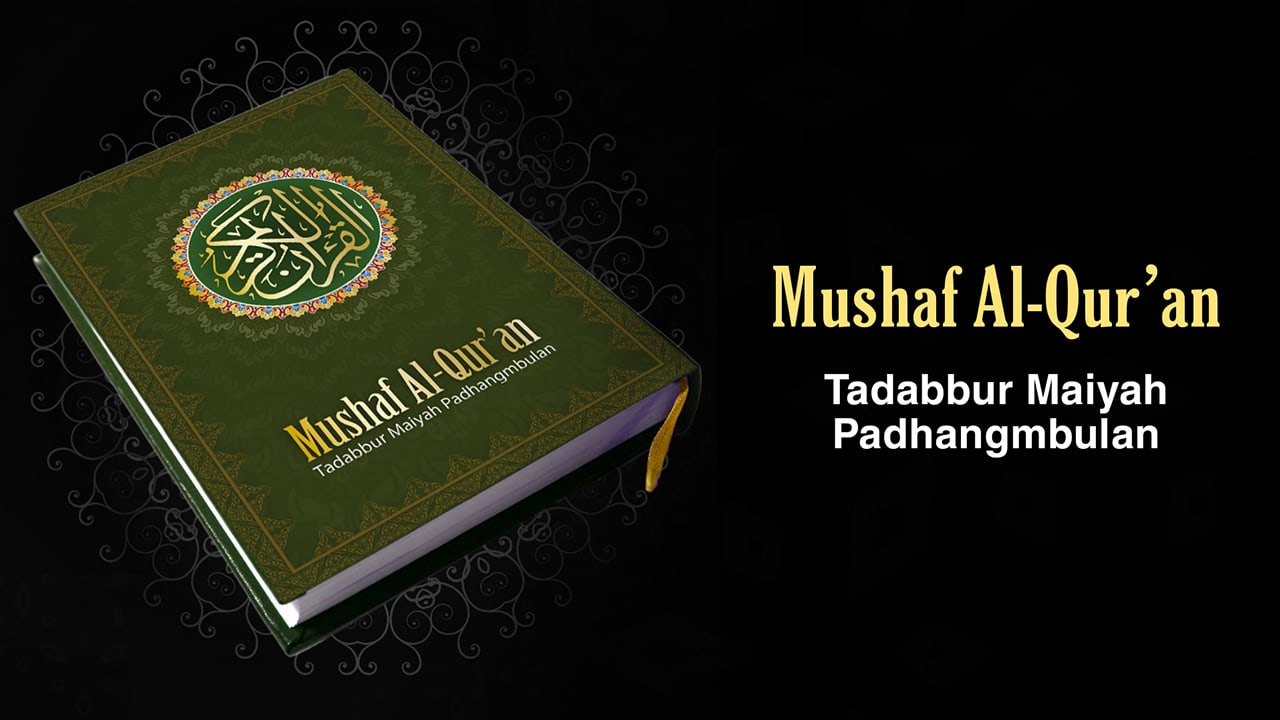
Tadabbur sebagai perenungan, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur’an memberikan wilayah imaniah amaliah lebih utama daripada tafsiran yang mengutamakan disiplin akademik. Tadabbur mengajak setiap orang tanpa pandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya untuk lebih berakrab sekaligus berkhidmat kepada Al-Qur’an.
Pertanyaan “mengapa kita berjarak terhadap Al-Qur’an?” terkesan spontan tapi sesungguhnya mengandung problem mendasar. Keberjarakan itu semakin ironis di tengah negeri yang hampir setiap saat memutar tartil kalam suci pada acara lelayu, pembukaan seminar keislaman, maupun industri pengajian di layar televisi. Daftar ini dapat diperpanjang sampai pelembagaan (kajian tafsir) Al-Qur’an, baik berdiri mandiri maupun menginduk perguruan tinggi tertentu.
Kemunculan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) pada tahun 1972 menandai salah satu bentuk pelembagaan itu. Tiga sampai empat dekade berikutnya, paling belakangan, diikuti oleh maraknya lingkaran-lingkaran “pemuda hijrah” yang tergabung ke dalam Gerakan Pemuda Hijrah dan Muslim United.
Wacana “hijrah” di kalangan artis melebar hingga kaum muda kelas menengah urban. Dalam tiap helatan acara akbar di setiap kota mereka tak luput menukil Al-Qur’an dengan berbagai terjemahan maupun keanekaragaman tafsirannya.
Pada lingkup paling kecil, di berbagai kampus swasta serta negeri di tanah air, gerakan dakwah berbasis liqa selama dua dasawarsa semakin menguat. Eksistensi kelompok yang acap mendaku diri bahwa lingkarannya merupakan sarana membangun serta merawat beribadah dan berdakwah itu bergerak secara rapi — diperkuat oleh relasi personal antara murabbi dan mutarabbi.
Terlepas dari stigma yang dilekatkan kepada mereka, terutama afiliasi politik praktis eksternal kampus apa yang memberikan sokongan di belakangnya, diakui atau tidak gerakan tersebut memperkuat politik identitas gerakan dakwah kampus.
Walaupun telah bertransformasi, tidak sebagaimana gerakan tarbiyah ala 80-an dan 90-an, kecenderungan keduanya berpaut erat. Basis gerakan mereka semakin mencair. Lebih mengakomodir medium dakwah yang ramah akan budaya pop islami. Terlebih semenjak terartikulasikan ke dalam kegiatan Islamic Book Fair, donasi trans nasional yang mendramatisir warga Palestina, kemunculan Indonesia Tanpa Pacaran, hingga gerakan pemuda hijrah.
Semua fenomena itu saling berkait dan beririsan. Kendati tidak selinier siapa memengaruhi siapa, kejadian satu bedampak kejadian berikutnya, benang merah antarperistiwa dalam konteks produksi pengetahuan pun memperlihatkan kesamaan pola.
Al-Qur’an memang tetap dipakai sebagai rujukan utama. Namun, ia tetap disertai “catatan kaki” berupa kitab tafsir yang di dalamnya mencakup metodologi ketat. Antara lain empat macam tipe seperti metode tahlili (analitis), metode ijmali (global), metode muqarin (perbandingan ayat dan hadis), serta metode maudhu’I (tematis).
Keempatnya disodorkan masing-masing kitab tafsir, baik memproyeksikan secara keseluruhan ataupun sekadar memuat permetode pendekatan. Hampir kurang terdengar di antara mereka yang memegang Al-Qur’an dengan tadabbur. Kalaupun memakai tadabbur, terkesan sayup-sayup, informal, serta dipakai sekadar untuk diri sendiri.
Dengan kata lain, tafsiran menempati posisi hegemonik ketimbang tadabbur dalam diskursus pengkajian Al-Qur’an di Indonesia. Mengapa demikian? Saya menduga sejauh ini kecenderungan beragama di Indonesia semakin mengakademik. Standar beragama kemudian ditentukan oleh seberapa meyakinkan teks keagamaan itu dibicarakan di ranah penafsir yang dinilai otoritatif.
Akibatnya, bukanlah mengherankan kalau akhir-akhir ini atau mungkin sudah bertahun lamanya orang rajin menghakimi apa dalilnya, jangan menafsirkan Al-Qur’an tanpa mufasir yang kompeten, dan pernyataan sejenis lainnya. Hal itu mengimplikasikan keberjarakan antara Al-Qur’an dan pembaca. Orang menggumuli Al-Qur’an seakan-akan harus dengan “calo” berupa versi tafsir tertentu atau mazhab yang dianggap otoritatif.
Pelembagaan Agama dan Tafsiran
Barangkali kalau ditelusuri ke belakang, hulu atas permasalahan di atas dimulai ketika agama berangsur terlembagakan (lihat, kajian-kajian yang ditulis Syaikh Kamba). Pelembagaan agama ini tidak mungkin tidak terikat oleh bagaimana kekuasaan dioperasikan.
Agama dinilai efektif sebagai wahana penyebaran bukan hanya nilai-nilai transendental di dalamnya, melainkan juga kepentingan kekuasaan saat itu. Kelahiran konsep aristokrasi maupun negara modern tak luput mendayagunakan lembaga agama berikut aparatus di dalamnya untuk menjangkar lebih luas pengaruh kekuasaannya.
Sejarah kolonialisme merupakan contoh relevan dalam menjelaskan bagaimana pendudukan suatu wilayah didorong oleh penyebaran agama, di samping kepentingan ekonomi-politik yang turut menyertai misi tersebut. Namun demikian, agama pula yang memperkuat perlawanan sipil terhadap kolonialisme.
Sebagai contoh, agama Islam di abad ke-19 justru radikal dan progresif dalam menanamkan spirit “jihad” di tanah Hindia-Belanda. Agama Islam, dengan demikian, mengukuhkan primordialisme melawan kebengisan kolonial. Waktu itu perlawanan berbasis nasionalisme belumlah menyeruak, sehingga agama Islam diyakini merupakan satu-satunya perekat kohesi sosial, suatu bentuk paling efektif dalam memobilisasi umat.
Perang Diponegoro (1825-1830 masehi) menunjukkan bagaimana radikalisme pemimpin kharismatik bersama tokoh ataupun kiai pedesaan bersama penduduk setempat melawan habis-habisan kolonial Belanda. Bagi penguasa kolonial, perang itu merupakan tonggak bahu-membahu antara elit politik serta rakyat di bawah bendera Islam. Begitu pula terjadi di dalam Perang Padri maupun Perang Aceh di Sumatera.
Itulah sebabnya, pemerintahan Hindia-Belanda mulai menjajaki strategi “politik ilmu pengetahuan” melalui pelembagaan Javanologi. Para orientalis berdatangan, salah satunya Cohen Stuart dan Theodore Pigeaud. Keduanya melakukan pengkajian naskah Jawa sekaligus memproduksi pengetahuan tentang citra Jawa yang adiluhung dan berupaya memisahkan Jawa dengan Islam.
Nancy K. Florida dalam bukunya berjudul Jawa-Islam di Masa Kolonial: Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa (2020) menyebut proyek Javanologi sebagai upaya melayani kepentingan kekuasaan kolonial dalam membingkai kebudayaan adilihung asli Jawa dan dibermaknakan vis-à-vis dengan Islam. Bukan tidak mungkin pula trikotomi santri, abangan, dan priyayi yang disusun Clifford Geertz terpengaruh produksi pengetahuan para orientalis sebelumnya.











