Anak Muda Urban Pembaca Buku Cak Nun
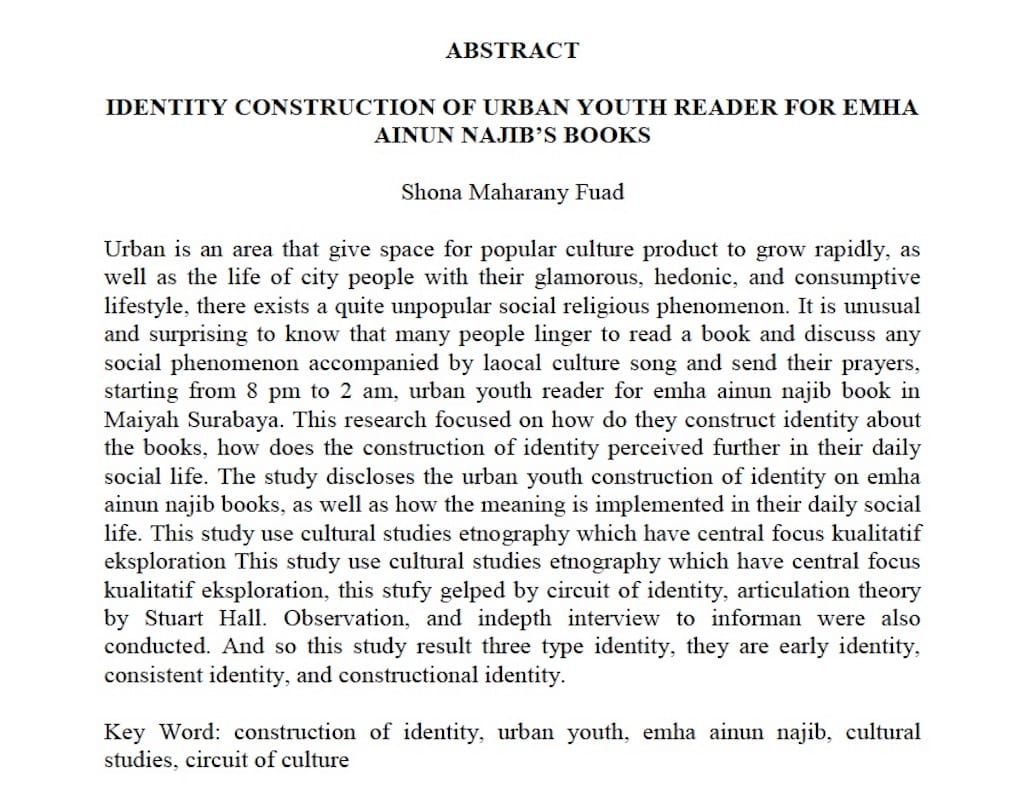
Di tangan pembaca yang aktif, karya-karya Cak Nun mendorong ruang kontemplasi sekaligus artikulasi. Pada gilirannya ia membentuk sebuah identitas tertentu.
Maiyah begitu banyak memberikan inspirasi bagi sejumlah mahasiswa di kampus. Inspirasi itu beraneka warna. Menyembul dalam bentuk gagasan, gerakan, maupun ketenangan. Maiyah Ibarat sumur ilmu. Setiap air yang ditimba selalu menyegarkan. Banyaknya air yang diambil bukan lantas membuat sumur itu lekas mengering. Keberkahan itulah yang acap dirasakan kebanyakan orang. Walau sebagian saja yang merasa menyadari keistimewaan tersebut.
Seorang teman di kampus dulu pernah membuat kelompok studi di fakultas. Ia menamai kelompoknya sebagai Kenduri Ilmu. Namanya sekilas tak asing bagi jamaah Maiyah. Benar. Kawan itu terinspirasi dari nama Kenduri Cinta. Ia memang aktif menyimak via daring helatan simpul Maiyah di Jakarta itu, di samping lumayan sering bertandang ke Mocopat Syafaat. Salah satu drive di laptopnya bahkan menyimpan tayangan-tayangan Maiyah yang ia bagi berdasarkan tema bahasan ke dalam folder secara alfabetis.
Lingkaran diskusi Kenduri Ilmu ini rutin membincangkan buku-buku Cak Nun. Buku klasik berjudul Sastra Yang Membebaskan: Sikap terhadap Struktur dan Anutan Seni Moderen Indonesia (1984) sampai didedah sebulan penuh. Perminggu satu bab. Para mahasiswa yang ingin ikut melingkar diwajibkan membaca. Mereka tak boleh datang tanpa bekal pengetahuan. Minimal ketika berpartisipasi dapat merespons isi buku Cak Nun sesuai bab yang sebelumnya telah disepakati.
Kenduri Ilmu tampak sebagai klub buku. Sebuah identitas suatu komunitas yang lazim dipakai di beberapa perguruan tinggi. Mereka memang berpretensi ke arah “produksi pengetahuan” yang secara konsisten menggumuli pemikiran-pemikiran Cak Nun melalui karya tulisnya. Seusai berdiskusi, hasilnya tak dibiarkan menguap begitu saja. Mereka menulis esai atas tanggapan, pendalaman, maupun elaborasi dengan pemikiran lainnya. Hasil publikasinya lalu diedarkan di media sosial masing-masing.
Fenomena para pembaca buku Cak Nun dalam lingkaran diskusi semacam ini ternyata terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu penelitian yang membentangkan topik demikian ditulis oleh Shona Maharany Fuad dalam sebuah artikel ilmiah bertajuk Konstruksi Identitas Anak Muda Urban Pembaca Buku Emha Ainun Nadjib (Journal UNAIR, 2017). Ia membatasi cakupan penelitiannya di Surabaya, sebuah kota yang disebutnya banyak kalangan anak muda beridentitas urban.
Di tengah hiruk-pikuk perkotaan yang waktu seakan berlari amat kencang, sejumlah anak muda di Surabaya itu justru menghabiskan malamnya untuk membaca buku sekaligus diskusi semenjak pukul 8 malam sampai 2 pagi. Partisipasi mereka dinilai Shona sebagai suatu fenomena yang “janggal dan mengherankan” tapi begitu kuat kesungguhan yang anak muda itu jalankan. Shona menyorot aktivitas klub baca ini dalam kesinambungan bingkai praktik konsumsi, produksi, dan representasi yang pada gilirannya mengonstruksi identitas anak muda.
Sebagai penelitian etnografi, khususnya mengakomodir lanskap teoretis kajian budaya (cultural studies/em>), early identity, consistent identity, dan constructional identity. Bagaimana temuannya?
Pertama, identitas pemula. Tipe pembaca buku Cak Nun seperti ini cenderung reseptif. Mereka merasa masih kesulitan dalam menangkap serta mencerna tulisan Cak Nun karena kekurangan daya imajinatif manakala mengikuti struktur bacaan, ungkapan metaforis, serta lompatan isi tulisan. Pembaca yang demikian masih mengikuti tulisan Cak Nun secara linier, sehingga kurang merengkuh “arah diskusi dan tulisan” di dalamnya (lihat, hlm. 10).
Kedua, identitas tetap. Pembaca model demikian sudah mampu memetik “makna intrinsik” tulisan Cak Nun. Misalnya, ketika mereka membaca dan mendiskusikan buku Tuhan pun Berpuasa, dirinya dapat memberi makna bahwa esai tersebut membicarakan bagaimana Tuhan menahan diri untuk menghukum manusia, walaupun Dia memiliki otoritas untuk melakukan itu.
Namun, ada hal menarik di sini. Anak muda yang lebih pada identitas tetap cenderung melakukan praktik konsumsi secara tebang pilih. Mereka menyortir tulisan dan pesan Cak Nun sesuai “porsi” kebutuhan yang dikehendaki. Atas petikan tulisan yang tersortir itu mereka kemudian melakukan refleksi lanjutan lewat menulis esai ataupun puisi. Bahkan mereka mampu menerapkan “kearifan Maiyah” dalam laku keseharian.
Shona menguraikan lebih lanjut soal ini: “…[mereka] menyelesaikan suatu persoalan dengan pisau analisis Cak Nun yakni meluaskan hati, melebarkan analisa dan berpikir sederhana.” Bak inspirasi menjalani kehidupan sehari-hari, tulisan Cak Nun telah dianggapnya sebagai sebuah pedoman, bahkan prosedur yang bernilai konkret diterapkan.
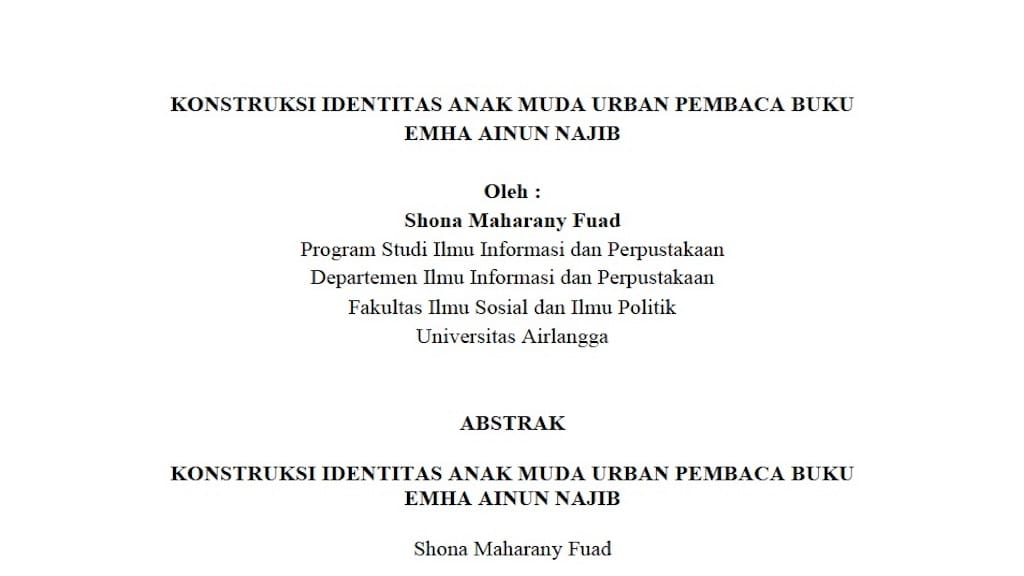
Ketiga, identitas terkonstruksi. Tipe pembaca terakhir ini mampu menangkap informasi di dalam tulisan Cak Nun secara simbolis. Gaya bahasa yang dipakainya pun mereka gunakan dalam ucapan atau tulisan yang dihasilkan. Termasuk “gesture tubuh saat berbicara dan bahan canda yang digunakan oleh Cak Nun dalam menyampaikan suatu pesan” (lihat, hlm. 12).
Selain terinspirasi dari Cak Nun sepenuhnya, anak muda yang demikian juga mampu memberikan pesan kepada orang lain. Tentu dengan versinya sendiri dan disesuaikan dengan siapa audiens yang dihadapi. Ada kecenderungan peniruan di sini tapi tiruan itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Sayangnya Shona tidak menjelaskan mendetail bentuk hasil peniruan yang dimaksudkan. Ia sekadar memberikan abstraksi dan kurang membicarakannya dalam bentuk contoh. Khususnya contoh yang diekspresikan anak muda tipe ketiga.
Walaupun begitu, penelitian Shona termasuk ranah yang baru pertama kali dieksplorasi. Studi ini memperlihatkan betapa buku Cak Nun, selain dibaca dan didiskusikan, juga menimbulkan suatu produksi makna yang mengejawantah ke dalam tindak-tanduk sehari-hari pembacanya. Apa yang dikonsumsi dan diproduksi seusai membaca buku Cak Nun ternyata membentuk identitas anak muda urban.
Betapapun buku Cak Nun bukan sesuatu yang pasif—dibaca lalu selesai begitu saja. Di tangan pembaca yang aktif, karya-karya Cak Nun mendorong ruang kontemplasi sekaligus artikulasi. Keduanya itu membentuk apa yang disebut sebagai identitas, yang mirip kasusnya sebagaimana model pemakaian jilbab kelompok menengah atas urban. Dengan demikian, identitas selalu terbentuk, terproduksi, dan terreproduksi.










