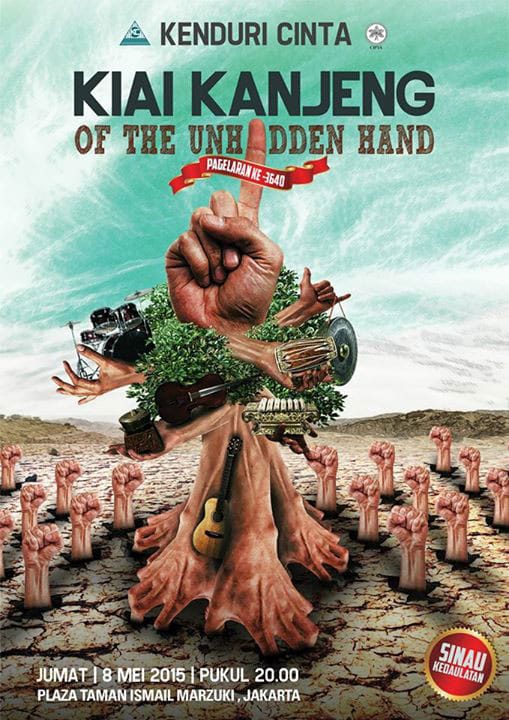Sinau Bareng Tanpa Sekat Kampus-Masyarakat

Perbedaan batas antara mahasiswa IAIN Purwokerto dan masyarakat mengabur di Lapangan Dusun Karanggintung, Sumbang, Banyumas. Kondisi ini disengaja agar kampus tak bertengger di atas awan yang kerap kali mengurusi diktat akademik dan tetek-bengek birokrasi. Aktivis Dewan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Dakwah, berada di belakang sebagai motor penggerak, mengajak civitas akademia kampus dan masyarakat melebur menjadi satu dalam format Sinau Bareng Cak Nun dan KiaiKanjeng pada Senin malam, 6 Januari 2020.
“Sinau Bareng diadakan di lapangan umum ini dimaksudkan supaya kampus menyatu dengan masyarakat. Upaya IAIN Purwokerto agar tak bertengger di menara gading, tapi dapat melebur tanpa sekat bersama masyarakat itu sendiri. Kita kumpul bareng untuk bermunajat kepada Allah,” pesan Moh Roqib, Rektor IAIN Purwokerto.
Senada dengan Pak Rektor, Cak Nun bersyukur atas terselenggaranya Sinau Bareng dalam rangka Dies Natalis ke-22, Fakultas Dakwah. “Bagaimana kondisi hatimu sekarang? Pikiranmu sedang gelap atau terang? Mudah-mudahan semua getaran-getaran yang benar, baik, dan indah dalam dirimu menguap ke langit dan sampai sana diantarkan malaikat kepada Allah dan dibalikkan ke sini menjadi berupa rezeki dan berkah,” harapnya.
Di depan puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat, Cak Nun menguraikan pentingnya Sinau Bareng Menurut Cak Nun, Sinau Bareng bertujuan agar tiap orang saling menginformasikan satu sama lain. Selama ini di pengajian-pengajian konvensional selalu terdapat garis pembatas. Anggapan yang di atas selalu lebih pintar ketimbang yang di bawah dibongkar format Sinau Bareng. Konsep Sinau Bareng cenderung egaliter, menghargai perbedaan, dan saling menyelamatkan.
“Kalau di forum-forum lain, pembicara dan audiens diperjarakkan. Namun, di Sinau Bareng, kedua komponen ini saling memperkaya pengetahuan. Saya berharap sinau malam ini dapat kita petik manfaatnya,” ucap Cak Nun.
Jajaran rektorat dan dekanat IAIN Purwokerto menyentil perubahan status birokrasi kampus. Sejarahnya sedemikian panjang. Sejak tahun 60-an. Mulanya merupakan bagian dari IAIN Sunan Kalijaga, pada gilirannya berangsur makin independen. Lini masa kampus diawali oleh status STAIN, IAIN, dan kini menuju UIN.

Merespons transformasi STAIN, IAIN, dan direncanakan akan distatuskan sebagai UIN, Cak Nun bertanya apa perbedaan STAIN, IAIN, dan UIN kepada civitas akademia. Ia menggali apakah perubahan format kampus sekadar urusan birokrasi atau justru lebih fundamental. Cak Nun kerap mewacanakan kalau kampus-kampus sekarang hanya meluluskan sarjana “fakultatif”, alih-alih “universiter” yang lebih komprehensif jangkauannya.
Kalau kampus telah melegitimasikan diri sebagai universitas, menurut Cak Nun, hendaknya memosisikan diri secara universal, baik keilmuan, pikiran, tindakan, maupun implementasinya di masyarakat. Hal ini menjadi tugas dari civitas akademia untuk merumuskan kembali pemahaman akan universitas tempat studi maupun pengabdian. Cak Nun meredefinsikan pemahaman elementer universitas yang bukan sekadar predikat, melainkan lebih pada jangkauan universalnya.
Tumbuh Bersama
Dalam praktik kehidupan, baik di kampus maupun masyarakat, mustahil tiap individu tecerabut secara sosial. Antarmanusia niscaya saling membutuhkan. Cak Nun bertanya dengan ilustrasi sederhana. “Apakah di antara Anda ada yang membuat bajunya sendiri?”
Tak ada jamaah yang mengangkat tangan. Ia melanjutkan betapa pentingnya Sinau Bareng itu. Mengurus sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), lanjut Cak Nun, manusia tak mungkin sendiri. Pada kehidupan ini tak ada orang yang berdiri sendiri. Semua selalu saling membutuhkan melalui pembagian peran masing-masing. “Manusia saja dalam bersinggungan dengan Allah mempunyai kekhasan tersendiri. Ada yang sendiri dan ada yang bersama,” jelasnya.
Lebih spesifik, Cak Nun mengajak audiens berpikir historis agar memetik hikmah tertentu. Ia menjelaskan perbedaan tiap Khulafaur Rasyidin dalam “menemukan Allah”. Pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq disebut Cak Nun manusia kultural, manusia proses, manusia bebrayan, atau manusia sesrawungan. Maka untuk menemukan kebesaran Allah, ia melakukan persentuhan langsung dalam kehidupan sosialnya. “Ia sangat bijak dalam pergaulan,” katanya.
Kedua, Umar bin Khattab membutuhkan sesuatu yang radikal, sehingga manakala bersinggungan secara keras dengan sesuatu, ia akan ingat kebesaran Allah. Ketiga, Utsman bin ‘Affan cenderung menemukan Allah setelah menimbang-nimbang. Keempat, Ali Bin Abi Thalib selalu menyadari tiap langkah dalam hidupnya merupakan kesadaran perjumpaan dengan Allah. “Ia tidak pernah tidak ketemu Allah. Melihat, mendengarkan, maupun mengalami apa saja selalu ingat Allah,” tuturnya.

Jamak nilai yang dapat diteladani dari keempat Khulafaur Rasyidin. Setidaknya nilai partikular tiap individu yang memiliki kekhasan masing-masing. Demikian pula dalam mengoneksikan kesadaran hamba kepada Tuhan.
“Apakah shalat harus dilakukan saat sekadar ingat Allah? Apakah agar ingat Allah harus menunggu waktu shalat atau dapat kapan saja? Apakah kita bisa menghadirkan kehangatan Allah pada situasi-kondisi apa pun, sebagaimana manakala diselenggarakan Sinau Bareng saat ini? Maka di lapangan ini kita berkumpul beribu-ribu orang tak perlu kekhusyukan seperti di masjid, namun tetap Allah hadir di dalam jiwa dan kesadaran kita,” pungkas Cak Nun.