Sabana Maiyah di Tengah Langkanya Majalah Sastra

Saat peluncuran alih majalah sastra Horison dari cetak ke on line, Emha Ainun Nadjib memberikan orasi menarik. Bagaimana sakralnya Horison saat masih cetak, puisinya dimuat rasanya seperti naik haji. Sekarang setelah on line apa masih seperti itu.
Ini majalah sastra satu-satunya di Indonesia. Alasan apa yang membuat Horison menghentikan edisi cetak. Banyak dugaan, karena ketiadaan dana. Kemudian pertanyaan klasik: siapa mau membaca majalah sastra. Ditambah arus media on line yang menggerus hampir semua media cetak. Kecuali mereka yang ibarat kerajaan mall dengan berbagai lapak besar tetap profit.
Banyak orang lupa, bahwa dunia sastra ialah dunia kemanusiaan mendunia. Di era orde lama orang menyebutnya sebagai jagad humanisme universal. Mudahnya, kalau kita sakit dicubit, Britney Spears juga merasa sakit sama saat saya cubit.
Bagaimana masyarakat dunia mengenal kebudayaan Indonesia. Tak lain melalui karya sastra. Bagaimana kritikus sastra Prof. A. Teeuw misalnya, mengenalkan puisi-puisi Chairil Anwar ke hadapan dunia. Perjuangan bangsa dalam melawan penjajah, dalam sajak “Diponegoro”. Keakuan manusia Indonesia dalam sajak “Aku” yang terkenal itu: aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Hubungan manusia Indonesia dengan orangtua dalam sajak “Nisan”, justru puisi pertama yang ditulis Chairil:
Bukan kematian benar menusuk kalbu
Keridlaanmu menerim segala tiba
Tak kutahu setinggi itu atas debu
dan duka maha tuan bertahta
Atau bagaimana sifat wanita Indonesia seaslinya seperti yang digambarkan Pramoedya Ananta Toer, melalui tokoh Nyai Ontosoroh dalam novel “Bumi Manusia”. Tokoh manusia muda Indonesia progres komplit dalam tokoh Minke. Lalu kolonialisme anti regenerasi yang digambarkan melalui simbolisasi tokoh Anelis.
Pada 1990-an A. Teeuw pernah mengusulkan tetra novel Pram — Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca — untuk menerima hadiah Nobel. Tetra novel yang justru lahir dari peristiwa politik 1965 lanjut kekuasaan otoritarian sang despot jendral besar Soeharto di era Orde Baru, yang menimbulkan ribuan korban penyiksaan dan nyawa. Termasuk Pram sebagai korban pemasungan kreativitas, walau karyanya itu mendunia.
Pada tahun-tahun itu, 1964-1967, seorang penyair Indonesia terkemuka, WS Rendra, justru dikirim ke Amerika. Hasilnya sajak-sajak panjang Rendra yang bicara peristiwa sehari-hari dengan bahasa keseharian. Bagaimana dia melihat dunia kapitalisme dalam puisi “Rick dari Corona”, dan pemberontakan perlunya kedaulatan kreativitas di tengah politik ABG (Amrik Baru Gede) dalam puisi “Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta”.
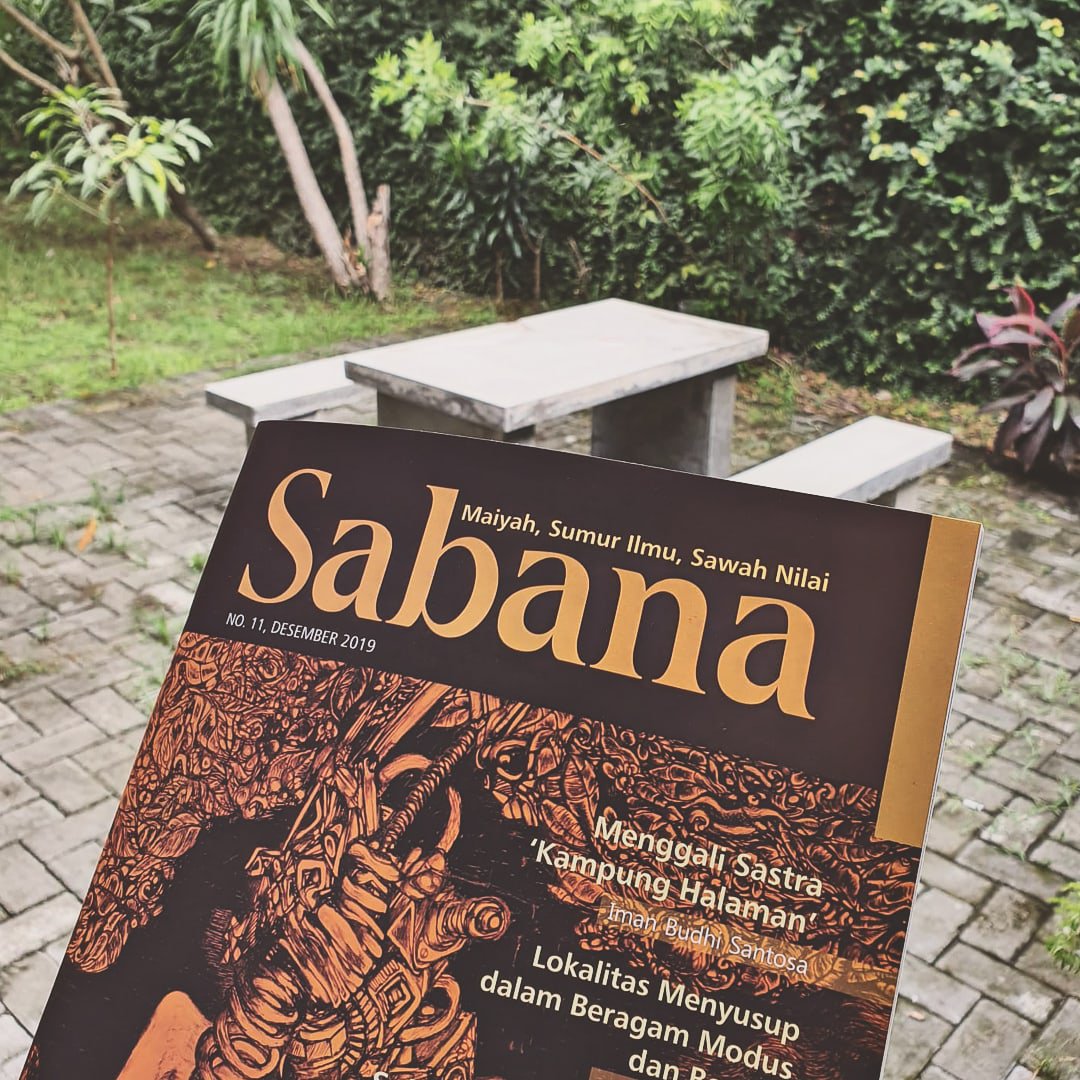
Demikian sastra Indonesia telah menjadi bagian sastra dunia. Untuk itu pemerintah perlu mengirim sastrawan kita dan karyanya ke luar negeri. Taruhlah sejak Rendra hingga Emha Ainun Nadjib. Untuk apa guna dengan gagah mengepalkan tangan di forum sastra dunia, di mimbar Amerika: ini aku dan karyaku, Indonesia my lovely country!
Tidak seperti sesudahnya, mereka yang serupa pengemis meminta-minta jatah dollar, sambil menjual form atraksi bahasa dan content gaya lebay nusantarania. Baik dilakukan perseorangan atau lembaga.
Dalam orasi di acara Horison itu secara guyon Emha bertanya: apa saat kita membuka kitab suci di on line kita juga perlu ambil air wudhu. Sebenarnyalah itu isyarat bahwa kitab, bukan sekadar majalah, tapi bahwa sastra mengemban kebudayaan sebagai institusi dan nilai. Bukan semata nilai keindahan, tapi juga kekuatan sebagaimana politik, ekonomi, hukum, dst.
Dalam pada itu saya menunggu, Emha menyampaikan hal terpenting, bahwa dirinya dengan penerbit Progressnya telah menerbitkan majalah sastra Sabana. Sebab, betapapun, itu salah satu hal terpenting yang seharusnya dilakukan negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia di tengah pembangunan meraksasa infrastruktur.
Ya, bukankah kita juga perlu mengapresiasi adab-budaya bangsa melalui karya sastra. Melalui majalah sastra, sebagai aset sekaligus invest bangsa. Bukankah pemerintah mesti memberi dana untuk majalah sastra Horison.
Tapi mengapa pemerintah menisbikan dua hal terpenting. Yakni persaudaraan berbangsa, dan apresiasi intitusi dan nilai kebudayaan melalui media sastra.
Mengapa dua hal penting yang mestinya menjadi tanggung jawab negara, justru dilakukan oleh Maiyah Cak Nun dan KiaiKanjeng: lingkaran persaudaraan sinau bareng Maiyah dan penerbitan majalah sastra maiyah Sabana.
Tapi hingga selesai orasi, hal itu tidak disampaikan Emha. Entah lupa, atau memang nggak mau tepuk dada.







