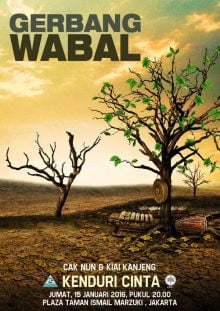Blahi Selamet dan Agama yang Dilembagakan

Untuk diri saya sendiri saya punya pertanyaan: sampai tahap kesejahteraan seperti apa manusia merasa aman atas hidupnya? Menjalani model hidup penuh ketenteraman hingga bagaimana manusia benar-benar aman sehingga ia tidak lagi bergantung pada Tuhan?
Anda bisa langsung menebak bahwa pertanyaan itu cukup kental dengan aroma sekularisme. Tidak salah, karena berkembangnya sekularisme dan melemahnya agama di Eropa tidak disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan. Sekularisme berkembang setelah kebutuhan dasar dan rasa aman masyarakat terpenuhi.
Tulisan ini mengambil jarak pandang dari sekularisme ketika nilai Islam dipahami secara tidak tepat, disalahpahami, dijadikan bahan Islamophobia. Bagaimana memandang Islam tidak terutama sebagai konsepsi sistem aqidah (al-‘aqidah) dan teologi yang sarat dengan aliran dan klaim pembenaran. Islam adalah ruang rahmatan lil ‘alamin bagi hidup manusia.
Kalau dipandang dari sisi kaum muslim, kita berhadapan dengan kenyataan al islamu mahjubun bil muslimiin. Islam tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Apa yang tertutupi dari Islam? Ya keindahan dan keagungannya, ya kedalaman dan keluasannya, ya keutuhan dan keseimbangannya.
Namun, pada konteks yang lain, menurut pelaku sekularisme, manusia Indonesia adalah manusia “tidak masuk akal”, tidak rasional, karena menjadikan Tuhan dan agama sebagai gandolan utama. Orangnya nekat-nekat. Jangankan kebutuhan dasar yang terjamin, soal keselamatan hidup kita nekat menerabasnya cukup berbekal “Bismillah”, baca jopo montro: “Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo,” kemudian nggedruk tanah tiga kali.
Sebagai warga negara kebutuhan dasar memang belum dipenuhi seutuhnya oleh negara. Namun sebagai warga masyarakat, warga kampung, warga dusun, warga RT/RW apalagi sebagai manusia Nusantara, mentalitas orang kita sungguh ngedap-edapi.
Kita menyaksikan seorang ibu berjualan beberapa botol air mineral untuk penghidupan primernya. Seorang Kepala Sekolah tidak segan bakulan rosok sepulang mengajar di sekolah. Sedangkan menurut pandangan pemerintah pekerjaan sampingan Pak Kepsek dianggap simbol kemiskinan sehingga ia perlu diberdayakan. Padahal para guru yang umek soal tunjangan tidak lebih berdaya dibandingkan kemandirian Pak Kepsek.
Kalau manusia membutuhkan Tuhan dan agama karena tidak mampu mengatasi ketidakpastian hidup, apakah sedemikian sederhana hidup ini — yang dimensi, lipatan, tikungan, terang dan gelapnya diselesaikan cukup dengan memenuhi kebutuhan dasar? Sehingga semakin aman hidup seseorang, Tuhan dan agama semakin ditinggalkan? Lagi pula, mengapa kita hidup? Bagaimana menerapkan sekularisme secara kaffah dalam hidup?
Persoalannya bukan pada aman atau terancam, kaya atau miskin, sehat atau sakit, melainkan pada keadaan apapun kita ridlo atau tidak.
Sikap ridlo ini mengatasi kecemasan dan ketidakpastian dalam hidup. Orang Jawa mengatakan, “Blahi selamet yang patah bukan kakinya.” Kalau bukan hasil dari refleksi penghayatan dan perilaku mendalam atas sikap ridlo rasanya mustahil muncul blahi selamet — satu-satunya “bahasa tauhid” di dunia.
Blahi, berasa dari kata billahi, berkat Allah atau sebab (pertolongan) Allah. Berkat Allah orang itu selamat. Sebab pertolongan Allah orang itu masih bisa berjalan. Billaahi atau lidah Jawa mengatakan blahi adalah wujud sikap ridlo atas apa yang terjadi dan menimpa manusia.
Zaman saya kecil billahi adalah sumpah yang diucapkan untuk meyakinkan teman bermain. “Billahi, ciker bungker, aku gak ndelikno sandalmu.” Maksudnya, Demi Allah, ciker bungker, saya tidak menyembunyikan sandalmu. Setelah sumpah diucapkan barulah teman kita percaya. Dalam situasi bermain bersama teman pun kita melibatkan Allah.
Entah sejak kapan dan siapa pembawa sanad sumpah billahi menjadi bagian dari dinamika komunikasi. Pokoknya, sumpah itu kami ucapkan begitu saja, dan kami sungguh-sungguh mengucapkannya walaupun situasinya dalam keceriaan bermain.
Saya dan kawan-kawan sepermainan tidak atau belum mengerti makna lughowi, etimologi dan epistemologi kata billahi. Yang saya rasakan adalah desir aneh dalam dada manakala mengucapkan kata yang sakral itu. Setelah satu persatu kami mengucapkannya baru terkuak siapa yang menyembunyikan sandal. Seorang kawan tidak tatag untuk mengucapkan billahi. Ia pun mengaku dan minta maaf.
Apakah saya dan kawan-kawan takut berdosa? Iya — walaupun sistem kepercayaan kami belum selaras dengan cara berpikir tentang konsepsi sifat Tuhan, seperti Dia Maha Mengetahui segala perbuatan manusia. Sistem narasi nilai ajaran agama lebih dahulu merasuk ke dalam kesadaran anak-anak ketimbang sistem logika bahwa Tuhan itu Ada.
Hal itu tidak berarti kami menjawab: “Tidak ada” ketika ditanya apakah Tuhan itu ada? Kualitas iman model anak kecil yang akalnya belum jangkep tidak memenuhi syarat aqidah. Kendati demikian sistem nilai tentang kejujuran, ketaatan, kebaikan menuntun perilaku sehari-hari. Baru setelah aqil baligh saya belajar menemukan dalil aqli dan naqli tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya.
Bagaimana sistem nilai ajaran Islam bisa mendahului sistem aqidah? Budaya langgar, atau meminjam istilah Mbah Nun, sastra langgar, zaman dahulu benar-benar hidup. Aneka cerita, dongeng, dan kisah seperti Uthek-uthek Ugel, Kasan dan Kusen, Gajah Obak Delik Melawan Semut, hingga cerita serem seperti Wewe Gombel, Ndas Glundhung, Cong Culi Cong — meneteskan nilai pekerti di kalbu anak-anak langgaran.
Ternyata sastra langgar cukup efektif bukan hanya untuk menyemai nilai pekerti yang baik. Kandungan hikmah cerita, dongeng dan kisah secara diam-diam membentuk fondasi aqidah yang kokoh. Tali aqidah itu mengikat dan menghubungkan setiap kisah sehingga secara diam-diam pula kami terikat olehnya.
Nuansa dan konteks belajar nilai Islam terasa kaya warna, kaya dimensi, kaya spektrum. Jauh dari suasana formal pengajian atau sekolah karena disampaikan di teras langgar sambil lesehan, klesetan dan pijet-pijetan. Dan demikianlah nilai-nilai agama bersentuhan dengan anak-anak zaman itu. Islam terasa kaffah hidup dalam pengalaman masa kecil saya.
Menjalani model hidup penuh ketenteraman hingga bagaimana manusia benar-benar aman sehingga tidak lagi bergantung pada Tuhan? Jawabannya ada pada hidup yang dirasuki materialisme dan agama yang diperlakukan sebagai lembaga, padatan, dan institusi.[] – Ach
Jagalan, 7 Desember 2020