Raksasa, Pegawai, mBilung
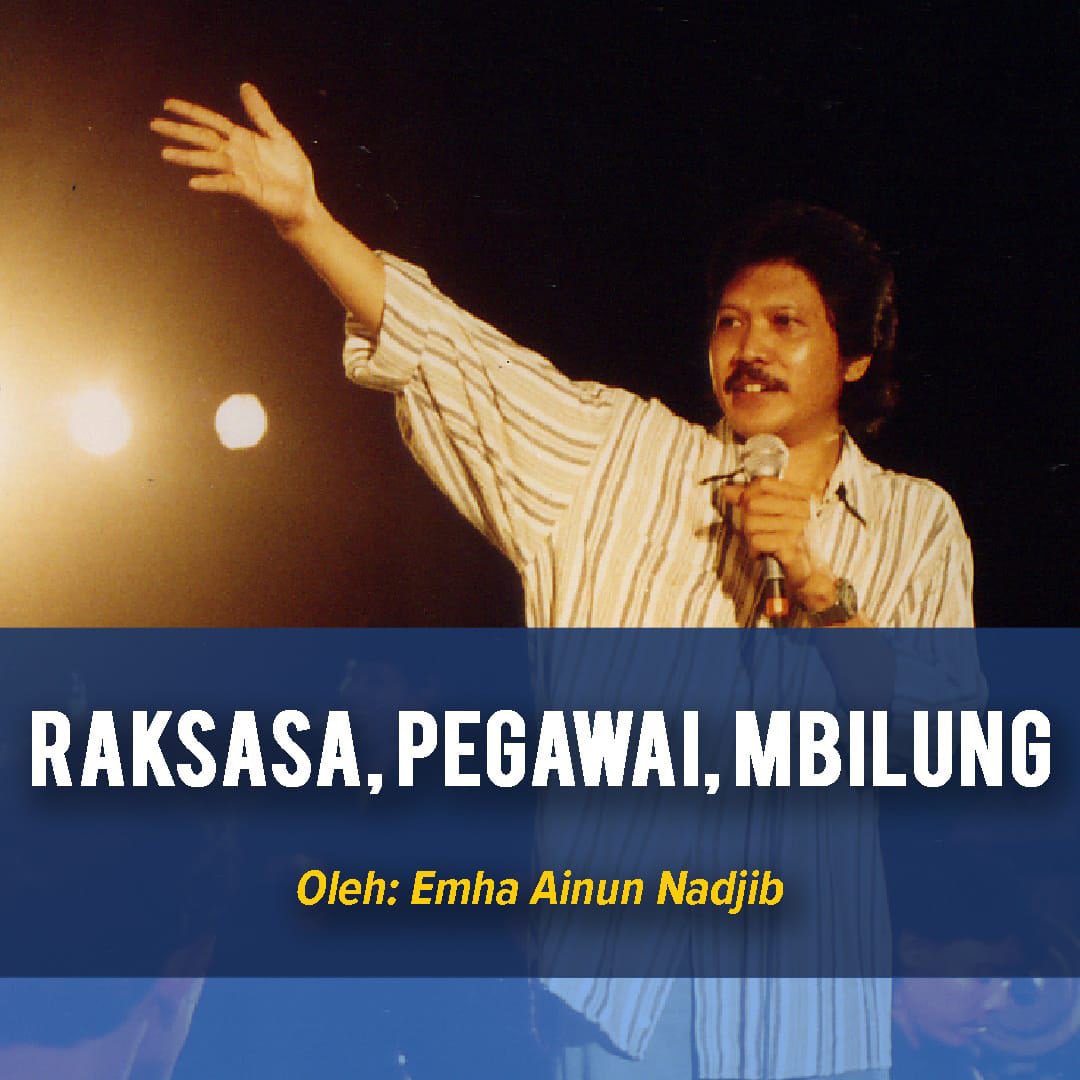
Patangpuluhan, Minggu keempat Mei 1990
TAMU jauh kita itu pada hakikatnya mengidap tiga kegelisahan yang ia sadari dan tiga kegelisahan yang tak ia sadari. Komplikasi dari keenam “penyakit” itu membuatnya tak betah hidup, irama mentalnya kacau, kesehatannya tak menentu, hatinya gundah gulana.
Tiga kegelisahan yang ia sadari ialah pemikiran yang bagai tak berujung tentang — pertama — kenapa ketidakadilan merajalela dan mengapa Tuhan ikut-ikut tidak adil karena terbukti Dia membiarkan saja begitu banyak ketidakadilan.
Kedua, segala peristiwa ketidakadilan itu diyakininya sebagai sunnatullah, sebagai takdir Ilahi, sebagai sesuatu yang memang sudah dipastikan sejak dari sononya sehingga apa pun yang diusahakan oleh manusia pada akhirnya akan sia-sia saja. Sebagai manusia yang romantis, kawan kita itu tidak pernah tahan hati menyaksikan orang sengsara atau kesengsaraan itu sendiri. “Kenapa harus ada kesengsaraan? Kalau memang Tuhan Mahakasih dan penuh cinta, mengapa tak ia ciptakan kebahagiaan dan kenikmatan saja?” protesnya.
Ketiga, lebih celaka lagi ketika dan sesudah manusia ditakdirkan untuk menderita serta mengalami segala sesuatu yang sudah Dia skenariokan; kelak harus dibagi menjadi dua golongan, yakni yang beriman dan kafir. Yang beriman masuk surga dan yang kafir dicampakkan ke dalam kedahsyatan api neraka.
Adapun ketiga kegelisahan yang tidak ia sadari adalah — pertama — ia bermaksud menjadi Tuhan, dalam arti ia ingin dunia dan kehidupan ini berlangsung sesuai dengan kemauan, kehendaknya. Itu pun peran Tuhan yang dipilihnya adalah peran “Tuhan yang egois”, yang tak mau berbagi, yang otoriter seratus persen, bahkan kepada Tuhan yang asli pun ia tak bersedia sharing kehendak.
Tuhan yang asli saja memberi peluang kepada manusia untuk menjadi wali-Nya, diberi-Nya mandat dan kemerdekaan, kebebasan untuk berpikir dan menentukan sikap sendiri, memilih dan memutuskan sesuatu. Tuhan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada manusia, sementara teman kita itu menjadi “Tuhan” yang bukan saja tidak percaya kepada manusia: melainkan bahkan tidak percaya kepada iktikad Tuhan.
Kegelisahan yang kedua adalah kegelisahan yang tolol dan sombong khas manusia. Dalam ketidakpercayaannya pada kemerdekaan yang diberikan oleh Allah itu, ia justru menjadi rontok kepribadiannya, tidak menjadi tegar, tetapi sedih dan putus asa.
Adapun kegelisahan yang ketiga tidak ia sadari — karena ia memang tak sadar memasuki suatu galaksi ilmu yang ia tidak sungguh-sungguh menguasainya — yaitu bahwa pada saat ia merambah arasy ilmu hidup secara gagah berani, ia tutup sendiri potensi-potensinya untuk realitas menerima kebenaran. Ia tidak mengerti dan tak sanggup mengikhlasi hakikat “kebenaran” dan “realitas”. Kalau daun tanggal dari tangkainya itu “realitas” dan itu adalah “kebenaran”, ia tidak bisa dibantah dan siapa pun tak usah menangis atau meratap mengapa daun itu jatuh ke bumi.
Ilmu kawan kita itu terletak pada “level prajurit”; bahwa yang beriman masuk surga dan yang kafir masuk neraka. Padahal, tidak bisa diterangkan siapa yang masuk beriman dan siapa yang kafir. Realitas “beriman” dan “kafir” disentuhnya hanya pada lapisan formalistiknya, padahal kandungan persoalan itu sedemikian kompleks — sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa betapa Allah itu Mahateliti dalam mengalkulasi segala sesuatu. Sebuah pabrik baja memiliki ketelitian sepersepuluhribu milimeter dan kelak teknologi bisa saja mencapai tingkat ketelitian sampai sepersejuta milimeter. Sedangkan, kelembutan hidup ini harus diukur melalui satuan sepertakterhingga milimeter — dan ketelitian Tuhan adalah Maha-Tak-Terhingga kelembutannya.
Itu semua bukan persoalan yang sederhana. Apalagi kawan kita itu telah menggeluti selama lebih dari dua puluh tahun. Mending Anda jadi tukang becak atau pegawai saja di kantor dan tak usah memikirkan macam-macam, segala kegelisahan yang muncul cukup Anda jawab dengan pernyataan: “Terserah Tuhanlah itu, saya pasrahkan sepenuhnya kepada-Nya. Yang penting saya bisa cari makan untuk anak istri. Soal yang ruwet-ruwet bagiku biar dimakan oleh para filsuf, pemikir, para nabi atau biar diurus oleh Tuhan sendiri. Kewajiban pokok saya hanyalah mencari nafkah yang halal, tidak peduli hidup ini aneh atau tidak, absurd atau tidak. Pokoknya saya jalani saja….”
Adapun teman kita ingin menjawab pertanyaan filosofis yang menggerunjal jiwa dan merongrong mentalnya. Jalan yang harus ditempuh menjadi terlalu panjang. Ia mengambil takaran “raksasa pemikir”, padahal kapasitas mBilung. Ia harus mempelajari ribuan buku referensi filsafat, padahal belum sepenuhnya dia baca. Ia harus menguasai berbagai informasi Allah di tiga dimensi hidup, padahal ia baru meminum seteguk — dan dia kacau karena pandangan-pandangan parsialnya. Ia harus mengimajinasikan berbagai eksperimen hidup dan sejarah yang memaparkan kepada otak kita hubungan-hubungan dialektis antara nilai dengan realitas, antara gejala mikro dengan makro, antara individualis dengan sosialis, antara sejengkal waktu dengan keabadian, antara sepetak tanah dengan ketakterhitungan ruang.
Untuk itu, ia memerlukan laboratorium raksasa untuk tiba pada sikap sehat, sehat terhadap realitas dan kebenaran. Laboratorium raksasa dan ruang waktu yang tidak main-main. Padahal, ia seorang pegawai negeri. Benturan antara tugas rutinnya dan raksasa kegelisahannya itu membengkakkan volume kegelisahan itu sendiri dan melipatgandakan kekacauan mentalitasnya.
Saya bukan dukun, psikiater, kiai, atau pakar paranormal. Juga bukan tukang sulap sebab pasti teman kita ini tidak bisa saya sulap untuk “normal” kembali. Lebih-lebih saya juga hidup di dunia ini tidak dikhususkan mengurus dia. Jadi, waktu saya amat sedikit. Keterbatasan waktu juga menentukan pola metode dan pilihan terapi. Sesudah saya “sandera” untuk tidak bunuh diri. Saya hanya tahu bahwa saya akan bikin dia shock secara pemikiran.[]







