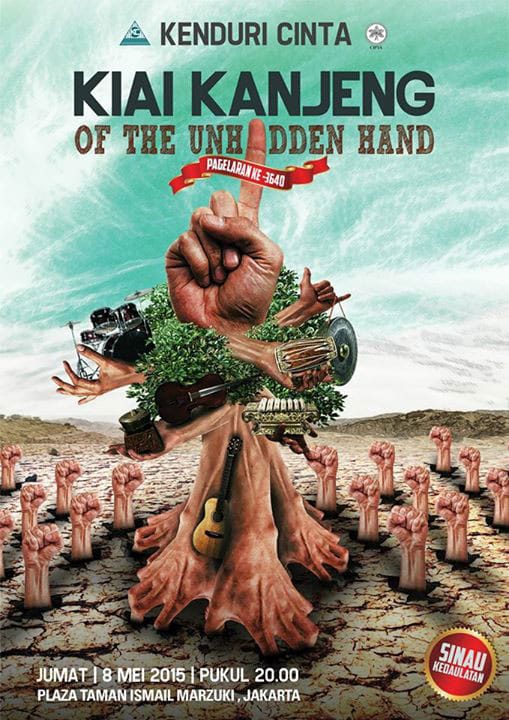Bersyukur Membuat Hidup Bermakna

Desa Bawu, khususnya RT 31/RW 06, Batealit, Jepara, pada Sabtu, 7 Desember, tak seperti biasanya. Orang mulai berduyun-duyun sejak senja, duduk lesehan beralaskan tikar di depan rumah Pak Yus. Masyarakat dari pelbagai elemen, baik muda maupun sepuh, bersiap mengikuti Sinau Bareng bersama Cak Nun dan KiaiKanjeng. Mereka menghabiskan malam minggu di sana berkat acara Tasyakuran CV. Surya Bangkit.
Acara dipandu oleh Brigadir Ratih Candra Ayu, Dinas Polres Jepara. Ia langung memberi kesempatan kepada Pak Ahmad untuk mendaras ayat suci Al-Qur’an. Warga sekitar menyimak dengan khidmat. Beberapa ikut merapal lewat Al-Qur’an digital. Penjual keliling, entah kopi atau aneka camilan, tertahan sejenak. Ia berdiri seraya menundukkan kepala, ikut menikmati orkestrasi kudus pembacaan kalam Tuhan. Pembukaan acara pun ikut memuisi.
Di panggung, ketua panitia, kepala dusun, Habib Anis, Kiai Muzammil, dan Cak Nun telah bersila. KiaiKanjeng membuka dengan munajat Shohibu Baity. Semua diajak Cak Nun agar berdiri, mengkontemplasikan sejenak, mengekspresikan kasih sayang kepada Kanjeng Nabi.
Lalu Cak Nun memungkasi. Beliau menuturkan, “Kalau bareng-bareng itu Pancasila, sedangkan demokrasi itu sendiri-sendiri.” Cak Nun mengaitkan nilai kebersamaan dengan pemaknaan terhadap Pancasila dan demokrasi. Keduanya kerap digeneralisasi, bahkan disangkutpautkan. Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki perbedaan filosofi. Ia mengajak masyarakat agar terus merenungi dan menanyakan ulang apa yang dianggap biasa di kehidupan sehari-hari.

Manakala memulai Sinau Bareng, Cak Nun bertanya kepada audiens. “Berapa saja yang sarjana, SMA, SMP, SD, atau tidak sekolah? Apa sebabnya orang pintar itu perlu bersyukur? Apa yang perlu disyukuri? Apa sebabnya orang bodoh perlu bersyukur?” jelasnya. Cak Nun mendeteksi kondisi sosiologis masyarakat apakah berada pada kategori-kategori akademik semacam itu. Dari penggayungan opini, ia kemudian menegaskan, kalau bersyukur itu tak terpaut strata sosial, tingkat akademik, atau sekat-sekat lain. “Bersyukur itu diperuntukan bagi manusia. Bagi manusia yang berpikir,” ucapnya.
Bagi Cak Nun, terdapat perbedaan yang mencolok antara manusia dan binatang. Yang membedakan antara lain adalah kemampuan berpikir. Manusia diberi bekal akal untuk berpikir. Sedang hewan dianugerahi insting. Letak perbedaan itulah yang Cak Nun uraikan secara kritis. Ia mengharapkan agar di Sinau Bareng tiap pelaku harus menggunakan akalnya untuk berpikir. Sebuah prasyarat yang tentu saja elementer.
Lebih lanjut, Cak Nun menyampaikan contoh bahwa terdapat titik pembeda antara orang bodoh dan pintar. Kalau orang bodoh itu, menurutnya, orang yang tak mau berpikir. “Kalau belum tahu sesuatu maka jangan lantas tak menggunakan akal pikirannya. Maka kita memiliki kewajiban untuk tetap iqra (membaca),” ujarnya. Membaca di sini bisa berupa membaca teks maupun konteks (kehidupan). Tergantung kecenderungan mana yang dipilih.
Masalah di kehidupan sangat kompleks. Cak Nun menganalisis kalau terdapat empat karakteristik orang. Pertama, orang yang bersedia belajar. Kedua, orang yang tak mau belajar. Ketiga, orang yang tak mau tahu. Keempat, orang yang bersedia tahu. Semua kategori ini disebabkan oleh kecenderungan individu yang sedemikian plural.

Dengan analogi yang membumi, Cak Nun memberi contoh orang bodoh dan pintar. Ia memberi ilustrasi seseorang dalam membuat sambal. “Ketika diminta membuat sambal, maka ia mencari bahan-bahan yang diperlukan, dan langsung membuatnya. Seseorang semacam itu menggunakan akal pikirannya sehingga kreatif. Orang ini adalah orang pintar. Sedangkan orang bodoh, ketika diminta membeli, ia langsung membeo semata. Diperintah membeli lombok ya beli, diminta membeli garam ya beli. Namun, ia tak memformulasikannya menjadi sambal. Ini orang bodoh. Sebab tak ada dialektika,” tandasnya.
Contoh yang dituturkan Cak Nun menegaskan betapa orang bodoh acap kali hanya berpikir satu langkah. Sementara orang pintar adalah selalu memahami apa yang harus dilakukan. Ia bisa memikirkan dan melakukan langkah panjang ke depan. “Orang pintar itu orang yang mempunyai orientasi panjang,” katanya.
Sabar Perlu Ilmu
“Kenapa syahadat disebut syahadat, tetapi bukan disebut amanat?” tanya Cak Nun kepada Kiai Muzammil. Salah satu Marja Maiyah tersebut sontak gayung bersambut. Menurutnya, terdapat perbedaan makna antara bersaksi dan percaya. Cak Nun pun sigap merespons, “Ketika engkau melihat kebesaran Allah, melalui daun, pohon, dan lain sebagainya, maka di situlah engkau menyaksikan kebesaran-Nya. Demikian pula saat sakit maupun senang. Itulah makna Tiada Tuhan Selain Allah. Itulah persaksian.”
Sabar ketika menghadapai sakit menjadi contoh apik yang dikemukakan Cak Nun. Menurutnya, terdapat gejala dalam hidup tatkala dipercaya Allah. Salah satunya dianugerahi sakit. “Di situ kemudian sabar memiliki peran penting. Apa hikmah di belakang sakit itu. Makna apa yang bisa dipelajari,” tanya Cak Nun.
Cak Nun mengutarakan, “Apakah bersyukur perlu pengetahuan? Perlu Ilmu? Itu perlu! Sebab itu kenapa Maiyahan di mana-mana tajuk utamanya selalu Sinau Bareng. Hal tersebut ditujukan agar kita makin bersyukur.”

Tatkala sabar memerlukan ilmu, maka menurut Kiai Muzammil, sebagai hamba hendaknya manusia lebih peka terhadap kata sabar. “Baginya, mengeluh bukan lawan kata syukur. Efek orang yang tak bersyukur itu mengeluh. Lawan kata syukur itu kufur. Jadi, itu persoalan sebab-akibat. Syukur itu ada yang dengan ucapan. Ada yang dengan perbuatan. Ada yang syukur sewaktu-waktu. Itu yang hatinya bersih. Itu orang yang berbahagia hidupnya. Syukur itu sepanjang hidup. Ia merupakan jalan hidup,” paparnya.
Cak Nun merespons Kiai Muzammil kalau definisi syukur menurut Kiai Muzammil antara lain bukan terletak pada berkurang atau bertambahnya harta benda. Namun, lebih cenderung pada kemampuan si pelaku atau manusia bahwa apa pun yang terjadi itu yang terbaik. Sehingga ia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru untuk membuat dirinya gembira.
Di sela-sela dialog atas konsep syukur yang diuraikan tuntas oleh Cak Nun dan Kiai Muzammil, Habib Anis menceritakan sebuah kisah. Syahdan, di Pati, ada Kiai bernama Kiai Alhamdulillah. “Kiai tersebut kalau tersandung, sakit, dan lain sebagainya selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi, jalan hidupnya itu selalu berterima kasih. Dan itu diucapkan. Bukan untuk apa-apa, melainkan dijadikan sebagai cermin diri. Untuk mengingatkan diri. Karena manusia selalu lupa,” tuturnya.
Mendengar cerita Habib Anis, Cak Nun memungkasi. “Orang kalau bersyukur maka akan membuat tiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang baik dan bermakna.”