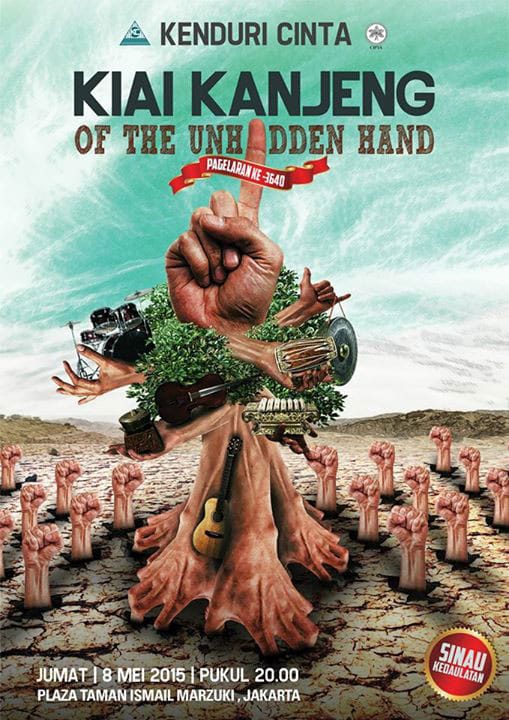Yang Qath’i Hanya Allah, Selainnya Cuma Pendapat Kok

Kita mencintai tanah air, udara dan budaya tempat kita lahir dan bernaung ini. Tapi negara, dia hanya inisiatif manusia. Dia terbuka pada proses. Bisa saja kalau kita nilai sudah tidak update, sudah tidak relevan, lantas kita carikan formula yang lebih tepat guna dan cocok pas panggonan zamannya kan?
Mbah Nun sendiri, meneguhkan kecintaan kita terhadap tanah air dan juga berulang kali melepaskan kepenatan dengan berpesan agar kita santai saja sama negara, bahwa dia bukan hal yang abadi. Bahkan belakangan ini mungkin kita makin perlu berpikir konsep pasca-negara. Maiyah adalah yang sepengetahuan saya paling siap menghadapi peradaban pasca-negara.
Ada masanya ketika Rasulullah Saw di Madinah sangat merindukan Bakka (Mekkah al-Mukarromah) tanah kelahiran beliau sang manusia teragung. Yang beliau tanyakan pada para kafilah mengenai Mekkah adalah soal sungai-sungainya, tanahnya, tanaman, hewan-hewan ternaknya. Intinya, hal-hal yang esensial. Beliau rindu pada tanah air, bukan administrasi negaranya.
Bahwa segalanya adalah dhonni, membawa saya pribadi pada kesadaran: jangan-jangan sikap pikiran saya yang tidak nasionalis itu juga hanyalah dhonni, atau sekadar persangkaan saya terhadap diri saya sendiri. Sebab, mengapa air mata saya selalu menitik kalau melantunkan lagu “Syukur”? Wah gawat, jangan-jangan saya lebih nasionalis daripada jargon “NKRI Harga Mati” yang saya sebelin itu. Entah, ini juga masih dhonni dan akan lanjut pada dhonni lainnya. Yang qath’i hanya Allah.

Sempat juga di awal acara memang Bapak Kepala Dusun Tlogo menyampaiakan persoalan-persoalan di desa. Kenakalan remaja, makin semaraknya bisnis pariwisata, serta bahkan pada perpolitikan desa fitnah bertebaran.
Mbah Nun menyampaikan, bahwa segala persoalan ini belum tentu akan ada solusi praktisnya pada malam ini. Namun yang lebih dulu mesti ditemukan adalah, ihwal “sebab-akibat” dari persoalan. Pola pikir yang sehat dibangun dulu, agar kita bisa menemukan pertanyaan yang tepat.
“Sekarang ini terlalu banyak orang yang mau menyelesaikan masalah, tapi ndak tahu masalahnya apa”, ujar Mbah Nun.
Kita tahu, segala persoalan yang kita alami belakangan ini memang adalah hasil dari ketidakcocokan tanam yang telah ditimbun bertahun-tahun, berdekade bahkan berabad-abad. Penyelesaian singkat tidak mungkin, selain hanya akan menambah persoalan. Kita benahi pola cocok tanamnya. Kita tandur dan kita berdoa agar pada timing yang tepat panen itu datang bersama generasi-generasi baru dengan penggalian yang otentik. Bukan solusi berdasar kesadaran “resep” belaka.
Khusus soal fitnah atau hoax, Mbah Nun menambahkan bahwa kita sekarang berada pada era kepungan fitnah, hoax dan prasangka. Ummat Islam sendiri menjadi sasaran persangkaan-persangkaan. Dan gawatnya, banyak persangkaan itu yang mereka adopsi pada kesadaran diri sendiri.
Dan tidak ada niatan dari pemangku kebijakan — tanpa kebijaksanaan — di NKRI untuk menangkal hoax. Karena bagi mereka, yang hoax adalah apa-apa yang merugikan citra diri mereka sendiri. Kalau menguntungkan, tidak disebut hoax. Slogan melawan hoax jadi bisa sama hoaxnya bila yang menggelontorkan pihak penguasa. Hoax bagi para pengusik kekuasaan? Oh itu namanya berita bagus, begitukah?
Saking mendominasinya prasangka di antara kita, Mbah Nun menyampaikan, sekarang ini kalau di acara-acara tertentu, seorang pejabat bicara di depan publik bahkan merasa perlu untuk uluk salam dengan berbagai tradisi agama. Supaya disangka pro-keberagaman, mungkin. Padahal sikap semacam itu justru mengandung kesadaran saling tidak percaya. Semacam kecurigaan diam-diam bahwa kalau orang tetap menjadi dirinya, tetap teguh dalam tradisi dan bahasa agamanya, orang lain akan terancam keamanannya. Ini saya pribadi menyebutnya “toleransi lamis”. Dirunut dalam sejarah, ini ada pada pluralisme ala penjajahan Romawi. Yakni toleran asal sesuai gaya hidup yang diizinkan penguasa. Nampak indah tapi saling mengincar-membinasakan.
Padahal, ucapkan saja salam sebagaimana agama yang dianut dan bersikaplah mengamankan dan menyelamatkan.