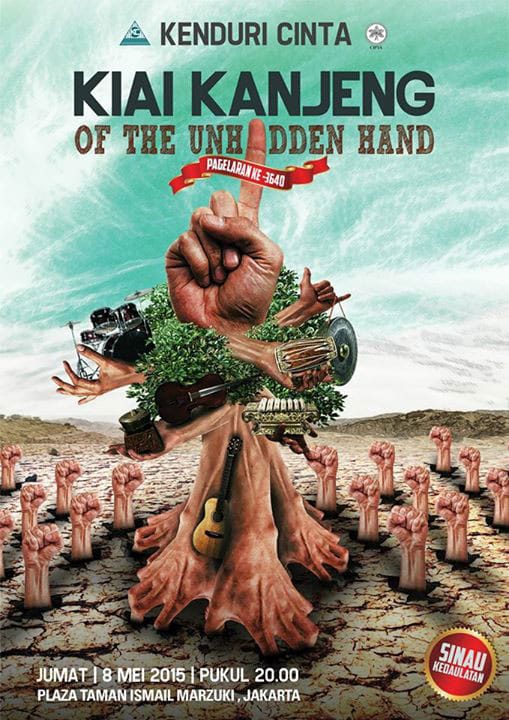Secuil dari Sepotong Dunia Emha

Sebuah panggung di tengah kampung — sebagaimana rutin digelar sesudah dan selanjutnya, lampu menyala terang-benderang, permadani dihamparkan, alat musik serta pengeras suara telah rapi tertata. Di hadapannya, halaman luas membentang. Di sekitarnya, berdiri rumah-rumah warga yang rapat dan hangat.
Tempat itu seperti magnet yang menarik minat orang-orang dari segala penjuru, dari beragam latar belakang, baik lelaki maupun merempuan, berbondong-bondong datang. Sebagian besar dari mereka masih berusia muda dengan energi yang kuat bergelora. Ada ciri khas yang mendominasi, para lelaki mengenakan peci berwarna merah putih di kepala. Semakin malam semakin banyak orang berdatangan. Mereka menamakan diri Jamaah Maiyah.
Ya, latar yang saya ceritakan ini adalah suasana Mocopat Syafaat yang digelar setiap tanggal 17 malam di halaman TKIT Alhamdulillah, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Begitulah gambaran yang terekam mata ketika untuk pertama sekaligus terakhir kali saya menghadiri acara tersebut. Oleh karena itu, sungguh saya tidak berani mendaku sebagai bagian dari Jamaah Maiyah. Saya bukan bagian dari para pencari kesejatian ilmu itu.
Benar-benar kewanen jika kemudian saya menyiarkan bahwa telah menyusun buku tentang Emha Ainun Nadjib dan akan menerbitkannya. Gendon, Pèncèng, dan Beruk pasti kemekelen menertawakan saya. Apa yang bisa saya sampaikan mengenai magnet dengan daya tarik luar biasa besar yang telah membuat majelis mulia masyarakat Maiyah berlangsung bertahun-tahun?
Tentu saja apa yang saya ketahui mengenai sosok Cak Nun, dunia, dan karyanya hanya sepanjang kuku ireng di jemari tangan. Itulah sebabnya, buku yang mula-mula adalah penelitian tesis dengan judul “Emha Ainun Nadjib dalam Arena Sastra dan Arena Sosial” yang dikerjakan selama tahun 2013 hingga 2014 itu diubah judulnya menjadi Sepotong Dunia Emha.
Yang sepotong tentu saja pengetahuan saya tentang Cak Nun. Sehingga hanya sepotong kecil dunia, hanya secuil dunia Cak Nun yang dengan sok-sokan saya ulas menggunakan teori seorang ahli filsafat dan sosiologi Prancis bernama Pierre Bourdieu. Semoga saja pemahaman mengenai pendekatan itu benar dan baik. Jika pun tidak, semoga sedikit hal yang saya ketahui dan ketengahkan mengenai Cak Nun dapat memberi manfaat.
Sungguh, sebenarnya saya sangat tidak percaya diri untuk mengulas hal ini. Oleh karenanya sebelum menulis catatan mengenai buku Sepotong Dunia Emha, terlebih dahulu saya meminta pendapat kepada Asef Saeful Anwar yang telah merelakan waktu dan ilmunya untuk membaca naskah buku ini dan menyuntingnya.
Sebuah pertanyaan saya ajukan, dan Asef Saeful Anwar menyodorkan bayang-bayang jawabannya. Pertanyaan saya sederhana, “Kira-kira bagaimana tanggapan Cak Nun setelah membaca buku Sepotong Dunia Emha, buku tentang sosoknya?” Ia pun menjawab, “Barangkali Cak Nun akan berkata begini: Saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan semuanya mengalir. Saya hanya berusaha memanusiakan manusia, baik lewat dialog budaya, aktivitas sosial, maupun dalam tulisan, dalam sastra. Jadi, saya tidak menyangka kalau langkah saya sedemikian terstruktur seperti dalam buku ini.”
Bisa jadi demikian kiranya tanggapan Cak Nun setelah membaca dirinya dalam buku yang diterbitkan oleh Penerbit Octopus ini. Sekali lagi, itu hanyalah sebuah bayang-bayang perkiraan. Maka, bukan suatu hal yang berlebihan kiranya jika pada suatu hari nanti, pada peringatan ulang tahun Cak Nun ke-65 tanggal 27 Mei 2018 misalnya, digelar acara untuk membicarakan buku ini. Dan pada forum itu kita dengar bersama bagaimana tanggapan beliau.
Namun, sebelum menggapai imajinasi-imajinasi itu, ada baiknya saya paparkan latar belakang yang melandasi pikiran saya untuk mengulas Cak Nun, dunia, dan karyanya.
Sesungguhnya pemantik api yang mengobarkan gagasan ini amat sangat sederhana, yakni catatan mengenai Cak Nun tidak lebih banyak dari catatan yang ditulis oleh Cak Nun mengenai banyak hal. Sungguh tidak sebanding apa yang telah dilakukan oleh Cak Nun dengan apa yang telah dilakukan untuk Cak Nun.
Meskipun demikian, sebagaimana telah saya sampaikan di muka, buku kecil yang saya susun ini hanya menjelaskan sepotong dari semesta Emha Ainun Nadjib. Untuk menerang-jelaskan Cak Nun sama halnya membaca kembali lembar demi lembar tulisan-tulisan beliau dan tulisan-tulisan tentang beliau.
Membaca kembali lembar demi lembar tulisan-tulisan beliau dan tulisan-tulisan tentang beliau sama halnya membaca kembali beragam peristiwa sejarah yang tertindih, ditindih, luput, lepas, hilang, dimusnahkan dari narasi besar yang ada di Indonesia.
Melalui catatan kecil ini saya ingin menyampaikan bagian kecil isi buku kecil yang tidak sebanding dengan kebesaran nama Cak Nun beserta segala predikat yang tersemat di pundak beliau. Saya sadar betul siapa sosok yang namanya tengah saya ketik dengan ujung jemari tangan ini. Yang saya tulis hanya sesobek buku harian Indonesia dari buku tua yang sesungguhnya amat sangat tebal.
Emha Ainun Nadjib yang kemudian lebih karib disebut Cak Nun, rasa-rasanya sudah sering saya jumpai di masa kecil dahulu. Beliau sering nongol di televisi nasional kala itu. Nama dan wajah beliau kemudian juga saya temui di koran dan majalah langganan orang tua saya, serta di sejumlah buku sastra di perpustakaan sekolah. Seingat saya, beberapa waktu beliau memancarkan sinar yang teramat terang lantas menghilang dari pandangan seperti meteor di angkasa.
Kaya dudu karepe dhewe, seperti bukan kemauan sendiri, saya dipertemukan lagi dengan beliau melalui karya lawasnya Syair Lautan Jilbab di pusat buku murah Shopping saat belajar sastra di Universitas Ahmad Dahlan. Buku tersebut kemudian menjadi objek material skripsi saya. Tidak perlu saya sebutkan judulnya, jujur saya malu mau menuliskannya di sini.
Saya juga tidak tahu apa yang membuat saya kelak di kemudian hari ketika melanjutkan belajar sastra di Universitas Gadjah Mada berpikir untuk memakai objek material karya-karya Cak Nun dalam semua tugas-tugas yang diberikan, selain tugas Filologi dan Sastra Lisan. Hingga kemudian saya menemukan pendekatan yang cukup pas dan luas untuk membicarakan Cak Nun, dunia, dan karyanya–seperti yang sudah saya singgung, yakni sosiologi sastra Pierre Bourdieu. Pengampu mata kuliah ini Dr. Aprinus Salam.
Bukan suatu kebetulan, waktu itu kakak kelas saya yang kemudian mengeditori buku Sepotong Dunia Emha ini, Asef Saeful Anwar, tengah menyusun tesis menggunakan pendekatan sosiologi sastra Pierre Bourdieu mengenai Persada Studi Klub berjudul “Persada Studi Klub: Disposisi dan Pencapaiannya dalam Arena Sastra Nasional” yang kemudian diterbitkan menjadi Persada Studi Klub dalam Arena Sastra Indonesia.
Selain itu, satu teman lagi yang mengerjakan penelitian dengan pendekatan yang sama ialah I Made Astika dengan judul tesisnya “Pergulatan Umbu Landu Paranggi dalam Arena Sastra di Bali: Tinjauan Sosiologi Sastra Pierre Bourdieu”.
Sebagaimana telah diketahui bersama, Malioboro mungkin telah kehilangan Cak Nun, tetapi Cak Nun tidak pernah kehilangan Malioboro. Cak Nun tidak bisa dilepaskan dari Persada Studi Klub dan Umbu Landu Paranggi.
Melihat dua kakak kelas saya mengerjakan penelitian yang saling berkait itu, mengapa tidak saya melengkapinya dengan menghadirkan Cak Nun. Semakin yakin saya gunakan pendekatan sosiologi sastra Pierre Bourdieu untuk menelisik lebih dalam mengenai Cak Nun. Berbekal koleksi buku-buku Cak Nun dan buku-buku tentang beliau, saya dedah struktur arena sastra dan arena sosial Cak Nun.
Cak Nun merupakan sosok multitalenta dan multidimensi yang tidak dapat dilepaskan dari dua perannya sebagai penulis dan aktivis sosial. Citra karismatik Cak Nun di arena sastra dan arena sosial bersinar terang, sebagai lintang panjer wengi sekaligus lintang panjer rina. Meskipun, berdasar pendekatan sosiologi sastra Pierre Bourdieu, berkenaan dengan arena produksi kultural, arena seni, dan arena sastra beliau harus dilepaskan dari dilema citra karismatik. Padahal citra karismatik Cak Nun ada dalam sosoknya dan lekat dengan kehidupan pribadinya. Beliau seperti dilimpahi karomah oleh Tuhan. Menjumpai hal ini, saya merasa kesulitan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Cak Nun.
Emha Ainun Nadjib berbeda. Cak Nun melakukan “perlawanan budaya” yang disebut beliau dengan melakukan dekonstruksi pemahaman nilai, pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi masalah masyarakat.
Oleh karenanya, meskipun tidak terjadi tubrukan langsung antara pendekatan yang saya gunakan dengan hasil temuan dari sosok Cak Nun, ada garis lurus yang menghubungkan antara dasar dan puncak temuan-temuan itu, yakni sastra. Sebagai sebuah kajian sastra mendapatkan kesimpulan bahwa Cak Nun tidak pernah akan bisa dilepaskan dari sastra (baik dunia maupun pola pikir) tentu saja menjadi sebuah hasil akhir atau kesimpulan yang sesuai dengan harapan.
Sepotong Dunia Emha, sepotong Indonesia dari sepotong tempat dan sepotong waktu.