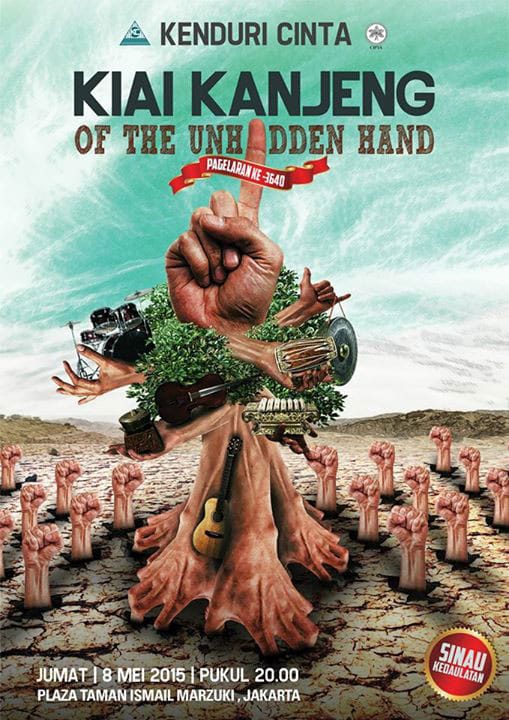Menggali (dan) “Mencari Buah Simalakama”
Sejak awal layar dibuka perlahan dengan denting-denting meditatif dari beberapa orang yang dilibatkan dari kelompok musik KiaiKanjeng, kemudian Dalang (Landung Simatupang) masuk beserta asisten melakukan upacara ritual pembuka. Sejak itulah garis batas antara penampil dan penonton telah disibak sedikit demi sedikit. Aroma kembang yang dihempas-hempaskan oleh Dalang menyeruak ke penonton. Itu pun kemudian masih ditambah pula, ketika baru beberapa menit berada di panggung terjadi chaos. Para pemain berebut masuk panggung. Dalang misuh-misuh sambil mengusir untuk kemudian, setelah situasi kembali tenang, menyampaikan permohonan maaf kepada penonton lalu membuka pagelaran “Inilah kisah Astinapura setelah Baratayudha!”
Terjadinya interaksi dari panggung ke penonton berarti ‘dinding pembatas’ antara penampil dan penonton telah diterabas. Maka setiap yang menyaksikan pagelaran adalah juga pemain, adalah penafsir atas apa-apa yang terjadi di panggung. Interaksi yang bila dirunut terjadi melalui beberapa media; pertama cahaya dan bunyi, kedua melalui aroma, kemudian ketiga melalui gerak dan kata-kata.

Kesadaran penonton dibawa untuk keluar-masuk panggung, dan mengaitkan rangkaian-rangkaian adegan di panggung dengan kondisi real dalam kehidupan masing-masing. Sehingga dalam menuliskan apresiasi atau ulasan mengenai pagelaran “Mencari Buah Simalakama” yang dipentaskan di gedung Concert Hall TBY pada 26 April 2017 ini juga tidak bisa hanya berdasar teori-teori pemanggungan, melainkan juga perlu didapati titik temu antara kejadian adegan dengan fakta-fakta dan gejala di luar panggung. Berdasarkan bekal pengetahuan dan bekal pengalaman pribadi masing-masing kita.
Pakem-pakem estetika panggung maupun dasar-dasar permainan drama sepertinya memang bukan hal utama yang ingin ditampilkan pada pentas ini. Jauh lebih penting adalah ‘buah’ yang akan didapat oleh masing-masing pemain dan penonton.
Para sesepuh dunia teater yang tergabung dalam Perdikan Teater sudah tidak perlu membuktikan diri dengan aturan-aturan baku dalam seni pertunjukan. Ini mengingatkan kita ketika dulu Metallica menerbitkan album St Anger. Lagu-lagu dalam album tersebut sangat minim melody gitar. Kirk Hammett sang gitaris berkomentar ketika ditanya mengenai hal tersebut: “Buat apa saya menonjolkan permainan gitar saya? Semua orang kan sudah tau saya bisa main gitar”. Mungkin begitu juga dalam pentas Mencari Buah Simalakama ini, toh semua orang sudah tahu kualitas Joko Kamto, Sitoresmi Prabuningrat, Landung Simatupang, Jujuk Prabowo, Bambang Susiawan, dan banyak lagi sesepuh lain dalam pentas ini, belum lagi kualitas pencahayaan Pak Wardono dan penyutradaraan Drs Suharyoso SK dengan disupervisi oleh Mbah Nun pula.
Namun juga jangan salah mengira. Jangan dipikir dengan begitu maka hal-hal mendasar dalam estetika panggung dan keaktoran tidak tergarap. Cahaya dan bunyi bekerja dengan kompak membangun nuansa, membawa penonton ikut masuk ke dalam karut-marut permasalahan di negeri Indo… maaf, Astinapura. Lalu membawa kita melayang ke Kahyangan. Bersama Anoman yang lincah namun telah renta, melaksanakan tugas mencari buah simalakama, tergoda oleh kata-kata bijak dan manis dari Bethari Uma yang anggun, kemudian berhadapan dengan kharisma Batara Guru yang mendapati hampir terjadinya perselingkuhan antara Anoman dan Dewi Uma.
Selain percaya diri dengan kualitasnya, naskah pentas ini juga merupakan naskah yang percaya pada penonton. Penulis naskah, tiga nama yang juga adalah jaminan mutu dalam penulisan naskah; Simon HT, Fajar Suharno, dan Landung Simatupang, sangat percaya bahwa setiap penonton memiliki bekal pengetahuan mengenai pakem-pakem pewayangan sehingga tidak merasa perlu menjelaskan beberapa latar belakang kejadian dan dialog.
Dalam satu kesempatan di Mocopat Syafaat beberapa bulan lalu, disebut oleh penulis naskah bahwa dialog-dialog dalam naskah ini digali dari kekayaan dan kedalaman Maiyah.
Ini membuat dialog-dialognya tidak berkesan menggurui, lagipula rasanya dengan dipentaskan di kota Yogyakarta tidak bisa disebut ekspektasi yang terlalu tinggi bila berharap semua orang punya bekal pengetahuan pewayangan sebelumnya.

Umpamanya ketika terjadi adegan Batara Guru yang diperankan oleh Pak Joko Kamto, merusak wajah Dewi Uma diperankan Sitoresmi Prabuningrat. Sambil menjerit dan tersedu-sedu Dewi Uma berkata, “Apakah pukulun masih mencintai Anjani? Ibu dari kera ini?” (sambil menunjuk Anoman), ini tentu mengingatkan kita pada satu kisah jauh sebelum Baratayudha, juga jauh sebelum era Rama-Shinta, yakni sejarah kelahiran Anoman sendiri, juga sejarah Anjani ibundanya.
Kisah ini perlu dirunut sejak era Rsi Gotama, jauh sebelum terjadinya geger Rama vs Rahwana. Rsi Gotama yang seorang pertapa di petilasan Erriya/Grastina memiliki istri Dewi Indradi dengan tiga orang anak yakni Anjani, Guwarsa, dan Guwarsi. Dewi Indradi yang sering ditinggal bertapa oleh suaminya memiliki affair dengan Batara Surya, dia pun diberikan Cupumanik Astagina yang dari dalamnya seseorang bisa menyaksikan segala peristiwa di alam semesta.
Dewi Indradi lalu menunjukkan cupu tersebut kepada Anjani yang kemudian dengan riang meminjam dan bermain-main dengan cupu itu. Ibunya berpesan agar keberadaan cupu tersebut dirahasiakan dari siapapun. Sayangnya dua saudara Anjani mengetahui keberadaan cupu tersebut dan ingin meminjam dari Anjani. Karena tidak diperbolehkan, Guwarsa dan Guwarsi mengadu pada sang ayah. Rsi Gotama yang segera tahu bahwa cupu tersebut adalah milik Batara Surya bertanya mengapa Dewi Indradi bisa memiliki cupu tersebut. Dewi Indradi merasa bersalah hanya terdiam, tanpa sengaja Rsi Gotama berucap, “Diam saja seperti tugu batu!”. Kata itu pun menjadi kutuk sehingga Dewi Indradi menjadi tugu batu yang oleh Rsi Gotama dilempar ke arah Alengka.
Sedangkan Cupumanik Astagina dilempar ke langit, Guwarsa, Guwarsi, dan Anjani mengejar cupu tersebut, cupu itu jatuh dan pecah menjadi dua. Tutupnya menjadi Telaga Sumala dan wadahnya menjadi Telaga Nirmala. Guwarsa dan Guwarsi langsung nyemplung ke dalam Telaga Sumala dan berubah menjadi kera. Anjani yang tiba belakangan meminum air dari telaga dan wajahnya berubah jadi kera namun tubuhnya tetap molek. Rsi Gotama memberi petunjuk pada anak-anaknya melalui suara gaib sebelum dirinya kemudian kembali larut dalam pertapaan, bahwa anak-anaknya mesti melaksanakan laku tapa masing-masing untuk menebus kesalahan mereka. Anjani diperintah melakukan tapa nyantuka (bersikap seperti katak), yaitu bertapa dalam keadaan telanjang sambil berendam dan hanya memakan apapun yang lewat di depannya.
Bertahun-tahun berlalu demikian, ketika satu kali Batara Guru menunggangi Lembu Andini sedang berkeliling. Dari langit dia menyaksikan tubuh molek wanita sedang berendam. Berahi sang dewa terbangkitkan dan jatuhlah air maninya, menempel pada daun asam muda: sinom. Daun yang tertempel kama sang dewa itu mengapung di telaga lalu dimakan oleh Anjani dan membuatnya hamil.
Bayi berwujud kera putih itulah, karena melalui media daun sinom maka kelak diberi nama Anoman. Anjani yang bingung dengan keadaan dirinya diberi petunjuk melalui Batara Narada bahwa putranya adalah putra Batara Guru sendiri, Anjani dipulihkan kecantikannya dan diangkat menjadi bidadari di kahyangan sedang Anoman diasuh oleh para dewa. Dia Anoman ya juga bernama Anjaniputra, dia jualah Bayusiwi (karena jadi kesayangan Batara Bayu), Guruputra, ya juga Handayapati, juga bergelar Yudawisma, Maruti, Palwagaseta, Prabancana, Ramandayapati, Senggana, Suwiyuswa (berusia panjang) dan juga bergelar Rsi Mayangkara di usia tuanya.
Dalam naskah India tidak ditemukan akhir hidup Anoman, dalam naskah Nusantara ia menemui ajalnya seratus tahun setelah era kekuasaan Parikesit berlalu, yakni pada era Prabu Jayabaya di Kediri.
Angkat Topi untuk Pak Jojo Kamto
Maafkan bila kisah latar belakang kelahiran Anoman sedikit kepanjangan, tapi karena inilah kita bisa mengetahui latar belakang kisah juga akan menjadi rasional mengapa Kiai Semar justru meminta Anoman untuk naik ke kahyangan mencari buah simalakama itu. Sebab Anoman dengan statusnya sebagai Anjaniputra maupun Guruputra memang memiliki privilege untuk naik ke kahyangan tanpa menimbulkan kegegeran. Akan berbeda bila misalnya, Semar sendiri yang naik ke kahyangan. Dalam kisah-kisah pewayangan kejadian seperti itu akan membuat marah Batara Guru, sehingga yang terjadi adalah revolusi dan konfrontasi.

Artinya, Anoman dalam lakon “Mencari Buah Simalakama” ini mengemban misi diplomasi. Dia tidak boleh pamer kekuatan dan kesaktian namun juga tidak boleh menggunakan jalur formal dengan meminta langsung buah itu. “Esensi dari tugas mencari buah simalakama, adalah pada kata ‘mencari’, bukan direbut atau diminta,” begitu kira-kira kata Kiai Semar dalam sebuah dialog ketika meminta Anoman mengemban misi ini.
Namun Kiai Semar juga bukan tanpa kekeliruan dalam menurunkan tugas ini pada Anoman. Pertama, karena sesungguhnya Semar sendirilah yang oleh Raden Arjuna diperintah untuk mencari buah tersebut. Karena menurut pada petunjuk yang didapatkan oleh Arjuna, hanya dengan memakan buah simalakama itu maka akan terselesaikan segala karut-marut permasalahan di negeri Astinapura. Kedua, Semar juga dengan sengaja meminta Anoman untuk meninggalkan tugas utamanya yakni menjaga Dasayitmo agar tidak terbangun dan tetap berada di Kendalisodo. Semar terlalu mengentengkan tugas Anoman yang utama itu, namun alasannya juga dapat kita pahami. Lakon ini memang memberi kita ‘simalakama’ sendiri. Seolah kita ingin diperingatkan, dalam kondisi bangsa dan dunia ‘kapal oleng’ seperti ini, sikap-sikap baik selalu memiliki konsekuensi yang belum tentu baik juga nantinya. Kita diajak untuk berwaspada sepresisi mungkin.
“Anoman! Bahwa sesungguhnya segala permasalahan yang terjadi di negri Indo… Aaastinapura…” Sepenggalan dialog itu dari Batara Guru menunjukkan kualitas keaktoran Pak Joko Kamto. Adalah tantangan yang sungguh berat bagi seorang aktor untuk menyampaikan sesuatu yang bila dirangkum adalah “kesalahan yang dilakukan dengan benar” dalam teater memang terkadang ada paradoks semacam ini. Simalakama!
Penggalan dialog tersebut, sepenggal dari dialog yang sungguh panjang sebenarnya, menuntut sang aktor tidak saja menyampaikan bahwa titik fokus pembahasan ada pada kerajaan Astinapura namun juga related dengan kondisi sosial sebuah negeri yang namanya hampir terucap. Dialog ini akan menjadi drop, atau bahkan gagal bila slip tongue pernah terjadi pada dialog sebelumnya atau pada dialog-dialog sesudahnya. Artinya keberadaan penggalan kalimat itu menuntut sang aktor untuk tampil sesempurna mungkin. Pun tetap memperhatikan intonasi, artikulasi, dan gestur.
Bila sempat terjadi satu saja kesalahan sebelumnya atau sesudahnya, maka dengan segera penonton akan menyimpulkan bahwa yang tadi itu adalah murni kesalahan aktor. Tapi dengan tidak terulangnya kesalahan, dengan tetap terjaganya semua dialog dengan timing dan momentum yang presisi, kejelasan suara dan gerak tubuh yang pas, maka barulah pesan tersebut bisa sampai ke penonton, dan memang seperti itulah yang dilakukan oleh Pak Joko Kamto. Angkat topi!
Dasayitmo; Sepuluh Arwah Kejahatan
Kita yang terbiasa dengan bahasan-bahasan di majelis Maiyah sudah tidak asing, bahwa apapun isitilah, ideologi, pemahaman, yang nampaknya membawa kebaikan masih perlu diteliti, dikaji, dan digali kembali; apakah itu istilah-istilah berlabel agama dari mulut agamawan, isme-isme yang tampak suci seperti pluralisme, toleransi, nasionalisme dan lain sebagainya mesti kita ukur betul detail-detailnya.

Sedangkan dalam salah satu dialognya berkata Kiai Semar, “Parikesit, peradaban baru yang diisyaratkan para dewa, tidak akan terwujud melalui jalur formal…” tentu masuk akal, mengingat semua formalitas yang ada pada zaman ini di Astinapura telah dikuasai oleh aspek-aspek Dasayitmo. Maka pentas ini juga adalah sesungguhnya sebagai nota ketidaksetujuan terhadap apapun yang berlangsung. Pernyataan tegas bahwa generasi ini sudah cukup untuk dibuai dengan penjajahan kemudian dilenakan dengan persepsi akan kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang lahir dari jalur-jalur formal, Negara, dan turunannya. Saatnya generasi Parikesit mengambil jurus, merumuskan kembali persoalan dan solusi dengan terlebih dahulu mensucikan diri.
Dalam situasi ‘kapal oleng’ seperti ini, besar kemungkinan ‘Kendalisodo’ (kendali dan petunjuk) kita belum mumpuni karena keburu ditinggal oleh kesucian Anoman dalam batin kita. Bayangkan, Dasamuka (sepuluh wajah kejahatan) saja sudah cukup membingungkan. Dalam lakon ini, yang diambil justru adalah Dasayitmo yang seperti kita pahami bersama merupakan tubuh halus Dasamuka alias Rahwana.
Sebab, Dasamuka alias Rahwana tubuh kasarnya telah ditimbun oleh Anoman dalam perang di Ngalengkadirja, namun Rahwana adalah pemegang ajian pancasona. Dia tidak bisa mati. Sebagai tubuh kasar dia terpendam dalam dataran alam bawah sadar peradaban dan secara tubuh halus dia mengintai terus, menanti kebangkitannya, di Kendalisodo. Dasayitmo tetap memiliki kesadaran Dasamuka, dengan pemahaman yang lebih lembut dan detail. Dia bahkan mengetahui rahasia nama Semar “Hay Semar, Samir, Samar… Sumur…”
Dalam bahasa panggung di pentas ini, dia (Dasayitmo) berada pada sisi panggung sebelah kanan penonton, tersembunyi di balik semak. Tak tampak namun terasa sebagai gejala, hasrat, dan dorongan. Dia merasuk pada setiap pesan-pesan kebaikan. Dasayitmo, masih jua Dasamuka yang menunggu setiap kelahiran (reinkarnasi) Widowati cinta pertamanya, baik sebagai Citrawati, istri Arjunasasrabahu, sebagai Dewi Sukasalya istri Begawan Rawatmaja, sebagai Sinta istri Rama maupun sebagai Wara Subadara (Sembodro) istri Arjuna.
Cinta Dasayitmo tetap kekeuh bahwa Widowati tetaplah Widowati. Dalam pementasan ini, merunut pada setting waktu kita bisa mafhum bahwa yang hadir adalah Wara Subadra, diperankan oleh Nunung Rita. Arjuna dan Kresna memanggilnya sebagai Subadra, Dasayitmo memanggilnya sebagai Widowati.
Pelajaran bagi kita, walau Dasayitmo lebih mengenal Subadra namun dia sendiri sesungguhnya masih tertipu bentuk. Widowati, biarpun adalah kelahiran pertama dari urutan empat titisan Dewi Sri namun tetap saja belumlah esensi. Bahwa walau berapa kalipun lahir, dari Widowati sampai Wara Subadra, semua itu hanya titisan bentuk dari Dewi Sri. Dewi kesuburan, padi. Jawa sendiri dalam satu naskah kuno berarti tanah tempat tumbuhnya padi. Betapa mengerikan apabila Dasayitmo sampai mengenal esensi Dewi Sri. Betapa banyak titisan Dewi Sri yang akan diincarnya di negeri ini?
Suta Kurawa
Satu hal yang juga menarik dalam lakon “Mencari Buah Simalakama” ini adalah munculnya gerombolan Suta Kurawa. Mereka bocah-bocah, anak-anak zaman yang kehilangan panutan dan arah.
Mereka yang benar-benar harus mencari apa itu buah Simalakama, karena mereka tidak bisa menghayati kebingungan “dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati” mereka tidak mengerti kebingungan macam apa itu, karena selama ini mereka memang telah yatim kebudayaan dan piatu peradaban.

Mereka muncul saat mendekati akhir adegan, bergerombol, gerakan serampangan. Dengan kostum yang jelas dibuat sengaja tidak memiliki persambungan dengan nuansa kostum dan make up tokoh lain. Pesannya sangat gamblang: generasi ini terputus dari jalur sejarah mereka sendiri. Karena mereka yang tidak tahu dari mana mereka berasal, juga tidak tahu kemana mereka menuju.
Mereka marah dan membabi buta, penuh amuk. Melawan dan menyalahkan segala. Tak peduli. Beringas. Namun justru karena itu juga, mudah dikalahkan oleh pasukan Dasayitmo.
“KAMI ADALAH GENERASI YANG TUMBUH KEMBANG DEWASA TANPA IDOLA KEPAHLAWANAN! GENERASI SEBELUM KAMI ADALAH GENERASI YANG DITOLAK OLEH SEJARAH!”
Generasi yang tumbuh dan berkembang tanpa uswatun hasanah, tanpa sosok keksatriaan “tanpa idola kepahlawanan”.
Berapa banyak keluaraga yang tidak berfungsi sebagai keluarga. Bapak tidak menjadi sosok maskulin yang mengajarkan ketajaman rasio dan tanggung jawab. Sedangkan ibu tidak lagi penuh kasih sayang yang feminin karena habis terus-menerus dieksploitasi kecantikan dan kemolekannya. Kita boleh mengganti kata “Bapak” dengan “Pemerintah” dan kata “Ibu” dengan “Tanah air ”, karena memang hal ini terjadi dari tingkat paling domestik-keluarga, kondisi sosial kota-desa, struktur birokrasi politik-pemerintahan negara hingga pada tatanan global dunia.
‘Bapak’ dan ‘Ibu’ yang tidak menikah secara nilai, tidak saling berta’aruf kepentingannya namun melampiaskan berahi. Sehingga yang terjadi adalah perselingkuhan kepentingan.
“Selingkuh tubuh, selingkuh pikiran, selingkuh jabatan. Selingkuh, satu kata yang dinajiskan tapi juga diburu untuk dikerjakan” (dialog Anoman)
Berahi kekuasaan yang tidak terkendali.
“Melampiaskan hasrat atau melestarikan kehidupan? Yang mana?” (dialog Batara Guru)
Bukan kemesraan melainkan pemerkosaan-pemerkosaan terhadap sang ibu tanah. Melahirkan generasi-generasi yang marah, yang terbiasa menyaksikan kekerasan, kedhaliman, ketidakpedulian. Di mana mereka mencari sosok uswah kepahlawanan?
Suta Kurawa digambarkan sebagai anak-anak Kurawa yang menjadi korban perang Pandawa vs Kurawa. Bisakah kita artikan juga sebagai; hasil ketidak-harmonisan keluarga, ketidak-cocokan nilai antara pemerintah dan tanah air.
Mereka terbiasa melihat ayah pemerintahan politik mereka saling tawur sehingga mereka mencontohnya dengan tawur-klitih antar sesama mereka. Mereka terbiasa menyaksikan tangan-tangan kekuasaan memberangus yang tidak sejalan sehingga mereka mengaplikasikan relasi kuasa kecil-kecilan dalam tingkat kampus dan sekolah-sekolah mereka dengan praktik-praktik bully dan perploncoan. Agar mereka juga bisa mengecap sedikit kekuasaan kecil-kecilan minimal sebagai senior, yang juga mencontoh tradisi lapuk yang telah diturunkan oleh generasi sebelum mereka dan jelas tidak pernah menghasilkan apa-apa.
Mereka terbiasa menyaksikan ketidak-jelasan nilai di kahyangan pemerintahan sehingga mereka juga mencontoh dengan tidak jelasnya kelelakian dan keperempuanan. Mereka lihat orang tua mereka mabuk kekuasaan dan mereka mencontohnya dengan mencari bahan-bahan kimia untuk teler dan mabuk; minuman keras serta obat-obatan.
Di sana mereka lihat dengan gamblang, dengan mata telanjang, betapa nafsu keserakahan dan kekuasaan begitu tidak terkendali. Sementara sang ibu tidak berdaya disobek-sobek kemurniannya sehingga juga mereka terbiasa melampiaskan tanpa rem akhlak dan tidak lagi punya upaya untuk mempertahankan keperawanan dan keperjakaan sehingga pergaulan bebas merajalela di kalangan generasi ini.
Dan tak ada yang peduli.

Lost generation, Suta Kurawa menjadi generasi yang tak ambil peduli. Mereka serang asal serang. Serbu asal serbu. Namun kuda-kuda mereka tidak kokoh. Mereka ambil apa saja yang nampak baik tanpa memiliki filter ketajaman rasio, kekokohan logika, kesetiaan pada ilmu dan kepekaan rasa.
Ada konsep khilafah mereka ambil, ada nasionalisme mereka telan mentah-mentah, ada pluralisme mereka puja-puja, ada konsep-konsep spiritual mereka sembah-sembah, ada post-modernisme, ada wacana pembebasan, ada feminisme, ada nihilisme, ada demokrasi, ada arus perdagangan bebas, ada marxisme, ada teori konspirasi, ada wacana purifikasi budaya, ada anrkisme, liberalisme, ada ini-itu apapun yang tampak baik yang nampak bisa mereka pegang mereka ambil. Tanpa pikir panjang. Tanpa tuma’ninah.
Tanpa mereka sadari bahwa Dasayitmo mampu merasuk pada apapun pesan-pesan yang nampak baik, dari dalam maupun dari luar, dari atas maupun dari bawah selama dia diambil dari sumber yang tidak ‘suci mensucikan’.
Simalakama Kondisi Kebangsaan
“Andai saja para ksatria Astinapura bisa membangun peradaban baru yang mengedepankan kesederhanaan kehidupan, persaudaraan kehidupan dan keperdulian kehidupan maka akan ada perimbangan kegiatan kehidupan. Termasuk kehidupan pasar antar lapis sosial maupun antarlintas negara. Buah Simalakama bukanlah material, tapi satu abstraksi dari satu kondisi yang harus dipilih. Makan akan kehilangan ayah, tidak makan akan kehilangan ibu. Ini mengajarkan betapa lekatnya antara kebijakan tindakan dan apapun itu namanya dengan yang namanya resiko atau konsekwensi. Negara Astinapura sedang gaduh, karena para punggawa dari lapis paling atas sampai lapis paling bawah tidak konsekwen” (Dialog Batara Guru)
Baiknya dialog tersebut dihafalkan dan dihayati betul-betul. Karena sungguh seperti itulah yang benar-benar terjadi di negri ini sekarang. Gaduh.
Ajuan solusi terhadap segala persoalan, justru mengandung minimal sedikit persentase persoalan baru, bagus kalau hanya sedikit sering terjadi justru menambahi persoalan. Tokoh-tokoh yang lahir dari sistem yang telah disepakati kebusukannya, bisa disanjung dan disembah. Sementara yang lain sibuk mencaci, pun tanpa dasar dan tanpa sadar.
Demokrasi menawarkan pada manusia apa yang ingin mereka pilih, tanpa bertanya apa yang tidak ingin mereka pilih. Itupun dengan menu pilihan yang sudah ditentukan dari sononya.
Mengkritik demokrasi dianggap berarti ingin membangkitkan tirani. Mungkin memang ada yang demikian, namun yang dilakukan di Maiyah demokrasi dikritik agar kita memiliki kesempatan untuk merumuskan sesuatu yang lebih layak dan cocok pada era-era selanjutnya.
Manusia dibuat gagal proses berpikirnya sehingga selalu gagal pula menemukan pola penjajahan di antara penjajah. Pengkhianat di antara pengkhianat yang dikhianati oleh pengkhianat lain. Para penjajah saling bertengkar, dan masyarakat dibuat harus mendukung salah satu seolah satu dari yang lain adalah yang paling suci. Padahal masing-masing menyimpan keterpelesetan pemahaman, kekeliruan nilai, dan menyimpan Dasayitmonya sendiri-sendiri.
“Sesungguhnya bangsa Astinapura tidak suka belajar sejarah. Sejarah hanya diberikan di sekolah dan materinya ya ampun… hanya hitam-putih saja”, begitu kata Bethari Uma kepada Anoman.
Lapis-lapis Penjajahan
Ada penjajah yang berniat murni melakukan penjajahan. Juga ada lapis penjajah yang tidak berniat melakukan penjajahan atau penjajah yang niatnya baik tapi tanpa sadar melakukan penjajahan juga. Saat ini semuanya ada, dan mereka saling menjajah satu sama lain juga.

Bukankah Daendels datang ke tanah Jawa demi mengemban tugas dari Napoleon untuk ‘menyelamatkan pulau Jawa’? Bukankah perlawanan terhadap Daendels salah satunya dikompori oleh mantan pejabat-pejabat VOC yang dendam juga? Apakah itu membuat Daendels bukan penjajah? Apakah tidak berniat menista pastilah tidak menistakan? Duhai, Betapa berlapis Dasayitmo itu.
Bukan hanya para tokoh yang mesti dipilih untuk dipuja atau dihujat. Pun juga masyarakat mesti terbagi pada pembakuan-pembakuan konsep yang jargonistik, yang simbol, kemudian berhala-berhala jargon itu diadu pula satu sama lain. Seolah khilafah harus bermusuhan dengan pluralisme, agama harus beradu dengan negara, politik tak berkaitan dengan Tuhan dan kebebasan adalah musuh dari batasan-batasan.
Satu hal mesti dianggap bagus terus apapun konteksnya dan hal lain harus dianggap jelek terus apapun konteksnya. Masyarakat semakin tidak mengerti seni dan cara “menggelar kloso”, tapi lebih senang membentangkan karpet merah untuk pemodal.
Wacana pembebasan menjadi alat penjajahan baru. Tata nilai terbolak-balik, cita rasa terhadap apapun juga telah terdegradasi. Setiap tokoh pada lakon ini digambarkan memiliki Simalakamanya masing-masing. Ya, seperti kehidupan bangsa ini.
Raden Arjuna yang menugasi Semar tanpa dibekali konsep apa-apa, Semar yang meneruskan titah pada Anoman yang dirasa lebih cocok namun sebenarnya melanggar birokrasi karena Anoman mesti meninggalkan tugasnya menjaga Dasayitmo. Raden Kresna yang hanya terdiam ketika situasi makin gawat di mana pilihannya adalah menyerahkan Wara Sembodro atau membiarkan Bagong mati di tangan Dasayitmo, sedangkan matinya satu Punakawan berarti matinya seluruh Punakawan lainnya. Dan sebuah negeri tanpa bimbingan Punakawan tinggallah menunggu kehancurannya.
Korsleting antara yang benar secara esensial maupun yang benar secara birokrasi terjadi, menimbulkan ketegangan antara Anoman dan Kresna. Beruntung segera ditengahi oleh Semar, namun juga berpuncak pada ngambeknya Semar dan mengajak para Punakawan dan Anoman untuk meninggalkan Astina, kembali ke Karang Kedompol mencari junjungan yang baru. Lalu apa bedanya dengan membiarkan Bagong tewas?
Pertanyaan serupa, kalau hanya untuk kemegahan dan kemewahan infrastruktur, kenapa tidak biarkan saja bangsa kita tetap pada genggaman bangsa Eropa? Toh pada saatnya mereka akan berikan kita infrastruktur yang memadai karena memang begitu kepentingan zamannya? Ngapain harus membebaskan Bagong kalau akhirnya Punakawan tetap pergi? Ngapain prok prok prok proklamasi kalau akhirnya hanya ganti penjajah?
Bukankah Simalakama? Sungguh membingungkan silang-sengkarut permasalahan Astinapura; mencintai pemerintah pasti berarti mengkhianati bangsanya, tidak loyal pada pemerintah dianggap tidak nasionalis.
Sosok junjungan baru telah akan ditemukan dalam diri Parikesit yang rupanya mengetahui hakikat Buah Simalakama. Anoman pun mengembalikan buah Simalakama ke kahyangan namun juga menimbulkan konsekuensi, Anoman pun hilang. Kemudian generasi-generasi Suta Kurawa, korban kericuhan Pandawa vs Kurawa, hasil pertarungan konspirasi Kresna vs Sengkuni bangkit melawan.
Para punggawa Astina telah terlalu lama larut dalam pertikaian hingga lupa menanamkan karakter ksatria pada generasi baru, para korban peperangan. Sehingga mereka melawan dengan ideologi-ideologi perlawanan sebisa yang mereka dapati. Mereka ingin mencari bentuk baru namun kepentok oleh senior-senior yang masih meneruskan tradisi lapuk hanya karena kenyamanan dan kemapanan picik.

Di tengah hiruk-pikuk, Dasayitmo pun bangkit! Keluar dari sudut panggung dan berperang melawan generasi-generasi baru.
Hingga akhirnya, semua rebah. Semua tak bersisa.
Suta Kurawa bangkit, mensucikan diri dari wacana-wacana asing yang dholalah dan mugholadhoh. Membentengi diri dengan
“Singgah-singgah kala singgah…” Mereka bangkit perlahan.
“Tan suminggah, Durgakala sumingkir”. Berjalan dengan tatapan jauh kedepan.
“Sing asirah sing asuku. Sing atan kasat mata. Sing atenggak sing awulu sing abahu”
Kemudian mengambil satu-satu batang-batang padi.
“Kabeh pada sumingkiro. Hing talenging jalanidi”
Dengan sikap Momong Dewi Sri; sikap Dewi Sri menggendong batang padi seperti menimang bayi. Para generasi emas ini berjalan, momong padi, momong kabudayan, kehidupan, memangku zaman, membawa Jawa, menggendong Nusantara.
Keibuan, feminin.
Untuk kemudian, membagikan batang-batang padi itu pada para penonton, membagikan kemanfaatan perlawanan mereka pada peradaban dunia.
“Singgah-singgah kala singgah. Tan Suminggah. Durgakala sumingkir…”
Bukan tepuk tangan yang membahana ketika pentas berakhir. Tepuk tangan yang bingung, penuh tanya. Pelan dan sesaat kemudian barulah pecah bahananya. Benarkah pentas ini berakhir? Seperti ada yang salah bila pentas ini berakhir di sini, sekarang. Karena memang tidak. Pagelaran “Mencari Buah Simalakma” tidak berakhir malam itu.
Karena memang tugas kita masih panjang. (MZ Fadil)