Meneroka Pluralisme Religius Gus Mus dan Cak Nun
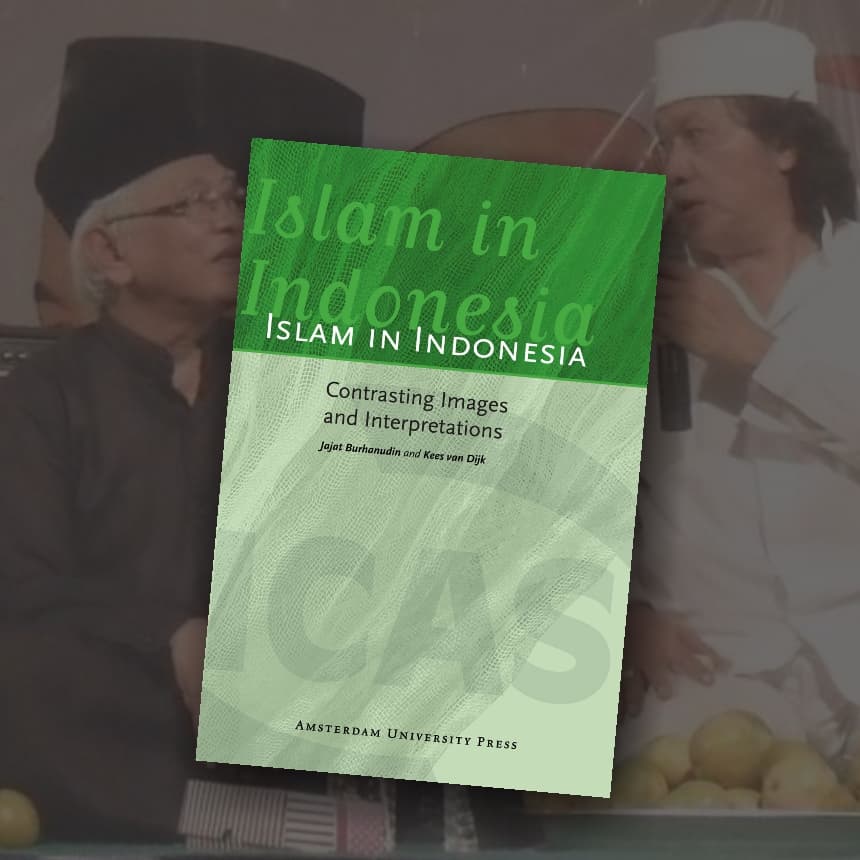
Praktik keberislaman di Indonesia relatif unik ketimbang negara lain. Islam berkembang di bumi Nusantara semenjak ratusan tahun lampau. Pendekatan dan penyebaran Islam berjalan dinamis seiring dengan tantangan zaman pada masa itu. Ilmuan sosial telah banyak menguak kenyataan demikian di mimbar akademik. Hal ini ditandai oleh segi kuantitas artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam tiga dekade terakhir.
Potret tersebut tak luput dari kejelian sejarawan, antropolog, dan sosiolog yang menyumbangkan pemikiran kritisnya terhadap transformasi keberislaman di Indonesia yang dihimpun ke dalam buku bertajuk Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations. Buku terbitan Amsterdam University Press tahun 2013 yang disunting Jajat Burhanudin dan Kees van Dijk ini menjadi dokumen historis era abad ke-21.
Buku setebal 285 halaman ini terdiri atas 14 tulisan ilmiah; antara lain tulisan Asfa Widiyanto, peneliti post-doktoral dari Philipps University Marburg, berujudul Religious Pluralism and Contested Religious Authority in Contemporary Indonesian Islam: A. Mustofa Bisri and Emha Ainun Nadjib. Ulasan berikut menitikberatkan karya ilmiah dosen sekaligus Wakil Direktur Pascasarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga itu.
Asfa mengawali kajian saintifiknya dengan kilas balik perkembangan Islam di antara abad ke-13 dan 14. Masa transisi itu diteropongnya karena menjadi titik balik penyebaran Islam lewat pendekatan tasawuf. Para sufi yang datang dari Timur Tengah pada perkembangannya dikontinuasikan dan digiatkan oleh Walisongo. Kesembilan wali itu mengajarkan nilai-nilai Islam tanpa pendekatan destruktif karena ia memahami peta sosiologi masyarakat Nusantara yang cenderung kooperatif.
Hal ini didukung pula keberterimaan masyarakat setempat yang telah memegang tradisi maupun kepercayaan luhur. Karenanya, pada tataran praktis, internalisasi Islam mengalami difusi dengan latar belakang tradisi dan kepercayaan setempat. Sinkretisasi demikian, dinyatakan Asfa, sebagai keberhasilan metode tasawuf yang sedemikian cair serta jauh dari kesan doktriner.
“Consequently, it can be said that Sufism or Islamic mysticism has gradually become an inextricable part of Indonesian tradition since the beginning of the Islamisation of the country. The phenomenon of the dissemination of Islam through Sufism, particularly from the thirteenth century onwards, concurred with the general state of the Muslim world at that time” (h.161).
Hibridisasi budaya setelah Islam masuk ke dalam sistem sosial masyarakat meniscayakan babak baru dalam historisitas bangsa Nusantara. Tahun-tahun setelah itu format politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan berangsur tumbuh dengan dan melalui kesadaran baru. Islam sebagai tatanan nilai universal, baik dalam perspektif etika maupun moral, berperan penting. Ini dapat dilihat dari ketersambungan takhta Majapahit ke Kesultanan Demak.
Konversi demikian acap dianggap sebagai keterputusan politik. Padahal, Raden Patah (Raja Demak) adalah putra kandung Raja Brawijaya V (Majapahit). Peralihan itu tentu menuai kecaman pelbagai pihak. Namun, kendala tersebut mampu ditengahi Sunan Kalijaga hingga sampai pada pemapanan struktur pemerintahan. Sirkulasi panjang ini berpengaruh signifikan terhadap segala konstelasi. Termasuk struktur pendidikan yang kini dikenal sebagai pesantren.
Istilah linguistik baru muncul seiring dengan perkembangan Islam. Asfa mencatat istilah kiai, ustaz, santri, kitab kuning, dan lain sebagainya sebagai produk dari masa ini. Ia berkembang divergen selama masyarakat gayung bersambut terhadap nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh bermunculan, termasuk A. Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Muhammad Ainun Nadjib (Cak Nun). Keduanya mempunyai relevansi geneo-teologis bila didedah lewat sudut pandang rekam jejak dakwah di abad ke-20.
Gus Mus dan Cak Nun mempunyai gerakan penyebaran Islam yang bertumpu pada derivasi semantik “saling menyelamatkan” dengan menggunakan media kesenian dan kesusastraan. Keduanya sama-sama berlatar belakang pesantren, meskipun berbeda tempat, namun kerap dianggap khalayak lintas usia sebagai kiai plus penyair.
Selain membentuk dan menyampaikan narasi Islam secara verbal di depan umum, keduanya juga aktif menulis sajak dan cerpen yang bernunsa ilahiah—pesan pragmatik isi karya sastra itu tak luput dari kesadaran transenden. Asfa mengistilahkan kecenderungan karya artistik dua kiai besar itu sebagai “sastra sufi”. Ia menguraikannya sebagai berikut.
“Bisri can be said to be a kiai who has strong leanings towards literature, whereas Nadjib is a man of letters whose literary works are profoundly inspired by the values and teachings in pesantren circles. The Sufi aspect of their writing is apparent in both their works; some people even see their literary works as part of the ‘Sastra Sufi’ genre (literature imbued with Sufi teachings), an inspiration that causes them to propagate more tolerant Islamic messages” (h.162).
Potret keberagaman di antara masyarakat Indonesia mesti disikapi sebagai anugerah Tuhan. Karenanya, penyampaian narasi Islam ke masyarakat sudah semestinya dilakukan secara ramah, bukan marah, sebagaimana pernyataan Gus Dur yang masyhur itu. Gus Mus dan Cak Nun, seperti ditekankan Asfa, menolak diskriminasi minoritas, betapapun bentuk praksisnya. Lingkup minoritas ini Asfa jelaskan lebih detail, yaitu mencakup agama maupun kepercayaan.
“Both scholars are also firm advocates of intra-Islamic pluralism, which was clearly shown by their defence of the Ahmadiyya Movement when this group was banned by the Majelis Ulama Indonesia (Council of Indonesian Religious Scholars, MUI). Both of them have also expressed their disapproval of perda syari’ah (regional regulations tinged with shari’a nuances)” (h. 167).
Bentuk otoritarianisme negara ataupun kelompok dominan yang memposisikan superior terhadap kelompok lain justru menggoyahkan stabilitas negara. Gus Mus dan Cak Nun cenderung berposisi sebagai oposisi bila melihat pelbagai bentuk ketidakadilan yang merugikan kelompok minoritas. Dengan demikian, keduanya memiliki kesepadanan sikap, yaitu membuka seluas-luasnya forum dialog antarkelompok agar tercipta suasana damai dan sejahtera.
Sikap asertif Gus Mus dan Cak Nun senada dengan semangat kesatuan dalam keberagaman (unity in diversity) yang disampaikan secara simbolik oleh Pancasila. Meskipun demikian, peneliti sekaligus penulis utama, Asfa, abai terhadap dimensi integral antara Islam dan Pancasila. Ia tidak mengkaji perspektif itu di dalam tulisannya. Padahal, aspek demikian begitu signifikan bila mempertimbangkan relevansi keduanya dalam konteks perkembangan dan praktik Islam di Indonesia.
Keterbukaan diskusi yang dimiliki Gus Mus dan Cak Nun membuka peluang besar bagi rekonsiliasi bangsa Indonesia yang dewasa ini semakin merenggang karena tersulut persoalan perbedaan pandangan. Sekalipun Gus Mus berlatar belakang NU, sedang Cak Nun berada di trasnsisi NU dan Muhammadiyah (Nahdlatul Muhammadiyin), keduanya memiliki kerendahan hati untuk dimintai pertimbangan sosial demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Terlepas dari kerumpangan gagasan Asfa, uraian akademis yang ia tulis telah berhasil meneropong praktik keberislaman kontemporer dengan mendudukkan dua variabel tokoh kawakan di Indonesia. Yang menjadi problem berikutnya adalah seberapa jauh generasi milenial menenun kembali kearifan kedua tokoh itu dengan dikontekstualisasikan dengan tantangan hari ini. Asfa sudah memulainya secara tertulis. Kita?








