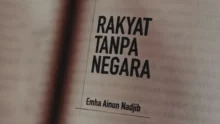Soto Handuk Celupan Sepatu Ala Chef Pipit Rochiyat
Pada medio Musim Panas 1983, Cak Nun, Gus Dur dan bersama beberapa orang rombongan mengunjungi Utrecht, Belanda. Pipit Rochiyat Kartawdijaja untuk pertama kalinya bertemu dengan Cak Nun di kediaman Adnan Buyung Nasution yang kala itu sedang menempuh studi di Belanda. Sebelum pertemuan itu, Pipit tidak begitu mengenal sosok Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Kelihaian Pipit dalam memasak adalah senjata andalannya untuk menaklukan Cak Nun dan Gus Dur untuk diakrabi saat itu. Kultur orang Indonesia yang sangat familiar dengan nasi dimanfaatkan betul oleh Pipit. Keju yang notabene merupakan salah satu makanan pokok di Belanda sudah pasti tidak akan diterima dengan baik oleh lidah orang Indonesia. Sedangkan beras di Belanda tidak bisa ditemui setiap hari.
Akal seorang Pipit sangat cerdik, jeroan babat yang dijual di toko daging milik orang Turki menjadi bahan masakan yang akan diolah oleh Pipit untuk menjamu rombongan yang berjumlah kurang lebih 50 orang saat itu. Bagi Pipit, cerita proses memasak Soto Babat ini sangat berkesan. Pipit bahkan menyebutnya sebagai Soto Handuk Celupan Sepatu. Mungkin akan terdengar aneh bagi kita. Tapi, itulah Pipit, gayanya yang nyentrik, sosok yang selalu mengenakan kemeja warna hitam, pengagum othak-athik-gathuk dengan gayanya yang cengengesan memang tidak akan mudah diterima argumen dan pendapatnya bagi orang yang baru pertama kali bertemu.
Daging babat diibaratkan oleh Pipit seperti handuk basah yang baru saja dicuci dan masih meneteskan air. Maka soto babat diibaratkan oleh Pipit seperti Soto Handuk Celupan. Lantas, kenapa ada kata sepatu? Pipit mengenang pada saat itu, di mana ia adalah satu-satunya orang yang pandai memasak, sehingga menyambut kedatangan rombongan Cak Nun, Pipit diminta untuk mengurusi persoalan konsumsi. Tenaga yang sangat minim, karena hanya ia sendiri yang sibuk di dapur, sementara ia harus segera memasak untuk sekitar 50 orang rombongan. Tidak ada waktu yang cukup banyak. Bawang putih yang menjadi salah satu bahan bumbu Soto Handuk Celupan itu disebar di lantai oleh Pipit, kemudian ia injak-injak bawang itu agar terkupas kulitnya.
Tentu saja adegan tersebut tidak diketahui oleh rombongan dari Indonesia yang sedang asyik berdiskusi di ruang tamu sembari menunggu hidangan makan yang siap disajikan oleh Pipit. Pipit menceritakan; “Mula-mula, ulek-ulekan asli Jawa diumpani ramuan pluralistik seperti kemiri, kunyit, sereh bubuk dan jahe. Plus Jahil. Jahil? Iyaah! Maksudnya? Guna efisiensi dan efektivitas memasak buat sekitar 40-50 orang, puluhan bawang putih yang saya beli di supermarket bule sekuler, lantas saya letakkan secara liberal di lantai. Setelah itu, saya injak-injek liberal urakan dengan sepatu produk Itali sekuler. Dan terkupaslah kulitnya. Baru diulek dengan ramuan pluralistik di atas, lantas ditumis di panci produk Kumpeni Kafir, dan diaduk-aduk liberal supaya jangan gosong kapiran. Tentu, walaupun kemasukan jurus-jurus pluralisme, liberalisme dan sekulerisme, menumismenya tetap harus menggunakan ‘feeling’. Ketika feeling bilang ya, baru air boleh diguyur ke dalam panci, menyusul kemudian daging jagalan sekuler bule dan babat halal Turki.”
Begitulah Pipit. Cak Nun dalam tulisan “Si Pipit Bajunya Hitam” menyebut Si Hitam kumal ndeso yang tak becus berdansa adalah salah satu potret tajam satu generasi yang lahir tidak oleh dirinya sendiri. “Pemberontakan” Pipit kepada rezim Orde Baru semasa ia hidup di Eropa merupakan sebuah bentuk kejujuran salah satu Putra Bangsa Indonesia. Di saat kebanyakan orang saat itu nurut kepada Soeharto agar tidak terganggu urusan ekonominya semasa belajar di eropa, Pipit berani untuk tetap idealis pada pendiriannya sendiri. Yang indah ia katakan indah, yang buruk ia sebut buruk. Tidak ada kemunafikan dalam diri Pipit.
Pipit memiliki pandangan tersendiri terhadap ajaran Marxisme, sehingga Pipit juga sering disebut oleh banyak orang sebagai salah satu aktivis kiri di Berlin Barat. Padahal, Pipit sendiri memiliki kenangan yang tidak terlupakan pada masa PKI berkuasa. Ayahnya merupakan salah satu musuh besar PKI saat itu, bahkan seringkali dituntut untuk mundur dari jabatannya yang saat itu memegang peranan penting dalam mengurusi Pabrik Gula di Ngadirejo, Kediri. Lingkungan pergaulan di Eropa yang mungkin membangun wawasan Pipit yang saat ini sering disebut oleh anak-anak muda sebagai pemahaman Liberal. Pipit sendiri pun mengakui, gaya tulisannya berubah setelah ia mengenal Cak Nun. Tulisan-tulisan Pipit sering menghiasi Media Massa PPI saat itu, tentu saja isu utamanya adalah perlawanan terhadap Orde Baru.
Awalnya Pipit mengakui tidak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran Cak Nun saat itu. Ketika datang ke Berlin Barat, di Forum Horizonte Berlin Barat, Cak Nun membacakan puisi-puisi karya beliau yang dipadukan dengan ayat-ayat Al Qur`an. Pipit merasa heran, karena menurutnya saat itu Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kongkret. Rezim Orde Baru yang begitu otoriter sangat mengancam keberlangsungan hidup Rakyat Indonesia, sehingga perlawanan yang dilakukan seharusnya adalah perlawanan yang kongkret, bukan dengan pembacaan puisi.
Selama kurang lebih sekitar 1 tahun Cak Nun di Belanda, seringkali Cak Nun tinggal di rumah Pipit. Bahkan buku “Dari Pojok Sejarah”, sebagian isinya ditulis oleh Cak Nun ketika tinggal di rumah Pipit. Dalam masa itu, Pipit seringkali terlibat diskusi yang sangat intens dengan Cak Nun. Diskusinya pun beragam, mulai dari persoalan Tuhan, Islam, Marxisme hingga cerita-cerita pewayangan. Kepulan asap rokok menghiasi ruangan diskusi Pipit dan Cak Nun, sama-sama penikmat rokok kretek, Pipit dan Cak Nun saling beradu pengetahuan. Jika sudah mencapai titik puncak diskusi, maka menu masakan Pipit adalah hidangan yang kembali menghangatkan suasana persahabatan keduanya saat itu. Kenangan lain yang juga berkesan bagi Pipit adalah, ketika Cak Nun ikut menemani Pipit untuk datang ke Konsulat Jenderal Indonesia di Berlin Barat saat itu untuk mengurusi Paspor milik Pipit yang mulai “disunat” masa berlakunya. Bahkan Cak Nun juga ikut memperjuangkan Istri Pipit yang saat itu juga berstatus stateless.
Pipit mengakui bahwa dirinya berubah dari kanan menjadi kiri ketika ia berada di Berlin Barat, yang notabene merupakan salah satu bagian dari Jerman Barat yang beraliran kiri saat itu. Hanya saja, karena Berlin Barat merupakan salah satu kota yang istimewa, pengambilan posisi kiri pun berjarak. Tetapi, Pipit di mata rekan-rekannya di Perhimpunan Pelajar Indonesia saat itu sudah dianggap sangat radikal. Bahkan kadar kesetiaan Pipit terhadap Pancasila sempat diragukan saat itu. Mungkin itulah salah satu penyebab mengapa Paspor milik Pipit kemudian diperpendek masa berlakunya, bahkan akhirnya dicabut oleh Pemerintah Indonesia.
Kehadiran Cak Nun sendiri saat itu sangat disyukuri oleh Pipit, persinggungannya dengan Cak Nun saat itu, Pipit mengakui diajak kembali untuk mengenali Islam. Bagi Pipit, Cak Nun adalah sosok penjabar dan pelaksana Islam yang sesungguhnya. Cak Nun adalah sosok yang sangat terbuka, tanggap dan sudi menerima hal-hal yang dianggap baru dan bermanfaat bagi Indonesia. Sebagai pemeluk Islam, Pipit mengakui bahwa Cak Nun tidak hanya merangkul orang Islam saja. Maka, Pipit merasa sangat cocok dengan Cak Nun, apalagi saat itu mereka sama-sama tidak setuju dengan rezim Orde Baru yang sedang berkuasa. Bagi Pipit, Cak Nun adalah sosok yang merepresentasikan Islam. Cak Nun sangat keras melawan Soeharto, tetapi tidak berkurang kritisnya meskipun Gus Dur menjadi Presiden di Indonesia.
Bagi Pipit, Cak Nun hari ini sama seperti Cak Nun yang dikenalnya pada tahun 1983, seorang jembatan bagi segala masakan. Yang menyukai daging kambing, silahkan masak gulai kambing, yang menyukai babi guling silahkan memasak babi guling, Pipit memberi amsal. Bagi Pipit, mau Kambing, Babi, Udang, Sapi apapun itu pasti ada manfaatnya. “Yang penting, bagaimana para kambing, udang atau babi memainkan jurus fastabiqul khoirot, berkompetisi dalam menegakkan kebajikan. Kalau perlu, secara membabi buta, urakan obralan dan liberal-liberalan dan tetap tegar ketika dikambing-kambinghitamkan”, begitu kata Pipit.