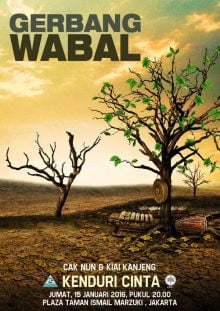Meneguhkan Jati Diri Budaya Manusia Nusantara
Arus besar globalisasi seolah tak terbendung. Seluruh instrumen kehidupan di-aklimatisasi sedemikian rupa menyesuaikan dengan gelombangnya. Sebenarnya peralihan atau pergantian peradaban dan kebudayaan adalah keniscayaan dalam perjalanan dunia. Namun, hegemoni dan penguasaan atas pihak lain adalah sesuatu yang tentunya tidak bisa dijustifikasi dan disimplifikasi sebagai ekses. Manusia adalah manusia, yang diciptakan Tuhan sebagai masterpiece-Nya, tentunya bukan untuk menjadi “sekadar” onderdil bagi kepentingan pihak lain.
Setelah usainya Perang Dunia II, yang berlangsung adalah apa yang dikenal dengan Perang Dingin. Uni Soviet yang menandai dirinya dengan Glasnost Perestroikanya teriris menjadi Rusia. Yugoslavia dan semenanjung Balkan terkapling-kapling. Berlanjut pada geger Irak-Iran hingga prithilan-prithilan Arab Spring. Perlahan namun pasti terlihat, peta konflik dan benturan horizontal mulai bergeser ke arah Ekuator. Kesuburan di area ekuator yang ditopang dua musim adalah lumbung pangan dunia. Peak Oil Theory harus menyerah pada realitas bahwa ternyata pada ujung lorongnya, manusia tidak bisa makan uang dan minum minyak. Keberlebihan uang dan minyak tidak berarti apa-apa ketika dihadapkan pada kemungkinan kelangkaan bahan pangan.
Peta besar Uni Soviet, Balkanisasi, Krisis Teluk dan Arab Spring menunjukkan pola dasar yang hampir seragam. Yakni meruntuhkan perekat kenegaraannya, sambungan-sambungan pemersatu kebangsaannya. Menganalogikan pada konstruksi ketekniksipilan, sambungan-sambungan pada sebuah struktur adalah titik-titik vital pada kestabilan struktur tersebut. Ialah yang merupakan titik temu dan titik sambung masing-masing elemen struktur, seperti misalnya balok dan kolom sebagai rangka utama strukturalnya. Bukan berarti setiap elemen struktur tidak penting, namun melemahkan sambungan-sambungannya jauh lebih efektif bagi keruntuhan struktur tersebut daripada menyerang satu-persatu elemen strukturnya. Pelemahan pada titik vital ini salah satunya adalah dengan menambah berat sendiri pada elemen-elemen strukturnya sehingga tidak mampu ditahan oleh sambungan-sambungannya (weakened joint), yang secara integral berpengaruh pada stabilitas struktur tersebut.
Pada konteks sosio-antropologis sebuah peradaban, penambahan berat sendiri elemen kebangsaan adalah bahasa lain dari “membesarkan” dan “menyala-liarkan” egoisme sempit (ananiyah) dan kemau-menang-sendirian sehingga melemahkan perekat kebangsaannya (tidak mampu ditahan oleh perekat kebangsaannya, lebih tepatnya). Elemen kebangsaan bisa saja berupa etnis/suku, wilayah, agama dan unsur antropologis lainnya. Itulah api yang digunakan untuk membakar tumpukan sekam ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, kerapuhan budaya, maupun kekejaman politik.
Soviet yang pada saat itu mencoba merekatkan kembali keutuhannya dengan Glasnost Perestroika, tidak mampu membendung tuntutan kemerdekaan diri dari wilayah federasinya yang sebagian besar berafiliasi pada etnis dan golongan sendiri-sendiri. Wafatnya Joseph Broz Tito yang menjadi perekat utama keutuhan Yugoslavia yang multi rasial, adalah kesempatan besar bagi etnis-etnis di dalamnya untuk menunjukkan dirinya, dari etnis Albania, Serbia, Bosnia, dan etnis lain di dalamnya. Irak, Iran, dan Kuwait pada krisis Teluk terjerumus pada perang panjang ketika kesombongan suku membesar dan ke-mau menang sendiri-an Sunni-Syi’ah ditiupkan (kembali). Arab Spring di awal 2000-an juga dinyalakan dengan konflik politik sektarian dan isu Sunni-Syi’ah di atas sekam hedonisme dan ketimpangan sosial ekonomi serta kerapuhan budayanya. Dari semua itu, yang tersisa hanya puing dan kebanggaan semu yang memusnahkan kebanggaan bersama sebagai sebuah bangsa. Kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang menerima keragaman dan keberbedaan elemen di dalamnya adalah perekat utama sebuah bangsa.
Pada konteks Indonesia, sebuah negara kepulauan di mana hampir 10% bahasa di dunia ada di dalamnya, tampak makin jelas terlihat kebanggaan bersama sebagai sebuah bangsa tererosi dan terdegaradasi secara serius oleh pola pemikiran baru bernama modernisme, yang berkelindan dengan megalomania sempit masing-masing golongan. Arus besar modernisme dan globalisasi sejak awal Abad Pencerahan di Eropa, telah mengubah cara pandang, sudut pandang, titik dan pijak pandang orang Indonesia tentang segala sesuatu, termasuk tentang diri dan bangsanya, dengan seluruh elemen budaya dan peradabannya. Dalam bahasa matematis, geometri berpikir manusia Nusantara bergeser (shifting) mengikuti arus geometri Renaissance dari Eropa. Mungkin karena inilah, setiap opresi dan hegemoni suatu bangsa atas bangsa lain ditandai dengan mengganti kalendernya.

Suatu malam di abad XV, di sebuah kota di Italia, seorang seniman sekaligus ilmuwan bernama Leonardo da Vinci sedang melakukan riset detail dan mendalam untuk menyelesaikan salah satu tugas yang dibebankan kepadanya. Menyelesaikan lukisan The Last Supper. Butuh bertahun-tahun Da Vinci menyelesaikan lukisan yang fenomenal tersebut, yang kemudian ditemukan bahwa ia dilukis dengan patuh pada elemen-elemen geometris modern. Sketsa-sketsa lukisan ini diisi dengan bentuk dasar geometris, mulai dari segitiga, persegi, lingkaran, lengkap dengan metanarasi perspektif geometri modern.

The Last Supper mengisahkan sebuah fragmen kelam dalam kehidupan Yesus menjelang mitologi penyalibannya. Ekspresi 13 sosok di dalamnya, penataan dan perspektif ruangannya menyampaikan suasana kelam pada perjamuan terakhir tersebut. Konon, Da Vinci melakukan pengukuran detail raut wajah, keriput, jarak mata pada setiap emosi yang diwakili setiap sosok di dalam lukisan tersebut.
***
Di waktu yang sama Da Vinci melukis The Last Supper, di tanah dewata, Bali, seniman lainnya yang namanya tak pernah tercatat dalam sejarah juga menyelesaikan sebuah lukisan lain yang bertajuk Smaradhana. Lukisan yang saat ini menjadi koleksi Museum Leiden juga memiliki kisah sendiri sebagaimana The Last Supper. Namun berbeda dengan The Last Supper yang berkisah tentang satu potongan fragmen saja, Smaradhana berkisah tentang narasi panjang. Di dalam lukisan tersebut, bisa kita temukan potongan gambar ruang tidur Dewi Ratih, istri dari Kama. Selanjutnya ada potongan gambar lain di mana Dewi Ratih menggerai rambutnya sebagai tanda berduka, berjalan ke tempat Kama terbakar karena bara mata Dewa Siwa. Ada pula potongan fragmen Dewa Siwa di dekat pepohonan bersama punggawanya, Nandhiswara dan Mahakala. Sementara di bagian tengah lukisan, dilukiskan Dewi Ratih dan dayang-dayangnya tengah dilalap api.
Yang menarik adalah, Smaradhana dilukis tidak dengan “pakem” geometri modern sebagaimana The Last Supper. Kalau kita “memaksakan” diri dengan menggunakan cara untuk melihat geometris yang konvensional, maka yang bisa kita temukan adalah ketidakberaturan, keacakan, ketidaktentuan, dan miskin aturan normal seni lukis modern. Secara sepintas, dari lukisan Smaradhana bisa kita temukan persambungan kuat dengan salah satu kekayaan intelektual budaya Nusantara, yakni batik. Smaradhana dan batik memiliki pola yang seragam.

Dan hampir lima abad setelahnya, matematika modern menemukan harta karun terpendamnya berupa geometri revolusioner yang diformalisasi oleh matematikawan Benoit Mandelbrot, yang membuka kacamata kuda geometri konvensional bahwa ada simetri lain di alam yang berbeda dengan geometri “modern”. Ialah yang dikenal dengan “geometri fraktal”. Dan yang mengejutkan, pola geometri fraktal inilah yang ternyata ditemukan pada lukisan Smaradhana dan lukis batik di Nusantara. Bayangkan, di abad XV bersamaan dengan Renaissance di Eropa, ilmuwan dan cendekiawan Nusantara telah menerapkan geometri fraktal pada karya ekspresi budayanya. Bagaimana metode, catatan maupun pola penerapan geometri fraktal saat itu di Nusantara, adalah ruang eksplorasi sangat lebar yang menawarkan diri untuk dijelajahi bersama.
***
Dari dua kisah seni lukis diatas, saya khususnya, merasa sangat malu dan bersalah telah (pernah) merasa minder akan pusaka warisan leluhur kita. Dan perasaan malu dan bersalah itu semakin besar ketika mengetahui bagaimana Borobudur (dan candi-candi lainnya) terbangun melalui sistematika dan metode yang ternyata di luar “pakem” matematika modern, namun patuh pada “pakem” lain secara saintifik, yang dikenal dengan “otomata selular”. Belum lagi melihat bagaimana hierarki birokrasi kerajaan-kerajaan Nusantara, kekayaan luar biasa kuliner Nusantara, pola matematis nada-nada musikal lagu tradisional Nusantara. Ah, betapa klaim kemajuan peradaban kita saat ini dibanding leluhur kita Nusantara, ternyata sangat prematur dan layak dipertanyakan.
Hal tersebut hanya pada pola matematis ekspresi peradaban Nusantara saja, belum lagi mendalami filosofi dan cara hidup orang Nusantara dalam interaksinya dengan elemen lain, sehingga termanifestasi pada ekspresi budaya Nusantara seperti misalnya batik, ukiran, anyaman, bangunan, kuliner, bahasa, dan ekspresi lainnya. Pendekatan matematis terhadap ekspresi budaya kongruen dengan memetakan genetika pada sebuah untaian DNA. Hokky Situngkir dalam bukunya Kode-kode Nusantara menyebutkan bahwa apa yang terlihat sebagai budaya adalah abstraksi kognitif kolektif dari masyarakat lintas generasi. Meneropong ekspresi budaya Nusantara hanya sebagai benda atau kearifan lokal semata, sama maknanya dengan mengeliminasi data dan informasi penting di baliknya. Matematika sebagai tawaran sains modern dalam memetakan kekayaan ekspresi budaya Nusantara memperlihatkan betapa erat, rigid, dan mengagumkan eratnya kekerabatan satu sama lain. Di hadapan godaan data faktual terhadap informasi matematis semacam ini niscaya membangunkan kembali rasa kebersatuan tunggal ika, sesama Nusantara. Di ujungnya, kita bisa menemukan betapa tak ternilai persatuan yang terbangun oleh keragaman (bukan keseragaman), sekaligus betapa sia-sianya keterpecahan, keterkepingan yang didirikan atas narsisme bahwa kita berbeda.
Kebanggaan kita atas pusaka masa lalu dari leluhur kita inilah yang saat ini berada pada titik nadir, padahal ialah salah satu perekat kebangsaan dan sambungan kenegaraan kita sebagai sebuah kesatuan, kebersatuan, dan kemenyatuan. “Penjajahan” panjang beratus tahun atas cara dan konstruksi berpikir sepertinya menunjukkan hasilnya di tahun-tahun belakangan ini. Juri Lina, seorang penulis berkebangsaan Estonia, menyebutkan bahwa ada tiga langkah melemahkan sebuah bangsa, yaitu (1) Kaburkan sejarahnya, (2) Hancurkan bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan keberadaannya, dan (3) Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan menanamkan stigma bahwa leluhurnya bodoh dan primitif.
Mungkin inilah yang tersirat di balik tulisan tangan Emha Ainun Nadjib “Jati diri Bangsa Indonesia yang merupakan benih masa depannya tersembunyi di kedalaman nilai benda-benda, yang sebenarnya bukan sekadar benda-benda. Kita wajib menjaganya sampai kapan saja kemudian menyelami dan menggali rahasianya sampai Allah mempertemukan kita dengan Indonesia. Kita menegakkannya, meneguhkannya, untuk ketetapan semesta anak-cucu kita”

Rujukan:
*) berdasar data di ethnologue.com, tercatat 707 jenis bahasa bahasa (dari total 7097 bahasa yang dituturkan di dunia) terdapat di kepulauan Nusantara ini.
*) Situngkir, H. 2016. “Kode-kode Nusantara”: Expose (PT. Mizan Publika)