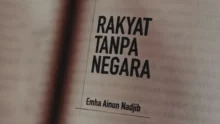Memilih Ibu, Meninggalkan Bapak
Ta’qid“...rakyat optimis cahaya Matahari akan tak lagi digerhanai untuk mereka nikmati. Ternyata tidak terjadi. Sama sekali tidak terjadi. Bahkan sudah empat Pemerintahan berlangsung, Gerhananya makin menjadi-jadi. Dan satu dua tahun terakhir ini adalah puncak Gerhana...”
Dua puluh tahun yang lalu beredar lagu dan narasi tentang kasus Gerhana Matahari, yang diakhiri dengan rekomendasi agar orang-orang berjuang untuk Menyorong Rembulan.
Ini amsal. Tuhan tidak merasa malu untuk membikin perumpamaan dengan menyebut nyamuk atau apapun yang kebanyakan manusia meremehkannya. Menyorong Rembulan adalah amsal yang mengumpamakan Matahari berfungsi seperti Tuhan, Rembulan berposisi Raja atau Pemerintah, sedangkan Bumi adalah Rakyat suatu Negeri, Negara atau Kerajaan.
Tuhan melimpahkan kesejahteraan ibarat matahari memancarkan sinar. Pada siang hari sinar itu langsung menaburi Bumi dan memandikan penghuninya. Jika malam tiba, Rembulan memantulkan sinar itu, sehingga Bumi tidak diselimuti kegelapan.
Kenapa Gerhana? Kenapa Rembulan menutupi Matahari, menghalangi sinarnya untuk merahmati Bumi? Kenapa Pemerintahan demi Pemerintahan di Negeri ini hampir selalu membangun Gerhana? Hampir selalu memonopoli cahaya Matahari, padahal pada hakikinya itu adalah hak Bumi?
Pernah ada era di mana Rembulan seakan bisa disorong, sehingga semua rakyat optimis cahaya Matahari akan tak lagi digerhanai untuk mereka nikmati. Ternyata tidak terjadi. Sama sekali tidak terjadi. Bahkan sudah empat Pemerintahan berlangsung, Gerhananya makin menjadi-jadi. Dan satu dua tahun terakhir ini adalah puncak Gerhana.
Maka sebagian kaum muda rakyat Negeri ini berkumpul di arena ini, juga di banyak arena-arena lainnya di berbagai wilayah. Untuk membikin semacam Tabung Cahaya yang persentuhan dan persambungannya hanya ke Langit dan Alam.
Mereka sudah mengalami, meneliti, merasakan, dan meyakini, sudah ‘ainul yaqin, ‘ilmul yaqin dan haqqul yaqin bahwa tradisi Gerhana itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kesadaran rakyat tidak bisa diservis lagi, mental kaum cerdik pandai di strata menengah harus turun mesin, dan peradaban politik harus ganti baru sama sekali secara menyeluruh.
Maka mereka selalu rindu untuk berhimpun di arena di mana mereka menjadi bagian dari Tarian Tali-tali Cahaya antara Langit dengan Bumi. Apalagi semakin hari semakin bulan semakin tahun semakin banyak yang berhimpun bersama mereka.
Tidakkah mereka sebenarnya sedang melarikan diri dari kenyataan?
O tidak. Mereka adalah janin-janin masa depan, yang bahkan sekaligus sedang belajar men-janin-i zaman dan sejarah.
Tidakkah mereka sedang bersembunyi dari kewajiban untuk menjunjung rakyatnya dan menyelamatkan negaranya?
O tidak. Mereka adalah para pengambil keputusan untuk bergabung dengan terbitnya Fajar serta mengolah cahayanya. Karena mereka sudah meninggalkan keremangan Senja yang segera memasuki kegelapan Malam.
Tapi apa hubungannya dengan Buah Simalakama?
Ibu adalah Alam. Bapak adalah Pemerintah. Rakyat, dalam simbolisme ini, adalah anak-anak.
Si Bapak itulah yang menghalangi sampainya sinar matahari ke anak-anaknya. Yang merampok, menghimpun dan menumpuk-numpuk sendiri cahaya kesejahteraan dari Tuhan.
Si Bapak itulah kolonialis-imperialis terhadap anak-anaknya sendiri. Si Bapak itulah diktator yang memaksakan kemauan dan aturan egoisnya ke anak-anaknya sendiri. Si Bapak itulah kapitalis, penghisap darah, penyedot kekayaan bumi, pengotor udara, lintah di darat maupun di laut.
Si Bapak itulah juara tipu daya, jagoan muslihat, malaikat kebohongan, seniman topeng, rasul dusta, iblis berlagak penggembala, dajjal berpakaian pendeta dan ulama, ya’juj ma’juj yang tak tahu apapun kecuali siang malam mengeruk keuntungan dunia.
Maka kaum muda yang berhimpun di arena itu sudah mengambil keputusan pasti: meninggalkan Bapak, memilih Ibu.