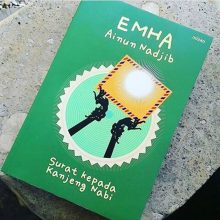Lembah Masa Depan

Tampaknya karena mendengar tema ‘Yogya Memangku Indonesia’ anak-anak saya menjadi lupa dinginnya udara. Hati yang menyala karena disulut oleh suatu pengharapan, serta pikiran yang bergolak, menjadikan hangat tubuh mereka.
Anak-anak itu memang “teman berkhayal” saya hal Yogya.
Kata ‘Yogya’ sangat sensitif bagi mereka. Menggetarkan hati dan menaikkan adrenalin. Ketiga-tiganya putra asli Yogya, cucu Perjanjian Giyanti, prajurit cintanya Kanjeng Pangeran Mangkubumi, cicit murid spiritualnya Pangeran Sambernyowo Mangkunegaran tapi pendorong utama cita-cita masa depan cakrawala jauh ke depan Peradaban Jawa Abadi.
Kalau kami jagongan dan berkhayal tentang masa depan Yogya, bisa semalaman atau sesiangan atau sekurang-kurangnya berjam-jam. Tidak terbatas pada eksplorasi tafsir tentang keistimewaan Yogya. Tentang beda antara Yogya Kota Budaya dengan Yogya Ibukota Kebudayaan Indonesia.
Tentang bentangan lembah dan tlatah selatan Merapi di mana para Auliya rutin mengadakan pertemuan sejak berabad-abad silam, sejak jauh sebelum Ratu Shima dan Pangeran Padmo hingga Syekh Maulana Maghribi dan Panembahan Bodho. Tentang wilayah koordinasi Buwana Baginda Jibril hingga logika dan kawaskitan Magersari yang tidak bisa dipahami oleh cara berpikir peradaban modern.
Beribu dimensi tematik Yogya yang skala besar maupun kecil. Yang substansial maupun yang ilustrasional. Yang prinsipil maupun yang romantik. Yang kultural maupun spiritual. Yang samar-samar maupun yang bersahaja. Yang bumi maupun langit. Dan sudah saya bayangkan wilayah-wilayah tugas yang perlu dieksplorasi oleh anak-anak ini.
Ah, kok anak-anak. Bukan. Bukan anak-anak. Gendon, Beruk maupun Pèncèng masing-masing sudah bekerja, sudah lumayan mandiri. Belum pada kawin, tapi pikiran dan mental mereka relatif sudah dewasa dan cukup matang. Saya kenal baik Ibu Bapak dan keluarga mereka. Mereka juga mengetahui dan tidak ada masalah bahwa putra-putra mereka sudah saya anggap dan perlakukan sebagai anak-anak saya sendiri.
Mereka bukan anak yatim yang saya tampung, saya kasih tempat dan sandang pangan dari saya. Mengangkat mereka sebagai anak bukan jasa, apalagi kehebatan. Ini hanya resonansi dari silaturahmi, pergaulan yang tak sengaja, meskipun Tuhan pasti menyengajainya. Mungkin semacam ketersambungan gelombang, pertalian alam pikiran, perjodohan ide, gagasan, aspirasi, visi dan pengharapan kemanusiaan dan kemasyarakatan.
Ketiga pemuda jomblo itu juga tidak bertempat tinggal di rumah saya. Kami mungkin semacam ‘geng’, meskipun jarak usia kami sangat jauh. Saya yang sudah KTP-abadi ini terjebak untuk tidak punya kesempatan untuk merasa tua, karena semakin tambah umur rasanya semakin banyak pengharapan-pengharapan hidup yang tidak tercapai.
Tentu maksud saya bukan pengharapan pribadi, melainkan dambaan-dambaan sosial. Sejak muda saya bangga menjadi manusia Indonesia, dan memiliki perasaan sangat khusus sebagai orang Yogya. Di masa remaja dan muda saya dulu saya menyangka bahwa kelak kalau usia saya sudah lewat 60 tahun, Indonesia akan sudah benar-benar moncer dan mencahayai seluruh dunia. Secara alam, tanah air kita terkaya dibanding negeri manapun. Dan kalau melihat manusia-manusia Indonesia, yang multi-bakat, yang rata-rata memiliki kecerdasan istimewa, yang ketangguhan mentalnya sulit ditandingi, yang kaya raya kebudayaannya serta jam terbang peradabannya telah melewati puluhan abad sehingga sulit disepadani oleh bangsa manapun di bumi.