Kita ini Penggembala atau Gembalaan
Berbicara tentang kepemimpinan, ada idiom-idiom budaya Jawa karya para Wali yang bisa dipegang. Falsafah kepemimpinan dalam angon bebek (menggembalakan bebek) atau angon wedhus (menggembala kambing), misalnya, si penggembala selalu berada di belakang. Posisi ini identik dengan kepemimpinan dalam shalat berjamaah, yakni para perempuan selalu berada di belakang. Perempuan adalah penggembala dalam konteks pemimpin yang angon (menggembala) kaum laki-laki yang berada di depannya.
Falsafah kepemimpinan bocah angon (penggembala) tersebut, dapat kita temui di tembang Ilir-ilir.
Tugas yang sedang diemban oleh bocah angon dalam tembang Ilir-ilir tersebut, adalah memanjat pohon belimbing yang bergigir lima. Dalam situasi sekarang dapat diartikan memanjat pohon reformasi, pohon demokratisasi, atau apapun istilah yang kita pakai. Lunyu-lunyu yo penekno. Selicin apa pun, terus harus kita panjat. Jatuh melorot lagi, naik lagi, melorot lagi, naik lagi.
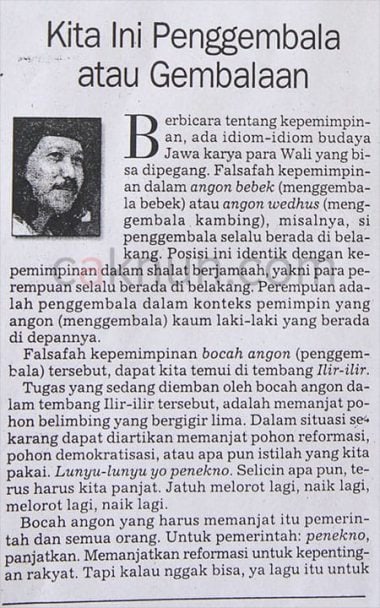
Bocah angon yang harus memanjat itu pemerintah dan semua orang. Untuk pemerintah: penekno, panjatkan. Memanjatkan reformasi untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau nggak bisa, ya lagu itu untuk rakyat: peneken. Panjatlah sendiri. Sementara upayakan kemandirian dan mengurangi semaksimal mungkin ketergantungan terhadap perekonomian makro yang dikelola oleh pemerintah. Tingkatkan etos kerja dan watak swasta. Tingkatkan akses ke alam dan jasa.”
Adapun blimbing bergigir lima, maknanya boleh dimultitafsirkan, bisa Pancasila, lima rukun Islam, bisa shalat lima waktu, yang pasti bukan mo-limo: maling (mencuri), madat (narkoba), minum (mabuk), madon (melacur), dan main (judi).
Lantas, apa makna bocah angon yang selalu berada di belakang? Begitu pula dengan para wanita yang selalu berada di belakang ketika shalat berjamaah? Makna simboliknya, sekali lagi, adalah bahwa kaum wanita sebenarnya sedang angon atau menggembalakan kaum laki-laki, sebagaimana dalam shalat jamaah itu. Bayangkan bila format dalam shalat itu dibalik, yakni perempuan di depan, sebagai imam, dan kaum laki-laki di belakang sebagai makmum. Bisa dipastikan suasananya akan menjadi kacau balau, karena para makmum—yang terdiri dari kaum laki-laki—tidak bisa khusyu’ dalam shalatnya, lantaran sibuk memandangi kaum perempuan yang di depannya. Begitulah, perempuan, pada hakikatnya adalah pemimpin.
Bocah angon bersedia berada di belakang. Artinya kita membutuhkan manusia yang tidak rakus kekuasaan, mau menjadi rakyat biasa, mau berada di belakang-belakang saja. Manusia yang punya kebesaran jiwa sebagai manusia, sehingga meskipun ‘hanya’ menjadi manusia biasa, ia tidak berpenyakit jiwa apa-apa. Bukan manusia kerdil yang memerlukan jabatan, otoritas politik, dan popularitas untuk merasa dirinya besar. Jika sudah matang ‘ke-belakang-an’nya seperti ini, justru orang macam inilah yang paling siap tampil di depan.
Ciri bocah angon yang lain adalah pada habitat budaya anak gembala. Egaliter, bersahaja, siap tidur di bawah pohon, siap ber-geluteh dengan kotoran kerbau. Bukan priyayi feodal, bukan anak Mami yang necis, bukan hedonis yang gaya hidupnya memerlukan pengorbanan ekonomi orang banyak. Orang semacam ini yang paling siap berpuasa dari KKN, nothing to loose untuk tidak maling uang negara.
Tapi mungkin yang kita miliki sekarang belum sebagai bocah angon. Yang kita punya bukan penggembala kerbau, melainkan kerbau.
(Dokumentasi Progress: Tulisan Cak Nun pada kolom Refleksi Harian Republika, 29 Juli 2001)



